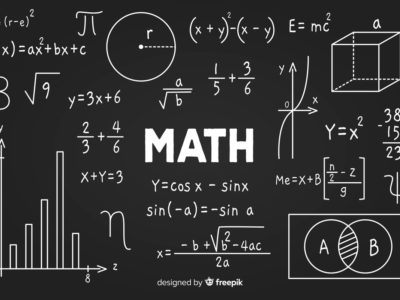Al-Anbiyā’: 23-24
لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ
“Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.”
Pada ayat ke 23 ini, terdapat beberapa poin penting, antara lain:
Pertama: Ayat ini mencakup aspek rububiyyah (ketuhanan) dan ubudiyah (penghambaan). Hal ini direkam secara apik oleh Syaikh Ibn ‘Atha`illah dalam al-Hikam dengan sebuah ungkapan:
تشوفك الى مابطن فيك من العيوب خير من بشوفك الى ماحجب عنك من الغبوب
“Obsesimu untuk mengenali keburukan dalam dirimu, lebih baik dibanding upayamu untuk menyingkap pengetahuan-pengetahuan gaib”
Apa sebab? Karena mengenali “keburukan dalam diri” adalah bagian dari ubudiyyah. Sementara mendapatkan “pengetahuan gaib” merupakan anugerah dari Tuhan (rububiyyah). Di sisi lain, insan yang mengenali keburukannya akan berupaya memperbaiki diri, sementara mereka yang beroleh pengetahuan batin boleh jadi terserang rasa angkuh dan merasa suci. Sebab itu, menunaikan tugas penghambaan tentu lebih baik ketimbang mendikte apa yang hendak diperbuat Tuhan (rububiyyah).
Kedua: Dalam Mafātih al-Ghaib, Imam ar-Razi meberikan delapan alasan tentang lā yus`alu ‘ammā yaf’alu (Dia [Allah] tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan), tetapi saya ingin meringkasnya begini: Tuhan adalah sebab, penciptaannya merupakan akibat. Suatu “sebab” tentu tidak memerlukan sebab lain, lantaran kebutuhan akan sebab hanya layak bagi “akibat”. Karena Tuhan bukan “akibat”, niscaya Dia tidak memerlukan “sebab”. Jadi mempertanyakan “kenapa Engkau mencipta seperti ini?” menjadi tidak tepat ditujukan kepada Tuhan.
Analogi sederhana, apakah tepat manakala kita bertanya, “kenapa engkau mencuri?” kepada seseorang yang tidak sekalipun pernah melakukan pencurian? Renungilah permisalan ini.
Lumrahnya, seorang raja yang memiliki kekuasaan atas kerajaannya, tidak boleh ditanya mengenai apa yang ia lakukan di kerajaannya, lalu pantaskah mempertanyakan hal tersebut kepada Sang Maha Raja di alam semesta?
Ketiga: Boleh saja Anda bertanya, “Sejauh mana kita tidak diperkenankan mempertanyakan penciptaan yang dilakukan Tuhan? Bukankah dalam al-Baqarah ayat 30 terdapat cerita tentang malaikat yang mempertanyakan keputusan Tuhan menjadikan manusia sebagai khalifah dibumi. Qālū a taj’alu fīhā may yufsidu fīhā wa yasfikud-dimā`, wa naḥnu nusabbiḥu biḥamdika wa nuqaddisu laka (Para malaikat bertanya: Apakah Engkau hendak menjadikan mereka yang merusak bumi dan saling menumpahkan darah [sebagai khalifah], sementara kami selalu bertasbih memuji-Mu dan mensucikan-Mu?).”
Berikut jawaban kami: (a) kata lā yus`alu sebenarnya tidak sekedar berarti “Dia (Allah) tidak ditanya”, melaikan yang dimaksud adalah “Dia (Allah) tidak dimintai pertanggungjawaban”. Apa sebab Dia tidak dimintai pertanggungjawaban? Karena Tuhan adalah penguasa yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih daripada-Nya. Sementara pertanggungjawaban hanya layak bagi diminta dan diserahkan kepada sesuatu yang levelnya lebih tinggi. Dalam bahasa yang lebih gampang, tidak ada satu pengadilan pun yang memiliki hakim lebih tinggi dibanding Tuhan, karena itu Dia tidak perlu diminta pertanggungjawaban atas apapun yang diciptakannya.
(b) Mempertanyakan tentang penciptaan yang dilakukan-Nya boleh-boleh saja, bahkan ayat 30 dalam surat al-Baqarah yang disebutkan itu merupakan bukti naqli yang jelas tentang hal tersebut. Lalu, sejauh mana hal itu diperbolehkan? Asalkan pertanyaan tersebut tidak diniatkan untuk menghilangkan tanggung jawab manusia, sebagaimana tersebut dalam penggalan ayat setelahnya: wa hum yus`alụn (tetapi merekalah yang dimintai pertanggungjawaban). Seperti, tatkala malaikat mempersoalkan tentang posisi khalifah di bumi, mereka tidak sedang mendakwa atau menganggap Tuhan keliru, melainkan pertanyaan tersebut demi mengetahui hikmah (li thalab al-hikmah). Hal itu terbukti ketika nabi Adam As sanggup menuntaskan tantangan untuk menyebutkan nama-nama, sementara malaikat tidak mampu melakukannya; lalu para malaikat merasa puas dan mengakui ketidaktahuan mereka dengan kata-kata subḥānaka lā ‘ilma lanā illā mā ‘allamtanā, innaka antal-‘alīmul-ḥakīm (Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana). Tetapi, jika pertanyaan tentang penciptaan yang dibuat Allah ditujukan agar mereka lepas dari tanggung jawab (li an lā yus`ala), inilah yang tidak diperkenankan. Seperti seseorang yang melakukan maksiat lalu bertanya, “Tuhan, kenapa Engkau menakdirkanku terjebak dalam kubangan maksiat ini?!” namun tujuannya adalah agar kesalahan itu disandarkan pada Tuhan, dan dia terlepas dari tanggung jawab perbuatannya. Semoga kita dilindungi dari pikiran picik seperti ini.
Sungguh baik kita renungi tulisan Shahib al-Hikam dalam Lathā`if al-Minan:
ولا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولايطالب نفسه لله, فذلك حال الجاهلين الذين هم لم يفهم عن الله…. والمؤمن ليس كذلك, بل المؤمن يطالب نفسه لربه ولايطالب ربه لنفسه…
“Janganlah engkau termasuk orang-orang yang menuntut Allah agar sesuai dengan nafsunya, bukan memaksa nafsunya agar sejalan dengan perintah Allah; hal itu merupakan kondisi orang-orang bodoh yang tidak memahami apapun tentang Allah… Sementara orang mukmin tidak demikian, mereka adalah orang yang mengupayakan nafsunya untuk berada pada jalur yang diridai Allah, bukan menuntut Allah agar membenarkan nafsunya.”
Keempat: Jika Anda bertanya, “Apakah diperkenankan belajar Ilmu Tauhid, yang membahas persoalan dengan begitu detail, padahal ayat ini menjelaskan bahwa lā yus`alu ‘ammā yaf’alu (Dia [Allah] tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan)?
Ada beberapa jawaban untuk menanggapi hal ini: (a) Secara dzahir, ayat tersebut menjelaskan ketidakbolehan itu pada aspek ‘ammā yaf’alu (tentang apa yang dikerjakan), bukan tentang Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, mempelajari Ilmu Tauhid tentu tidak menyelingkuhi makna ayat yang tengah kita bahas ini. (b) Di poin ketiga telah kami sampaikan bahwa kebolehan mempertanyakan manakala ia dilatarbelakangi thalab al-hikmah (mencari hikmah), sedangkan pertanyaan dengan motif menghindari tanggung jawab (li an lā yus`ala) berkonsekuensi hukum sebaliknya. (c) Mempelajari dan mencari tahu tentang Tuhan adalah perintah, bahkan ia masuk dalam kategori kewajiban paling utama, sebagaimana tersebut dalam surah Muhammad ayat 19: fa’lam annahụ lā ilāha illallāhu (Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan selain Allah). Bahkan anjuran yang diberlakukan menggunakan redaksi fa’lam yang bermakna disiplin ilmu yang metodologis, bukan sekedar pengetahuan biasa dan sederhana. (d) Lebih lanjut, pada ayat setelahnya terdapat tantangan kepada orang-orang musyrik untuk membuktikan klaim mereka (bahwa ada tuhan selain Allah), yaitu pada redaksi qul hātụ bur-hānakum (Katakanlah [Muhammad], “Kemukakanlah argumentasi kalian”). Hal ini adalah bentuk pengajaran dari Tuhan (tarbiyah min ar-Rabb) agar tak bertaklid, lebih-lebih dengan persoalan keimanan. Jika orang musyrik saja diminta mendalilkan keyakinan mereka, maka bagaimana dengan keimanan seorang mukmin?
Kelima: Dalam tinjauan sufistik, Imam Shadr ad-Din al-Baqli (w. 606 H), menulis dalam tafsir ‘Arāis al-Bayān fī Haqāiq al-Quran, bahwa lisan mahluk tak sanggup mempertanyakan tentang apa yang diperbuat Tuhan, karena kewibawaan dan keagungan Tuhan yang tampak manakala disingkap keluasan al-Jabarut dan persaksian mereka terhadap kebesaran al-Malakut. Kala itu, tak ada tanya maupun kata-kata dari mereka, lebih-lebih celaan terhadap yang diperbuat Tuhan. Justru mereka yang sibuk dengan mencacat tindakan mereka, yang akrab dengan kekurangan, menyelingkuhi perintah dan aturan yang ditetapkan oleh-Nya.
Seperti simpulan Imam al-Kawasyi—yang diceritakan dalam al-Bahr al-Madīd—bahwa ketika seseorang merenungi ayat ini dengan baik, didapatinya ia sebagai setengah dari al-Quran, sebab ia mengandung topik rububiyyah dan ubudiyyah secara global.
Selanjutnya, al-Anbiya` ayat 24:
اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗقُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ
Amittakhażụ min dụnihī ālihah, qul hātụ bur-hānakum, hāżā żikru mam ma’iya wa żikru mang qablī, bal aktṡaruhum lā ya’lamụnal-ḥaqqa fa hum mu’riḍụn
Atau apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia? Katakanlah (Muhammad), “Kemukakanlah alasan-alasanmu! (Al-Quran) ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku.” Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak (kebenaran), karena itu mereka berpaling.
Ayat ini memeliki beberapa poin penting, antara lain:
Pertama: Pengulangan redaksi amittakhażụ min dụnihī ālihah (atau apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia?) yang senada dengan ayat sebelumnya (al-Anbiya: 21) guna menunjukkan betapa besar bentuk keingkaran dan kemusyrikan yang mereka lakukan; selain itu, mereka juga menuduh Tuhan dengan yang bukan-bukan. Demikianlah pendapat para mufassir.
Kedua: Ayat ini, lebih-lebih pada kata qul hātụ bur-hānakum (Katakanlah (Muhammad), “Kemukakanlah alasan-alasanmu!) juga mengandung tentang pengingkaran suatu kepercayaan yang didasari taklid, di satu sisi; serta kewajiban membangun argumentasi dan menunjuk dalil tertentu guna menopang sebuah keyakinan, di sisi lain, demikian Imam al-Qusyairi.
Imam ar-Razi juga menyatakan di dalam ayat ini terdapat etika diskusi, karena mula-mula, Allah menunjukkan dalil ketauhidan; disusul kemudian dengan menegaskan prinsip ketauhidan yang akan meluluhlantakkan kesubhatan orang-orang yang menganggap tuhan lebih dari satu; dan yang terakhir, Allah menantang orang musyrik agar mendatangkan bukti demonstratif (burhān) tentang kepercayaan yang mereka anut.
Imam Abu Manshur al-Maturidi memasukkan qul hātụ bur-hānakum kategori keniscayaan pada negasi (luzụm ad-dalīl ‘ala an-nafy); hal ini sama dengan ungkapan, “ayo buktikan ucapanmu bahwa ini adalah bilangan genap!” seandainya seseorang yang ditantang tidak bisa membuktikan bahwa bilangan itu genap, secara otomatis yang tepat adalah bilangan tersebut berstatus ganjil. Hal ini serupa, ketika orang musyrik tidak dalam membuktikan bahwa ada tuhan selain Allah, niscaya kesimpulan yang benar adalah keesaan Allah semata.
Sekali pun menggunakan kata perintah, qul hātụ bur-hānakum (Katakanlah (Muhammad), “Kemukakanlah alasan-alasanmu!), tetap saja orang-orang musyrik tidak dapat memberi rasionalisasi tentang kepercayaan mereka, sebagaimana tersebut dalam ayat 117 surah al-Mu`minun:
وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖۙ
(Dan barang mengatakan bahwa ada tuhan yang lain selain Allah, pasti tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu.)
Dengan demikian, perintah ini bermakna sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dari situ kita bisa merenungi dengan seksama betapa jauh ketersesatan orang-orang musyrik. Semoga keimanan kita terus dijaga oleh Allah Swt.
Ketiga: Imam ar-Raghib pernah menjelaskan dalam Mufradāt Alfādz al-Qur`an, kata burhān berarti “penjelasan argumentatif”. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia terbentuk dari kata bariha-yabrahu yang bermakna “terang” atau “menjadi jelas”. Namun yang tak kalah unik, terdapat kata bentukan lain, yaitu burhat yang berarti “sekilas”, “sekejap” atau “partikularia dari waktu (muddat min az-zamān)”. Karena itu, burhān bisa dimaknai sebagai dalil terkuat yang bisa menjelaskan sesuatu secara tepat-akurat dan berlaku sepanjang lipatan masa; baik untuk sesuatu yang dipastikan benar maupun ia keliru.
Dalam disiplin logika, burhān dibedakan dengan dalil. Imam Ibrahim al-Baijuri pernah menyederhanakan bahwa dalil bersifat umum, ia bisa dibuat dari satu proposisi untuk kemudian mengantarkan pada kesimpulan. Sementara burhān adalah bangunan silogisme yang terdiri dari premis mayor, premis minor dan sebuah konklusi. Contoh sederhana tentang dalil menegenai pembuktian eksistensi Tuhan adalah alam. Ya, alam saja ini sudah bisa dijadikan dalil bahwa Tuhan itu ada. Namun burhān lebih kuat lagi, karena sistematikanya akan mengantarkan kita pada rumus berikut:
Premis mayor : Semua yang baru (kejadian) membutuhkan sebab
Premis minor : Alam semesta adalah hal yang baru (dijadikan)
Konklusi : Alam semesta membutuhkan sebab
Sekalipun sekilas tampak sama, dengan mempelajari logika, kita bisa melihat detail kebenaran di masing-masing premis yang tak menyempatkan kita mencicipi keraguan sama sekali.
Keempat: Penggalan ayat hāżā żikru mam ma’iya wa żikru man qablī (ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku), dalam tafsir Ta`wīlāt al-Quran, Imam al-Maturidi memaparkan tiga pandangan: (a) makna hāżā żikru mam ma’iya adalah bahwa al-Quran memuat hukum halal-haram (syariat) yang berlaku bagi umat nabi Muhammad Saw; sementara wa żikru man qablī adalah kabar yang merekam tentang sejarah umat terdahulu, beserta seluruh hal-ihwal mereka. (b) menjelaskan tentang kebenaran risalah (kerasulan) nabi Muhammad Saw sendiri, beserta kebenaran para rasul terdahulu. (c) ayat ini menunjukkan keselarasan ajaran seluruh utusan yang membawa kalimat tauhid, “lā ilāha illāllāh (tiada tuhan selain Allah)”, sebagaimana diungkap pada lanjutan ini:
وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا۠ فَاعْبُدُوْنِ
(Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.) QS. Al-Anbiya: 26
Kelima: Penggalan akhir ayat ini berbunyi bal aktṡaruhum lā ya’lamụnal-ḥaqqa fa hum mu’riḍụn (Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak (kebenaran), karena itu mereka berpaling). Setelah Allah menjelaskan keesaannya, dengan berbagai macam model argumentasi, lalu menantang orang musyrik memberi rasionalisasi tentang kepercayaan mereka, tetap saja mereka berada dalam kesesesatan; sebab mereka memiliki muasal segala keburukan dan kehancuran yang tertancap jauh dalam diri mereka, yaitu ketiadaan ilmu (‘adam al-‘ilm), disertai dengan pengingkaran dan dilengkapi dengan kemalasan mencari kebenaran. Begitulah ungkap Imam ar-Razi tentang potongan ayat ini.
Imam al-Qusyairi memotret mereka dengan cara berbeda, beliau berpendapat bahwa ketiadaan ilmu disebabkan keengganan mereka merenung (an-nadzr); sebab, andaikata mereka merenungi dengan baik, niscaya mereka dapat memperoleh pengetahuan yang benar. Ayat ini menunjukkan kewajiban merenung, karena seluruh pengetahuan pasti membutuhkan usaha, tak terkecuali ilmu ladunni!
Di sisi lain, ayat ini juga semacam penguat dari sebuah pepatah bahwa:
الجاهل بالشيئ ينكر ذلك الشيئ
“Manusia cenderung memusuhi apa yang tak diketahuinya!”
Keenam: Dalam Futụh al-Ghaib, Imam Husain ath-Thibi membeberkan semua kesalahan kaum musyrikin, bahwa mereka telah keliru dalam pembuktian naqli maupun aqli. Redaksi hāżā żikru mam ma’iya wa żikru mang qablī (ini adalah ajaran bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku) menunjukkan tidak ada satu wahyu dari nabi-nabi terdahulu yang mengajak pada kemusyrikan atau menyekutukan Allah; sementara bal aktṡaruhum lā ya’lamụnal-ḥaqqa (Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak (kebenaran)) berarti kesimpulan Allah memiliki sekutu juga tidak dapat dipertanggungjawabakan secara rasional; dan konsekuensi dari itu semua fa hum mu’riḍụn (mereka berpaling).
Wallahu A’lam. [HW]