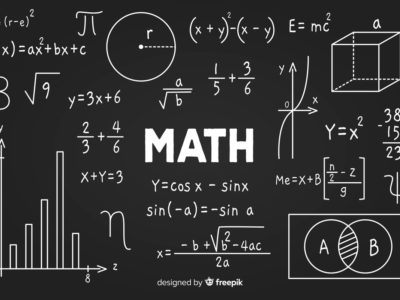Kategorisasi Clifford Geertz yang masyhur tentang Agama Jawa itu nampaknya sudah mulai usang. Betapa tidak, wajah vis-a-vis “abangan” dan “santri” ala Geertz sudah baur maknanya. Santri tidak hanya sebuah nomenklatur yang digunakan untuk antitesa kaum abangan semata. Wajah santri hari ini juga tidak bisa hanya dicitrakan dengan stereotip-stereotip dengan gelar kaum konservatif, tradisionalis, jumud dan paling parahnya Santri sering dilabeli esketik. Tak ayal, bukti sejarah membuktikan bahwa Serat Wedhatama yang konon dikarang oleh Mangkunegara IV banyak mengkritik gaya hidup santri. Salah satunya tuman temanem ing sepi (baca: terbiasa gemar tertanam dalam kesepian). Gaya hidup ini mungkin menjauhkan kehidupan kaum sarungan (baca: santri) dengan lingkungan sosial menengah keatas yang seringkali punya hiruk-pikuk sendiri dengan kemajuan pengetahuan masa kini. Akhirnya, kaum santri ini berakhir hanya dikenal menjadi tokoh masyarakat tingkat RT atau aktivis tingkat desa. Namun, itu problem santri dahulu.
Vice versa. Potret santri era ini punya kemajuan yang luar biasa. Konsep nahdliyyin yang sering disebut-sebut “al-Akhdzu bil jadidil ashlah” (baca: mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik) itu mungkin merupakan bentuk sikap adaptif kaum santri untuk melihat realitas hari ini. Sebut saja Gus Dur, mantan presiden RI keempat itu merupakan seorang santri tulen. Namun, menariknya semasa muda beliau merupakan santri yang saya sebut sebagai santri yang go international. Sudah maklum kita ketahui bahwa dengan ijazah SD dan kompetensi kepesantrenannya beliau tak berhenti mencari ilmu hingga Al-Azhar Mesir, University of Baghdad hingga mengembara ke Belanda dan Jerman. Kala itu, bacaan-bacaan Gus Dur sebagai santri bahkan tak hanya masalah-masalah teologis, namun masalah filsafat, politik, sosial hingga ekonomi beliau lahap. Sebagaimana kata Greg Barton, Gus Dur muda menghabiskan bacaannya dengan karya-karya Ernest Hemingway, Faulkner, Marx hingga Lenin.
Kisah Gus Dur diatas, nampaknya di era ini sudah bukan hal baru. Santri-santri Indonesia kini banyak yang sudah punya kiprah baik sebagai pejabat, pengusaha, bahkan guru besar kelas Internasional pun ada, sebut saja Prof.Nadirsyah Hosen atau Habib Ismail Fajrie Alatas. Nah, inilah mungkin yang harus kita pertanyakan relevansitas kategorisasi Agama Jawa tentang santri yang sekarang mulai hidup pada “Kategorisasi Ketiga” sebagai bentuk kritik-adaptif pada peradaban yang disebut oleh Goenawan Mohamad sebagai a wounded civilization (baca: peradaban yang terluka).
A wounded civilization ini merupakan bentuk sindrom bagi kaum agamawan baik di Barat, Timur Tengah bahkan Indonesia sekalipun, pada Abad ke-20. Dibelakang peradaban ini ada revolusi Perancis, mesin-mesin Industri, kemegahan teknologi, Hak Asasi Manusia, filsafat Marx hingga filsafat Godam Friedrich Nietzsche yang menghabisi apa yang ada dibalik fisik atau kita sebut sebagai metafisika. Dibalik itu semua hal-hal seperti kepercayaan akan Tuhan, Nabi, Surga, Neraka bahkan laku agama pun raib dihantamnya. Singkat kata, apapun yang “diluar fisik” itu meaningless (baca: tak bermakna) bagi dunia fisik.
Akhirnya, bentuk penolakan pun muncul dari berbagai kalangan agamawan. Manifesto yang muncul dari kalangan agamawan ini melahirkan gelombang fundamentalis atau puritanis yang massif, tak terkecuali dalam Islam. Mereka mensinyalir bahwa ketidakmampuan menghadapi a wounded civilization ini merupakan bentuk laku tiap pemeluk agama yang tidak mengamalkan agama dari sumber agamanya masa lalu secara otentik. Menurut mereka, praktek beragama orang pada masa kini sudah tidak beragama secara murni. Dus, kekecewaan gelombang kelompok ini akhirnya menjelma sebagai bentuk upaya takfiri dalam Islam yang seakan memperburuk citra Islam sendiri dengan menghegemoni truth claim, pengkafiran serampangan hingga gerakan-gerakan teror atas nama agama.
Namun, menarik diketahui bahwa santri bukanlah sosok yang gegabah hingga kagetan. Kaum sarungan (baca: santri) ini menanggapi hal ini sebagaimana nalar Hegelian, bahwa peradaban yang terluka bukan berarti peradaban yang sudah mati. Ia membutuhkan penyembuhan untuk luka yang ia derita. Dalam arti lain, peradaban yang jelek, batil atau fasid di mata kita, butuh perbaikan yang solutif. Bukan dengan membentur-benturkan peradaban ala Samuel Huntington yang terkenal dengan teori Clash of Civilizations.
Oleh karenanya, santri yang kita kenal hari ini adalah santri yang melek pengetahuan, sadar akan agama (baca: bukan mabuk agama), cakap akan teknologi, hingga mahir berkompetisi. Santri model ini tidaklah anti terhadap kemajuan zaman, namun juga tak lupa akan kearifan masa lampau. Santri-santri semacam inilah yang mungkin diinginkan oleh Abid Al-Jabiri, sarjanawan muslim Sorbonne, Perancis, sebagai kelompok proyeksi pencerahan Islam (renaissance of Islam). Bukan santri yang ikut arus gelombang para takfiris yang memperburuk citra Islam serta momok bagi kemanusiaan.
Memang, kaum santri kali ini sedang berjalan sekaligus mempersiapkan peradaban baru ini—-barangkali juga merobohkannya, siapa tahu? Namun, patut kita menaruh harapan pada kaum santri. Mungkin saja dengan wajah yang baru ini akan lahir sosok-sosok seperti Gus Dur, sudah barang tentu kita mendambakan kaum santri melahirkan pionir-pionir pencerahan pada sejarah peradaban Islam sekelas Ibnu Rusyd, al-Farabi hingga al-Ghazali. []