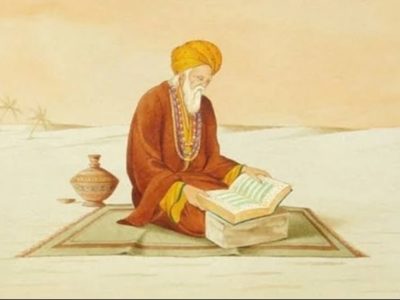Untuk pertama kalinya saya sowan ke Ndalem Gus Baha’ di Narukan, Rembang. Sebagaimana yang saya tulis dalam catatan sebelumnya, saya pertama kali bertemu beliau di Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, kala itu beliau ‘transit’ sebentar dan berziarah ke Makam Mbah Kholil, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke PP. Bata-Bata Pamekasan.
Di sore itu, sebelum hadir ke acara Haul Mbah Zubair, saya sowan bersama dua ponakan saya, Muhammad Ismail Al-Ascholy dan Muhammad Thoifur (Putra Kiai Thoifur Ali Wafa Sumenep), ada juga Yek Shodiq El Khered (salah satu santri kesayangan Gus Baha’) dan para Gus dan Lora lainnya.
Kala itu ternyata Gus Baha’ sudah bersiap-siap untuk tindak ke Sarang, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk menyambut kami, mempersilahkan kami duduk dan memulai dawuh beliau yang penuh mutiara ilmu dan hikmah itu :
“Orang itu kalo keturunan ulama atau wali, dia seharusnya tidak bangga, tapi justru sedih dan terbebani. Sedih jika akhlak, prilaku, dan pencapaiannya tidak sama dengan mbah-mbahnya. ”
Gus Baha’ seakan ingin menjelaskan kepada tamunya di sore itu yang kebanyakan adalah para Gus dan lora, bahwa nasab mulia itu bukan untuk dibuat bangga-bangga-an, bukan hanya dapat ditunggangi untuk mendapat rasa hormat manusia kebanyakan, lebih dari itu semua nasab mulia adalah sebuah beban dan tanggung jawab, sebuah pelecut diri untuk mengikuti tindak-jejak para leluhur yang merupakan wali-wali Allah itu.
Beliau lalu mengambil sebuah kitab, Kitab Fawaidul Mukhtaroh kumpulan kalam dan fawaid Habib Zain Bin Smith, beliau meminta Yek Shodiq untuk membacakan sebuah kisah dalam kitab itu :
“Suatu ketika ada golongan para Sayyid sedang berkumpul membaca kitab المشرع الراوي, kitab manaqib para Habaib Ba’alawy. Kala itu ada seorang Baduwi yang kebetulan ikut menyimak sejak awal. Ketika pembacaan kitab selesai, Baduwi itu bertanya :
“Mereka yang dibaca manaqibnya ini keluarga siapa? ”
“Mereka adalah buyut-buyut kami.” jawab para sayyid.
“Alhamdulillah mereka bukan buyut-buyut saya.” Baduwi itu menimpali.
Para Sayyid itu jelas kaget lalu berkata :
“Jika mereka buyutmu, itu adalah sebuah anugrah untukmu.”
“Tidak, justru jika mereka adalah kakek buyut saya, saya akan merasa sangat malu karena amal perbuatan saya sangat jauh dibandingkan amal perbuatan mereka.”
Gus Baha lalu mengomentari kisah itu:
“Jadi gak enak to anaknya kiai ? Misalnya ada orang baca sejarahnya Syaikhona Kholil, kita (yang bukan keturunan beliau) senyum-senyum aja, gak beban, gak harus niru, kan gak cucunya ”
beliau tertawa, sedangkan kami yang menjadi target “sindiran” itu hanya bisa tersenyum malu. tapi itu yang saya suka dari Gus Baha’, beliau selalu mempunyai cara yang khas dan unik dalam menyampaikan sebuah pesan, tanpa ada kesan menyakiti atau menggurui, Alih-Alih menyampaikan pesan kaku :
“Kalian keturunan ulama harus begini.. Harus begitu.”
Gus Baha’ justru lebih memilih menyampaikan sebuah cerita dengan hikmah yang sangat dalam, diselingi dengan “gojlokan” ilmiah yang selama ini sudah menjadi ciri khasnya.
Sowan pertama saya waktu itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi beberapa menit bersama beliau jelas sangat istimewa rasanya. Baru ketika sowan ke ndalem beliau untuk kedua kalinya pada malam Idul Adha kemarin, saya bisa ngobrol dengan beliau agak lama, mulai dari jam setengah sebelas sampai hampir jam dua belas malam. Saya ingat ketika itu beliau berpesan :
“Saya dengar sampean suka nulis. Pesan saya, jika sampean nulis jangan hanya karena mengikuti permintaan atau minat pembaca. Tapi jadikan tulisan itu sebagai sesuatu yang ” Talqallah bihi”, sesuatu yang bisa dibawa dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.”
Di Kantor PWNU kemarin untuk kesekian kalinya saya bertemu beliau. Setelah acara Launching kitab Syaikhona Kholil beliau bahkan mengajak saya untuk sowan kepada Habib Zain Baharun di Markaz Ha’iah Sofwah. Dan dimanapun Gus Baha’ memang seperti itu, yang selalu beliau bicarakan adalah ilmu, ilmu dan ilmu. ketika beliau berbicara dengan saya dan saya hanya bisa terkagum-kagum seraya mengimbangi “sekali-kali” agar kebodohan saya gak begitu “ketara”, kadang terbesit di dalam hati saya :
“Gus Baha’ ini ilmu semua. Mulai dari ujung peci sampai ujung kaki.”
Rahasia kealiman Gus Baha’
Dari dulu saya selalu curiga, bahwa di balik sosok hebat pasti ada peran seorang waliyyullah di sana. Saya pernah menceritakan bahwa Habib Ali Al-Jufri lahir dalam keluarga politik, ayahnya adalah mantan wakil Presiden Yaman. Tapi karena sang ayah seringkali membawa Habib Ali kecil sowan ke Ndalem Al-Quthub Habib Abdul Qodir Assegaff, akhirnya Habib Ali bisa menjadi sosok ulama besar yang kita kenal saat ini.
Gus Baha’ ternyata juga begitu, beliau ini adalah “korban” cipratan barokah waliyullah. Ceritanya dulu ketika Gus Baha’ masih kecil, Abah beliau Yai Nur Salim seringkali mengajak beliau sowan ke ulama-ulama Lasem. Dan salah satu ulama yang disowani abah beliau waktu itu adalah Waliyullah Mbah Yai Hamid Baidhowi. ketika melihat Gus Baha’, Mbah Hamid spontan dawuh kepada Yai Nur Salim:
“Anakmu besok sing bakale paling ngalim yo cah iki.” (sambil menunjuk ke arah Gus Baha’ )
Barokah dawuh, doa dan pandangan Mbah Hamid waktu itu, Gus Baha’ bisa menjadi tokoh hebat yang diidolakan jutaan orang seperti yang kita kenal saat ini.
Membaca sejarah hidup Habib Ali dan Gus Baha’, saya teringat Gubahan Indah pengarang Nadhom Riyadhotussibyan :
و ليلتزم فعل الكرام الأوليا * المتقين الصالحين الأتقيا
و يعتمد ْجلوسه بينهمُ * حتى يوافق طبعُه طبعَهمُ
“Hendaknya sejak dini, kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk mengikuti jejak orang-orang mulia para wali, para sholihin, para kekasih Allah.”
Kita juga harus membiasakan anak-anak kita untuk duduk bersama mereka, agar tabiat anak-anak kita bisa serasi dan “mencocoki” tabiat mereka ”
Barokah Gus Baha’, Habib Ali, dan para kekasih Allah lainnya. Karuniakan kami Ya Rabb. Keturunan yang sholeh dan sholehah. Yang menyejukkan mata. Dan menentramkan hati.