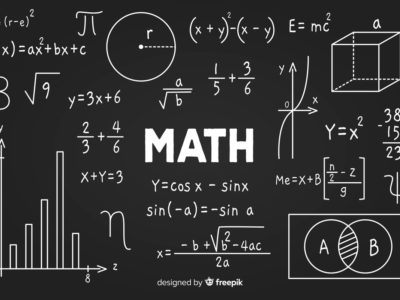Dalam catatan para pengamat pesantren, baik orang pesantren sendiri ataupun orang dari luar pesantren. Konsep pesantren selalu diidentikkan dengan kiai, santri, masjid/mushala, kitab kuning dan asrama santri. Sehingga definisi pesantren yang “tertulis” di catatan para pengamat dalam dan luar negeri belum banyak (kalau tidak bisa dikatakan tidak ada) menyebutkan nyai sebagai bagian unsur penting didalamnya. Bahkan sesaat sebelum tulisan ini dibuat, dalam definisi konsep pesantren di Wikipedia juga tidak menyebutkan nyai sebagai unsur utama penopang pesantren (penulis kemudian menambahkan nyai sebagai unsur utama pesantren dalam definisi itu, sebelum memposting status ini). Kenyataan ini bisa jadi merupakan salah satu “eskpresi” betapa kuat nilai-nilai ideologi patriarki dalam benak para penulis atau pengamat pesantren tersebut. Sehingga luput dalam mencermati peran nyai yang begitu penting dalam dinamika pesantren. Untuk kemudian disematkan dalam definisi pesantren.
Pesantren adalah sebuah subkultur yang di dalamnya terdapat unsur-unsur utama penopangnya mulai dari kiai, nyai, santri, mushala/masjid, asrama, dan pengajian kitab kuning/gundul atau kitab klasik berbahasa Arab tanpa tanda harakat (Kitab-kitab kuning ini adalah karya ulama yang otoritatif dalam ilmu agama. Karena itu kemampuan memahami kitab tersebut menjadi syarat “utama” kompetensi santri pesantren salaf). Sangat penting diketahui bahwa peran nyai selama ini seringkali di sembunyikan di belakang sosok kiai. Padahal dalam kenyataannya, peran nyai ini terkadang jauh lebih strategis dibandingkan sang kiai. Karena para Nyai inilah yang mengatur manajemen pesantren, mulai dari memanage keuangan, dapur logistik, mengajar santriwati dan bahkan merawat jaringan dengan para wali santri. Secara simbolik yang muncul di ruang publik memang sosok kiai, tetapi dihampir semua pesantren tradisional sosok Bu nyai adalah “pemegang” otoritas manajemen pesantren. Para nyai bukan saja melakukan kerja-kerja domestik, tetapi juga melakukan kerja-kerja publik yang sangat menentukan terhadap keberlangsungan “hidup” sebuah pesantren. Ketika ada santri/ alumni yang sakit, wafat, atau punya hajat, para nyai menjadi subjek terdepan dalam menerima dan merespon informasi tersebut. Ketika para kiai sibuk tampil di ruang publik, Bu nyai sibuk menguatkan jaringan dengan para alumni dan wali santri di belakang layar.
Jejaring pesantren yang selama ini lebih difokuskan pada “jejaring” intelektual semata, ternyata memiliki aspek yang lebih substansial dan sangat mendasar, yakni hubungan sosial “kekerabatan” yang disponsori oleh para Nyai. Sebab para Nyai inilah yang menjadi “eksekutor” ketika seorang Gus atau Ning akan dikirim ke pesantren untuk belajar. Para nyailah yang melanjutkan lobi para kiai untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan “pelayanan” yang terbaik. Bukan hanya itu saja terkadang para nyai ini pula yang menjadi penentu proses perjodohan para Gus dan Ning (putra-putri kiai/nyai) dari pesantren satu dengan pesantren lainnya. Sehingga akhirnya pesantren memiliki ikatan kekerabatan atau kekeluargaan disamping ikatan kultural karena adanya transmisi keilmuan antar kiai terhadap putra putri mereka. Fenomena memperkuat dan mempertahankan nasab “keulamaan” ini, sampai sekarang masih terus berlangsung. Meskipun sudah mulai banyak mengalami pergeseran, karena perkembangan zaman.
Para kiai dan Bu nyai adalah Soko guru kemandirian pesantren. Sejak dahulu pesantren dengan segala unsur penopang utamanya tersebut dikenal sebagai sebuah lembaga yang otonom. Pesantren adalah ekspresi puncak pengabdian keilmuan seorang ulama (kiai dan nyai). Pesantren bukan lembaga bisnis pendidikan untuk mencari keuntungan ekonomis. Kesadaran intelektual para kiai dan nyai yang menyatu dengan kesadaran spiritualnya. Menjadikan mereka menempatkan dirinya sebagai subjek yang siap mengorbankan apapun untuk mengamalkan ilmunya secara ikhlas dan cuma-cuma. Dahulu tidak ada pesantren yang berbayar, para kiai juga tidak menerima salam tempel. Sebaliknya para kiai dan Bu nyai lah yang terkadang harus menyediakan kebutuhan sehari-hari para santri, terutama para santri yang berlatar belakang keluarga yang sangat sederhana. Meskipun demikian umumnya para santri adalah sosok yang mandiri. Mereka memenuhi dan menyiapkan kebutuhan mereka sendiri. Inilah karakteristik kemandirian pesantren yang mulai “luntur” dengan hadirnya pesantren modern yang lebih mengejar “kelulusan”, ketimbang proses membangun karakter “kemandirian” dengan bekal ilmu dan spiritualitas.
Kemandirian pesantren dalam segala hal adalah sebuah proses “riyadho” para kiai dan nyai, serta santri dan para walinya. Inilah sumber keberkahan utama pesantren salaf di masa lalu, sehingga bisa melahirkan ribuan ulama (kiai dan nyai) yang menjadi ujung tombak proses islamisasi di Nusantara. Menjelang peringatan hari santri kali ini, perlu bagi kita untuk menyadarkan semua komponen pesantren baik itu Kiai, Nyai dan santri, serta masyarakat luas agar bisa mengembalikan “Marwah” pesantren sebagai ekspresi puncak pengabdian intelektual dan spiritual bersama, yang harus dijaga otonominya. Karena hanya lembaga pesantren inilah yang sampai sekarang tetap bisa mempertahankan karakter-karakter pendidikan yang membebaskan, mencerdaskan dan mencerahkan. #SeriPaijo