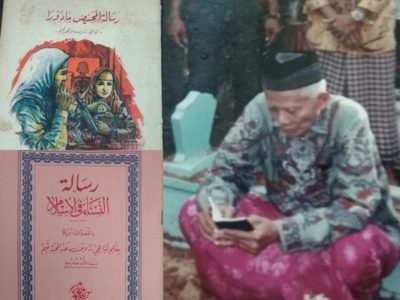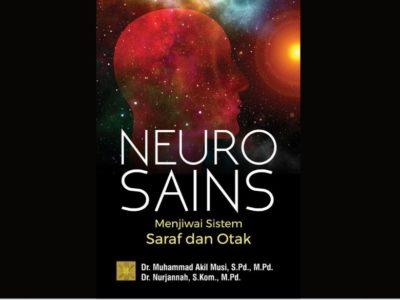Akhirnya aku tiba di Terminal Giwangan Jogja pukul 23.47 WIB tadi malam. Aku tatap agak lama terminal ini sembari mengingat-ingat kapan terakhir kali aku menggunakan bisnya untuk pulang ke Jombang. Sangat lama. Aku baru sadar kereta api benar-benar telah merampok keberanianku menaiki bus Jogja-Jombang.
“Pulanglah.. Kamu harus ke kampus besok pagi,” kataku ke adikku, Lail yang selalu setia mengantar dan memberiku tumpangan tidur setiap kali ke Jogja. Kami berpelukan, tanda perpisahan, selah sejak siang terus bersama.
Aku mengajaknya menghadiri peresmian Omah Larasati di kawasan Semail Sewon, Bantul. Pemiliknya adalah guruku, Rachmi Dyah Larasati, professor seni asal Bantul yang mengajar di Minnesota AS. Aku tidak pernah belajar tari darinya. Persentuhanku dengan perempuan flamboyan ini terjadi dua kali. Yang paling lama, ketika aku ikut kelasnya selama 4 hari di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Kelas Dekolonisasi dan Cultural Studies.
“Mas, nyuwun tulung sampeyan datang ya. Doa dan sambutan di acaraku. Daerahku terkena land grabbing,” katanya melalui pesan singkat . Sejenak aku berfikir “land grabbing,” merujuk pada keserakahan akuisisi lahan oleh para pemilik modal yang tak mengindahkan kedaulatan sumber daya alam. Namun ternyata lebih buruk dari yang aku kira. Diksi itu rupanya ia gunakan secara ekstentif, yakni pengguritaan lahan oleh kelompok yang selama ini memandang Islam sebagai ideologi dan paradigma politik.
Tak butuh waktu lama bagiku untuk mengiyakan meski aku harus meninggalkan buah hatiku, Galang dan Cecil sendirian di rumah untuk sesaat. Bagiku, inisiatif dan komitmen Mbak Dyah harus aku apresiasi tak peduli ratusan kilometer aku tempuh untuk menemukan Desa Semail.
“Perempuan, Islam, Sunni, Jawa, sangat jarang dididik untuk konfiden membuat forum-forum budaya. Laki-laki kerap memonopoli dunia tersebut, apalagi dalam Islam-Sunni. Paling notok, bikin pesantren dan biasanya membutuhkan figur laki-laki agar bisa lebih diterima masyarakat. Namun guru saya ini berbeda. Ia mewarisi spirit Sukayna, cicit Rasulullah,” kataku membuka sambutan.
Sukayna mungkin satu-satunya perempuan Islam awal yang bisa mengkonsolidasi puluhan seniman di Hijaz, antara tahun 690-730an Masehi. Rata-rata adalah penyair dan penyanyi. Hampir semuanya laki-laki.
Di rumah mewahnya, ia punya gelanggang seni. Para penyair kerap antri agar bisa tampil. Namun tidak semuanya lolos. Sukayna tidak segan memberi insentif bagi penyair yang karyanya bagus.
Sukayna bint Husain ini juga dikenal punya suara sangat bagus dan melatih beberapa penyanyi, termasuk Abdul Malik Lelaki ini dibina Sukayna, dibiayai sekolah vokalnya ke Ubaydallah bin Surayj hingga menjadi penyanyi dengan spesialisasi elegi dan kedukaan. Jika ada yang meninggal, maka Malik dipanggil untuk menyanyi, persis dalam tradisi beberapa denominasi Kristen saat ini.
Saat Muhammad al-Hanafiyyah, anak pasangan Ali bin Abi Thalib dan Khaula bint al-Ja’far al-Hanifah, meninggal dan diistirahatkan di Masjid Nabawi 25 Februari 700 M, Malik diminta menyanyi. Sukayna ada di situ juga.
Mbak Dyah bukanlah Sukayna karena ia tidak menyanyi saat peresmian Omah Larasati tadi malam. Alih-alih, perempuan berwajah Jawa-ndeso otentik ini menari di hadapan banyak orang. Ia tidak sendirian. Ada banyak seniman-akademisi dan praktisi-seni dari berbagai kota dan negara yang hadir dan menyumbangkan karya seninya.
Secara spesifik, saat tampil dalam sebuah fragmen pendek tari dan dialog, Dyah menyindir peminggiran perempuan dari ruang produksi dengan dalih agama. “Aku krungu saiki wong wedok-wedok gak oleh melu nang sawah soale kuatir ‘bukan muhrim’,” sentilnya disambut tawa hadirin. Dyah sedang mengkritik politik segregasi berbasis jenis kelamin yang mulai marak beberapa tahun terakhir ini.
Perempuan ini jelas tidak salah. Amatanku menyatakan Islamisme di kalangan muslim semakin mengental. Islamisme berbeda dengan Islam. Islamisme, jika disederhanakan, adalah “pokoe kudu Islam sing menang,” Tidak ada kemitraan dan seduluran yang setara dengan agama/keyakinan lain.
“Ibu bapak sekalian tugas kita sebagai orang Islam adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat berarti tulus mengasihi dan selalu siap mengampuni. Bukan mengislamkan orang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi rahmat kalau kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Islam tidak menghendaki kita mencopot dan mengganti identitas kita setelah menjadi Islam. Tetaplah menjadi Jawa sekaligus Islam. Tetaplah menari, ngremo, ketoprakan, nyinden, wayangan. Menjadi Islam adalah menjadi diri kita seutuhnya. Bukan mengganti tradisi kita. Allah tidak meminta pergantian itu. Mari kita umbulkan doa bersama,” aku menandaskan sambutanku.
Setelah doa dihaturkan, aku meminta semua hadirin berdiri menyanyikan lagu Padamu Negeri.
***
Aku terbangun geragapan di kursi Bis Sumber Kencono. Wajahku terkena tetasan AC yang bocor. Seketika itu pula aku cari ransel yang tadi aku taruh di sampingku. Alhamdulillah masih ada.
“Mengkreng…Mengkreng…” kondektur berteriak mengingatkan penumpang. Jam menunjukkan 4.31 subuh. Solo-Kertosono hanya 3,5 jam saja. Lumayan cepat. Sepuluh menit lagi aku harus turun dari bis. Tiba di rumah.