Ketika Fathu Makkah, Rasulullah Saw mempercayakan dua hal penting kepada Takmir masjid Nabawi yang beliau sayangi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memasrahkan kota Madinah yang beliau tinggalkan sementara kepada Abdullah bin Ummi Maktum r.a. Sahabat ini buta, bersuara merdu, menjadi asbabun Nuzul turunnya Surat ‘Abasa, dan punya ketajaman mata hati (bashirah). Ini adalah keputusan penting: seorang penyandang disabilitas dipercaya menjadi pemimpin sebuah kota.
Keputusan kedua, memberikan peluang kepada takmir lainnya, yaitu Bilal bin Rabah r.a untuk mengumandangkan adzan di atas Kakbah. Keputusan penting yang membuat beberapa orang yang baru masuk Islam, sewot. Mereka heran mengapa Rasulullah memberikan amanah kepada bekas budak berkulit hitam untuk menaiki Baitullah sekaligus mengumandangkan adzan. Tapi inilah wujud Egaliter beliau. Memberikan peluang kepada para sahabat lintas etnis untuk bisa tampil sesuai dengan potensinya.
Selain Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal r.a Rasulullah juga memperhatikan Ummu Mahjan, seorang perempuan tua, berkulit hitam, berpenampilan sederhana, yang saban hari ikut membantu mempersihkan masjid Nabawi. Ketika tiga hari tidak menjumpai perempuan tua ini, beliau bertanya keberadaannya. Dijawab oleh para sahabat, jika wanita tersebut sudah wafat.
“Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?”
Saat itu para sahabat melihat Ummu Mahjan sebagai sosok yang tidak penting. Biasa-biasa saja. Rasulullah kecewa karena para sahabatnya tidak memberitahukan kabar duka ini kepada beliau.
“Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya!”
Lalu para sahabat bergegas menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah Saw. Setelah sampai di kuburnya, Rasulullah mendoakan Ummu Mahjan.
Luar biasa sayangnya Rasulullah kepada para marbot masjid. Ibn Ummi Maktum, Bilal, dan Ummu Mahjan. Ketiganya berasal dari kelompok yang termarginalkan: mantan budak, berkulit hitam, penyandang disabilitas, serta seorang perempuan sepuh. Tapi bagi Rasulullah, tidak ada bedanya. Semua sama. Berhak menjadi orang baik yang bertakwa, dan beliau memberikan peluang kepada mereka untuk berkreasi sesuai dengan potensinya.
Ini adalah di antara contoh Rasulullah yang menghormati para takmir masjid Nabawi. Sebuah profesi yang kini jarang dilirik karena dianggap tidak bergengsi. Padahal menjadi takmir ini salah satu jalan mulia (Lihat QS. Taubah ayat 18).
Masjid adalah fondasi peradaban. Ketika hijrah, Rasulullah membangun Masjid Quba terlebih dulu, kemudian membangun Masjid Nabawi di Madinah. Demikian pula para pahlawan Islam. Amr bin Ash r.a ketika memasuki Mesir, memilih membangun masjid terlebih dulu. Para da’i ketika menyebarkan Islam, biasanya memilih membangun masjid sebagai tonggak peradaban dan spiritualitas. Pola demikian bertahan selama ratusan tahun.
Dalam “Al-Madinah al-Islamiyyah”, Muhammad Abdussattar Utsman mengutip pendapat
Ibn Ar-Rabi’ tentang penanda kota Islam. Pertama, masjid jamik sebagai titik pemersatu. Kedua, setiap jalan besar, jalan kecil, lorong, maupun jalur dirancang agar menuju masjid. Di kota-kota besar yang menjadi poros peradaban Islam klasik, dari Baghdad, Toledo, Granada, maupun Istanbul, tata letak masjid ada di tengah kota, dan dikelilingi berbagai jalan yang menuju kepadanya. Sampai saat ini tata ruang di sekitar Masjidil Haram juga demikian.
Dulu, ketika Walisongo merancang sebuah kota, konsepnya juga meletakkan masjid sebagai sentrum. Hanya saja, mereka juga berijtihad dengan meletakkan masjid di barat alun-alun, serta menempatkan posisi pendapa di sebelah utara alun-alun. Hal ini mengandung filosofi tata pemerintahan yang menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi.
Ketika membangun masjid, filosofi Walisongo diletakkan di atap bersusun tiga. Seperti Masjid Demak. Filosofinya Islam, Iman dan Ihsan. Ini tampak di semua masjid yang didirikan oleh para santrinya Walisongo, maupun jejaring intelektual yang bersambung dengannya. Misalnya, Masjid Kesultanan Banten, Masjid Kesultanan Ternate, Tidore dan seterusnya. Bahkan, masjid Baiturrahman (yang menjadi tempat pengajian semalam), masih melestarikan desain arsitektur atap susun tiga ini.
Ketika para da’i membangun masjid, mereka juga menyertainya dengan kolam kaki yang diletakkan di samping kiri masjid. Ini tataruang masjid khas masyarakat agraris. Fungsinya, agar jamaah bisa mencuci kaki sebelum memasuki area masjid. Sebab, dulu masyarakat jarang yang menggunakan sandal. Kaki dibersihkan terlebih dulu. Setelah itu bisa melewati kolam kaki kedua yang berfungsi sebagai penyuci kaki. Standar ukuran, 2 kulah atau 216 liter, versi kekinian, 270 liter.
Selain tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat tarbiyah, pendidikan. Di zaman Nabi, para ahlus shuffah tinggal di emperan masjid Nabawi. Mereka nyantri(k) kepada Rasulullah. Hidup dalam suasana yang sangat sederhana dan seringkali berpuasa sepanjang tahun. Mereka tidak punya tempat tinggal kecuali di masjid itu. Jumlahnya 70, dalam riwayat lain 90 orang. Mereka menyertai dan ikut mengabdi kepada junjungannya. Abu Hurairah dan Hudzaifah al-Yamani adalah di antara ahlusshuffah yang terkenal. Konsep ahlussufah ini berkembang menjadi Zawiyah dan Khanaqah dalam tradisi para sufi.
Dulu, sebelum ada madrasah, masjid menjadi penyelenggaraan kuttab, alias pengajaran ilmu agama dengan format halaqah. Para ulama lahir dari majelis berformat ini. Ketika tradisi ini berkembang, maka di sekitar masjid didirikan pemondokan. Ini adalah level perkembangan awal pondok pesantren. Ketika pendidikan Islam berkembang lagi, lahirlah madrasah. Biasanya sistemnya klasikal. Berjenjang.
Wallahu A’lam Bisshawab





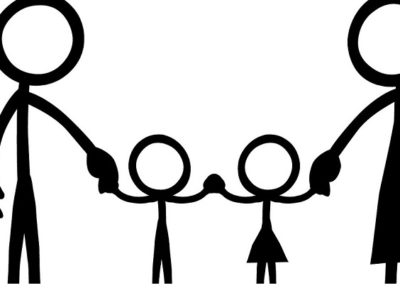





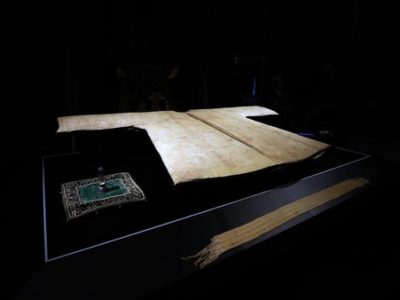












Mantaaap guuus….renyah bacanya