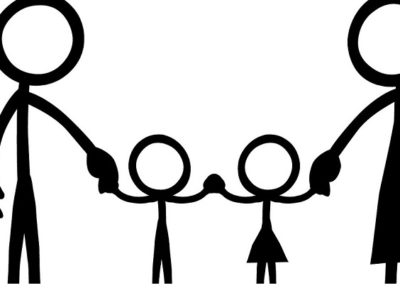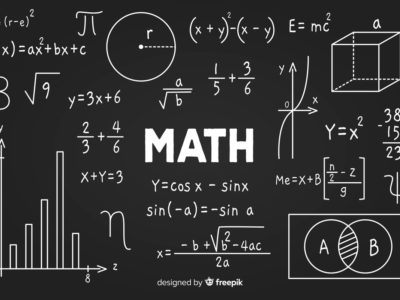Sejak lama, saya bertanya-tanya agak “kepo,” kenapa sarjana Barat bersedia mati-matian mempelajari budaya-budaya bangsa lain; dan untuk itu, mereka bersedia menempuh jalan terjal yang amat sulit. Tidak mudah bagi sarjana-sarjana Barat ini untuk mempelajari budaya bangsa-bangsa lain, terutama di dunia Timur. Mereka, pertama-tama, harus mempelajari bahasa yang sangat asing bagi mereka. Mereka harus belajar bahasa-bahasa antik seperti Arab klasik, Persia, Turki, Ibrani, Suryani, Ugaritik, Kawi, Sanskerta, Melayu lama, dan bahasa-bahasa lain di kawasan timur yang lain.
Tidak hanya itu. Mereka juga bersedia membaca dengan kesabaran yang nyaris tak masuk akal ribuan manuskrip kuno yang amat sulit. Kita bisa membayangkan, betapa terjalnya jalan yang harus ditempuh oleh sarjana besar Belanda seperti, misalnya, untuk membacai naskah-naskah kuno berbahasa Kawi dari era Majapahit. Saya heran: kenapa mereka mau melakukan ini semua? Apakah sarjana kita ada yang “sesabar” ini?
Saya melihat ada sesuatu yang agak “problematis” pada (sebut saja) kegilaan sarjana-sarjana Barat itu untuk mengkaji dunia Timur (termasuk dunia Islam), hingga bersedia banting tulang, bertungkus-lumus, berdarah-darah (dan saya tidak sedang mendramatisir ketika memakai kata-kata ini!) untuk mempelajari bahasa-bahasa “antik” di dunia Timur. Setahu saya, tidak ada bangsa manapun di dunia yang memiliki kegilaan seperti ini. Apakah ini semua motifnya semata-mata kecintaan pada ilmu, kehendak memahami budaya bangsa lain, atau ada dorongan lain yang tak terkatakan sebagai “leitmotif,” motif utama?
Sejarawan Islam besar (harus diakui, memang dia hebat!) Bernard Lewis pernah bertanya dalam bukunya “What Went Wrong” (2002) begini: kenapa saat peradaban Islam unggul dulu, sarjana Muslim tidak memiliki hasrat besar untuk mempelajari dunia lain seperti dimiliki sarjana-sarjana Barat? Sarjana Muslim yang melancong untuk melongok dunia lain hanyalah segelintir saja jumlahnya, salah satunya Ibn Battuta (w. 1369). Jumlah ini amat tak sebanding dengan sarjana barat yang sejak dulu selalu ingin mengkaji dunia lain di luar dunia mereka. Lewis memiliki spekulasi begini: mungkin karena sarjana Muslim dibebani oleh “hantu teologis,” yaitu memandang dunia lain di luar Islam sebagai dunia “kafir” yang sama sekali tak layak dipelajari. Apa yang layak dipelajari dari dunia kafir? Begitu dugaan Lewis.
Saya sangat tidak setuju dengan pandangan Lewis ini. Pandangan ini hanya menggambarkan prasangka dia yang memang sejak awal “sinis” pada dunia Islam.
Meskipun sulit dibuktikan, tetapi saya kira penjelasan Edward Said sebagaimana ia tulis dalam bukunya yang sudah amat klasik, “Orientalism” (1978), lebih masuk akal: hasrat yang nyaris gila untuk mempelajari dunia Timur di kalangan ilmuwan Barat ini adalah bagian saja dari hasrat yang lebih besar untuk mendominasi bangsa lain; hasrat untuk dominan.
Saya tidak yakin, hasrat ilmiah pada sarjana Barat ini semata-mata didorong oleh “kehendak memahami”. Saya agak sulit percaya. Dengan mengakumulasi pengetahuan yang begitu massif tentang bangsa-bangsa lain, termasuk dan terutama tentang dunia Timur, sarjana Barat sebetulnya ingin mempertahankan dominasi mereka sebagai bangsa yang menang.
Ini semua bukan berarti bahwa kita tak bisa belajar dari produk pengetahuan yang begitu kaya dan mencengangkan yang diusahakan oleh sarjana Barat selama ini. Bukan. Ada manfaat yang amat besar dalam kajian-kajian mereka mengenai bangsa Timur ini, dan kita bisa mengambil faedah dari sana. Saya sendiri amat menikmati kesarjanaan Barat tentang Islam, termasuk tentang Imam Ghazali. Tetapi ini semua tak boleh membutakan kita untuk melihat sesuatu yang “tersembunyi”: yaitu hasrat mendominasi yang saya duga melandasi kerja ilmiah sarjana-sarjana Barat.
Sejak era awal Islam hingga saat ini, setahu saya, para sarjana Muslim tidak mengkaji sesuatu untuk “mendominasi”. Ketika ulama Muslim di era klasik mempelajari filsafat Yunani dan lain-lain, misalnya, mereka melakukan hal itu semua bukan karena dorongan untuk menguasai bangsa lain. Mereka tidak mengkaji sesuatu tentang bangsa-bangsa lain dengan tujuan untuk mendukung “hasrat imperial” yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Mereka mempelajari segala sesuatu sebagai bagian dari perintah agama untuk memahami. Memahami adalah tindakan yang baik pada dirinya sendiri, karena akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita baca kitab-kitab filsuf besar Muslim bernama Ibn Sina, misalnya, akan tampak sekali tekanan pada aspek ini: ilmu sebagai sumber kebahagiaan, dan jalan yang membawa kita kepada Allah, sumber segala ilmu.
Saya kira memang di sini kita melihat dua “mode of knowing” (cara mengetahui) yang berbeda antara sarjana Barat dan sarjana-sarjana lain, termasuk sarjana Muslim. Di Barat, “mode of knowing” tampak amat dibentuk dan disemangati oleh hasrat untuk dominan. Semangat ini tidak ada, atau kurang menonjol pada sarjana dari bangsa-bangsa lain, termasuk sarjana Islam di era kejayaan peradaban Islam dulu. Contoh perbandingan yang menarik: ambisi “imperial” China saat ini tidak dibarengi dengan hasrat yang “gila” untuk mengetahui bangsa-bangsa lain seperti pada bangsa Barat.
Bagi saya, mengetahui untuk mendominasi jelas sesuatu yang bermasalah. Mengetahui, mestinya, adalah untuk memahami dan mengenal. Setelah mengenal, kita membangun jembatan dialog, persis seperti etik yang dikenalkan Qur’an dalam surah al-Hujurat: li-ta’arafu, saling mengenal. []
Wallahu a’lam.
(Catatan yang ditulis karena “gabut” di rumah terus)