Pernikahan adalah sebuah prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Banyak proses yang ditempuh sebelum melangsungkannya. Pernikahan, kendati merupakan sunnah Nabi yang didambakan banyak orang, namun justru terkadang terlampau sulit bagi sebagian orang. Selain norma agama, pernikahan tidak dapat dilepaskan dari norma budaya masyarakat. Hampir di setiap pelaksanaan tahap-tahapnya dipengaruhi oleh adat yang mengikat.
Dalam Islam terdapat konsep terkenal yang disebut dengan mukafa’ah/kufu (sepadan atau sama). Masing-masing dari pihak mempelai putra dan putri dianjurkan memiliki kesepadanan atau kesamaan dalam beberapa lini kehidupan. Konsep ini sebenarnya tidak mengikat, karena tidak termasuk syarat atau rukun pernikahan. Ada atau tidaknya tidak akan mempengaruhi keabsahan pernikahan. Keberadaannya hanya merupakan anjuran, agar manusia selektif dalam memilih pasangan.
Akan tetapi, sebagian kalangan memperbesar kriteria kufu yang meliputi berbagai aspek; agama, nasab, kecerdasan, kedudukan sosial, material (kekayaan), dan hal-hal lain yang menuntut kedua calon mempelai benar-benar memiliki kualitas yang sama. Sebagian yang lain mengaitkan mukafa’ah dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 26:
ٱلۡخَبِیثَـٰتُ لِلۡخَبِیثِینَ وَٱلۡخَبِیثُونَ لِلۡخَبِیثَـٰتِۖ وَٱلطَّیِّبَـٰتُ لِلطَّیِّبِینَ وَٱلطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَـٰتِۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةࣱ وَرِزۡقࣱ كَرِیمࣱ
“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”
Dalam beberapa literatur tafsir disebutkan bahwa ayat tersebut merupakan penekanan dari ayat-ayat sebelumnya yang mengisahkan fitnah yang dituduhkan kepada ummul mu’minin Sayyidah Aisyah. Dalam konteks ayat di atas disebutkan bahwa kata ‘ulaika’ (mereka) yang dimaksud adalah ahlul bait (keluarga dan keturunan Nabi) yang terbebas dari ucapan dan tuduhan kaum yang memfitnah. Oleh karenanya, Nabi yang memiliki kedudukan mulia sebagai seorang utusan Allah, mendapatkan orang baik pula, yaitu Sayyidah Aisyah (yang tidak mungkin melakukan perbuatan zina seperti tuduhan dan fitnah yang dilontarkan kepadanya).
Konsep kufu, kendati memiliki tujuan yang mulia, yaitu melestarikan dan melahirkan generasi yang mulia, berakhlak karimah, dan memperoleh keturunan yang baik, namun tentunya memiliki kelemahan di bidang sosial kemasyarakatan. Jika orang baik mendapatkan orang baik, dan orang buruk mendapatkan yang buruk pula, bukankah itu akan membuat yang buruk semakin memburuk? Dimana wujud kepedulian Islam dalam membangun prinsip keadilan dan kesalingan? Bukankah salah satu fungsi pernikahan adalah saling melengkapi kekurangan satu sama lain?
Persoalan baik dan buruk juga akan menimbulkan subyektivitas dari setiap orang. Karena, baik al-khabitsin al-khabitsat dan ath-thayyibin ath-thayyibat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat. Kriteria orang baik yang seperti apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Bagaimana pula dengan kriteria orang yang buruk? Tentunya masing-masing masyarakat memiliki tolok ukur yang berbeda-beda.
Konsep ini akan menjadi semakin rancu ketika manusia saling merasa bahwa dirinya adalah seorang yang baik, sehingga ia layak mendapatkan orang yang baik pula. Atau keluarganya adalah keluarga yang baik, sementara tak mau menyambung kerabat dengan keluarga lain yang ‘dianggapnya’ buruk. Dari sini akan muncul eksklusifisme yang akan berujung pada ‘ujub (kesombongan dan kecongkakan).
Tanpa disadari, konsep kufu yang berlebihan ini justru semakin menutup mata batin kita bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kita mau berpikir sederhana dan tak muluk-muluk, kufu yang dimaksud di masa Nabi adalah kedua mempelai sama-sama orang yang merdeka (karena dahulu masih berlaku perbudakan) dan beragama Islam. KH. Abdullah Salam, salah seorang ulama dari desa Kajen Pati menggambarkannya dengan sederhana, bahwa yang dimaksud dengan kufu di zaman sekarang adalah sama-sama beragama Islam dan melaksanakan salat lima waktu dengan istiqamah. Dua kriteria ini cukup untuk dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Karena adanya pernikahan adalah untuk saling melengkapi kekurangan dari masing-masing mempelai. [HW]









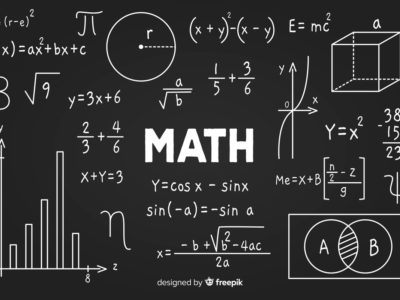














[…] ini ada karena selama masa iddah masih belum selesai, keduanya masih ada ikatan zaujiyah (pernikahan) yang sewaktu-waktu bisa diulangi jika keduanya berubah pikiran untuk kembali ruju’. Sementara […]
[…] kitab tersebut di dalamnya. Kemudian pada bab pertama beliau menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan, yang meliputi sunah, wajib, haram dan makruh. Penjelasan mengenai rukun-rukun pernikahan beliau […]
[…] memahami tanda-tanda itu untuk mencapai tujuan dalam sebuah pernikahan. Dengan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Bila keduanya selalu belajar memahami […]