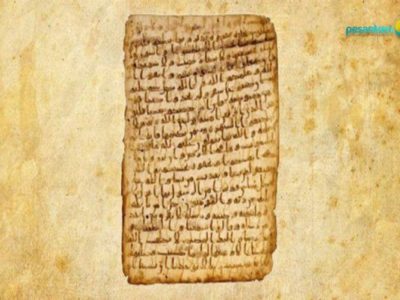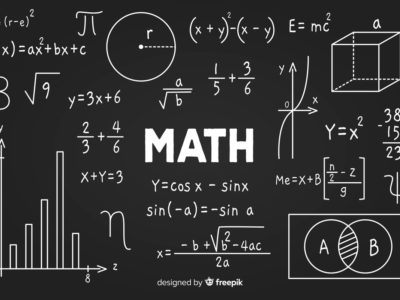Kebelet menulis ini sejak awal Maret ketika membaca tema ‘Mendobrak Bias’ dalam peringatan hari perempuan internasional 2022. Tapi ada kondisi yang menjauhkan saya dari alat tulis dalam minggu-minggu terakhir ini, sementara ada kawan yang masih menunggu tulisan saya.
Tentang tema ini sudah ada tulisan yang memesona dari Mba Lies Marcoes di halaman FBnya yang juga dimuat di The Jakarta Post. Konstruksi tulisan saya juga agak mirip dengan yang dibuat Mba Lies, tapi alurnya jadi berbeda karena elaborasi yang berbeda.
Sekedar mengingatkan, umumnya generasi saya atau mungkin setelah itu pertama kali mengenal kata ‘bias’ dari pelajaran IPA di SD (namun rupanya saat ini sudah dikenalkan juga di PAUD, saya tahu dari website ayoguruberbagi.kemendikbud.go.id, yang gambarnya saya pinjam).
Kata ‘bias’ muncul dalam tema belajar tentang cahaya. Kita dapat melihat karena cahaya memantulkan citra suatu benda ke dalam mata, yang oleh syaraf dikirim dan diproses dalam otak, sehingga kita dapat melihat dan memahami keberadaan suatu benda.
Cahaya bergerak lurus merambat dalam udara, namun dalam udara yang mempunyai kerapatan berbeda, (misalnya di atas dan di dalam permukaan air), cahaya mengalami pembiasan, atau pembelokan. Karena pembelokan cahaya ini, benda yang aslinya berbentuk lurus jadi terlihat patah. Uji coba dari jaman saya kecil hingga kini biasanya menggunakan pensil yang dimasukan ke air. Karena pembiasan, pensil yang lurus terlihat patah. Tiga unsur dalam fenomena ini adalah cahaya, perbedaan (kerapatan udara), pem-bias-an.
Kesimpulan: perbedaan (kerapatan udara) dapat menghasilkan kesan yang tidak sesuai aslinya. Kesan terkait mempersepsikan sesuatu.
Menariknya fenomena fisika berupa pembiasan ini ternyata terjadi juga dalam relasi sosial dan interpersonal. Pembiasan dalam relasi ini juga muncul karena perbedaan, namun di sini pemicunya adalah perbedaan situasi dan kondisi subyek. Misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kemampuan, perbedaan budaya dan agama, perbedaan kondisi sosial-ekonomi dst., ketika subyek hanya menggunakan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang dirinya, namun ia merasa pemahamannya sudah ‘benar’, lurus, apa adanya, padahal dengan adanya perbedaan, untuk mencapai pemahaman ‘yang sesungguhnya’ membutuhkan sudut pandang lain, agar tidak menimbulkan ‘patahan’ dalam pemahaman tentang realitas tersebut. ‘Patahan’ ini bisa bermakna salah pengertian yang dapat berdampak pada salah memilih tindakan.
Pemahaman dari sudut pandang tunggal dalam relasi dengan liyan yang diyakini kebenarannya meski sebenarnya ada pembelokan dan belum diklarifikasi, ini yang biasa disebut prasangka.
Sudut pandang praktisnya adalah posisi dalam membaca fenomena kehidupan, cara memahami sesuatu, kemampuan merumuskan kenyataan dan dengan ini menjadi kuasa memutuskan tindakan. Bila ini hanya dilakukan sepihak, maka hanya pihak yang berkemampuan membaca dan merumuskan tadi yang menentukan arah dan gerak dalam relasi yang terjadi.
Bias dalam relasi interpersonal dan sosial muncul karena tidak ada pertemuan atau ‘dialog antar sudut pandang’, karena hanya satu yang digunakan, yaitu sudut pandang pihak yang dominan. Misalnya bila sudut pandang orang dewasa yang dominan dari sudut pandang anak, maka pemahaman-pemahaman yang muncul dalam relasi itu bias (membelok pada kepentingan atau selera) orang dewasa. Bila sudut pandang kaum laki-laki yang dominan, maka pemahaman narasi dan keputusan tindakan bias (membelok pada kepentingan atau selera) laki-laki, bila sudut pandang orang biasa yang dominan atas kaum difabel, disitu pasti terjadi bias kaum non-difabel, demikian pula dalam soal agama dst.
Makna bias dalam relasi interpersonal dan sosial adalah kondisi mental-intelektual di mana salah satu pihak menguasa cara berfikir semua pihak, sehingga keputusan yang diambil hanya mementingkan satu pihak. Sementara pihak yang lain suka atau tidak suka dianggap sepakat, bahkan kemudian tersudut hingga menyakini kebenaran yang diputuskan dari pihak lain yang sesungguhnya memiliki pengalaman berbeda, karena sistem pengetahuan mengkonstruksi demikian. Relasi yang terjalin menjadi relasi subyek obyek.
Dalam sejarah ilmu pengetahuan, soal bias ini menjadi tema penting karena nilai validitas dalam penelitian dan kebenaran sebuah konstruksi pengetahuan.
Sebelum Thomas Kuhn memproklamirkan revolusi paradigma keilmuan, ada anggapan bahwa seorang peneliti dapat mengamati secara netral, hasil pengamatannya dianggap terbebas dari kondisi subyektifnya. Namun dengan penemuan teori relativitas, terbukti bahwa subyek peneliti pun bisa bias dalam melakukan pengamatan. Ini lebih jelas dalam sejarah ilmu sosial humaniora, misalnya dengan fenomena etnosentrisme, sehingga kejahatan kemanusiaan berupa penjajahan, tindakan rasis pun saat itu dianggap wajar. Revolusi paradigma ilmu pengetahuan telah mendobrak bias, mengingatkan bahwa subyek peneliti, pengamat pun bisa bias, hasil pengamatan bisa terkontaminasi oleh selera, kepentingan dan kondisi-kondisi tertentu dari pengamat.
Namun revolusi paradigma ilmu pengetahuan ini tidak serta merta membuat para peneliti mawas diri pada bias, sebagai kondisi intelek yang mewarnai mentalitas dan pilihan tindakan. Masih ada kepentingan yang seringkali lekat dalam pengetahuan yang dikuasi seseorang atau sekelompok orang.
Dorongan untuk menguasai, memenangkan atau mendominasi dalam relasi dengan liyan ini yang melanggengkan terjadinya bias.
Bias menghasilkan pemahaman yang tidak tepat atau keliru. Bila pemahaman ini menjadi dasar sebuat tindakan, tentu dapat menyebabkan tindakan yang salah atau tidak tepat, bahkan bisa menyebabkan munculnya kejahatan kemanusiaan.
Untuk mencegah reproduksi bias, semua pihak dalam setiap relasi harus aktif mengungkap sudut pandangnya, sehingga relasi yang terjalin adalah relasi dialogis atau relasi intersubyektivitas, tidak memberi ruang bagi dominasi. Mencegah bias juga dapat dilakukan dengan membuat pengalaman berada dalam situasi pihak yang berbeda, mengalami atau membuka diri pada sudut padang orang lain, sehingga memunculkan kritik diri dan mencegah dampak bias berupa dominasi dan salah memilih tindakan dalam relasi.
Orang yang pergaulannya hanya dengan komunitas homogen, serba sama, cenderung memiliki bias dalam pikiran dari pada orang yang memiliki pergaulan beragam dengan kalangan yang heterogen, karena akan mendapatkan kesempatan klarifikasi lebih banyak, dapat menumbuhkan kebiasaan otokritik serta mawas diri dari bias.
Istilah Mba Lies Marcoes ‘Merebut Tafsir’ pada tulisan-tulisan beliau pada dasarnya adalah contoh sikap ilmiah yang mendobrak bias ini.
Bias masih mewarnai banyak cara pandang dalam bermacam-macam relasi yang tidak setara. Refleksi perempuan tentang bias ini, sangat berharga bagi penyehatan peradaban. []



![Mengulik Makna Berbakti Kepada Orang Tua Dalam QS. Al-Isra [17]: 23-24](https://pesantren.id/wp-content/uploads/2022/03/berbakti-kedua-orang-tua-180x180.jpg)