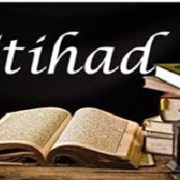Aing rapih jeung pangampih/jeung bangsa sili eledan/teu meunang padoger-doger/moal mangrupa beunangna/ngaingkar ka sasama/nya mucuk papucuk-pucuk/moal kurang nu beukina.
Saya rapi dengan tempat berlindung/dengan sesama saling toleran/tidak boleh saling meledek/tak akan terlihat hasilnya/mengingkari pada sesama/saling berlomba menjadi pucuk/tak akan berkurang yang menggemarinya. (Buku Haji Hasan Mustapa: Sufi Besar Tanah Pasundan, Penerbit Imania (Pustaka IIMaN), 2020, hal 251)
Beuti tutukeuran beuti/sakapeung jeung lain bangsa/
pare ditukeuran pare/tandana jeung sasamana/itu pake ieu hakan/pangabutuh tara tangtu/sahayangna-sahayanga.
Umbi saling tukar umbi/terkadang dengan yang beda jenis/padi ditukar padi/tandanya dengan sesamanya/itu pakai ini makan/ kebutuhan tak menentu/semaunya masing-masing ((Buku Haji Hasan Mustapa: Sufi Besar Tanah Pasundan, Penerbit Imania (Pustaka IIMaN), 2020, hal 252)
Menurut sufi mahiwal kelahiran Cikajang, Garut, Haji Hasan Mustapa (selanjutnya ditulis HHM): barang siapa yang telah mengetahui siapa Tuhannya maka ia akan bisa bersikap tenggang rasa. Ia tidak akan mengingkari keberadaan orang lain. Toleransi terhadap sesama, menurut HHM, adalah salah satu bentuk makrifat makhluk dan Khaliknya. Sebab, sekalipun berbeda sifat dan kecenderungan keyakinan, sebagai sesama manusia, tetap sama-sama makhluk di hadapan Khaliknya.
Jika seseorang telah memahami jati dirinya sendiri maka ia akan selalu saling membantu antar-sesama. Dalam proses interaksi, seseorang yang telah memahami hakikat dirinya akan selalu mencari persamaan dibandingkan perbedaan, kendati ada beberapa hal yang secara duniawi dirasa tidak sama. Bila pemahaman seperti ini telah terbentuk maka agama akan digunakan untuk menemukan persamaan, titik temu, kalimat sawa’. Bukan perpecahan, pertengkaran, dan eker-ekeran.
Wacana pengarustamaan moderasi (cara) beragama digalakkan dan diseminarkan, buku-buku dan jurnal tentang moderasi beragama ditulis, pusat kajian moderasi beragama didirikan. Lantas apakah aksi dan laku intoleransi bisa ‘disembuhkan’, atau diminimalisir di Republik ini?
Sejumlah kaum intelektual dan aktivis penggiat toleransi hendak mengatasi masalah intoleransi dari hilirnya saja, dengan berupaya memberi penafsiran-penafsiran baru terhadap sejumlah ajaran-ajaran agama. Padahal, masalahnya ada di hulu, dalam hal ini pandangan ketuhanan yang eksklusif melahirkan tafsir, sikap, dan perilaku eksklusif pula. Masalah intoleransi tidak akan pernah selesai sebelum adanya perubahan padangan ketuhanan yang benar- benar inklusif. Tuhan bukan untuk kelompok atau golongan A maupun golongan B, melainkan Tuhan bagi semua, terserah masing-masing memanggil dan menamakan-Nya. Nama bukan sesuatu yang esensial pada Tuhan. Dia sudah ada sebelum adanya nama. Nama hanya sebatas cara manusia berkomunikasi dan mengomunikasikan pandangannya, tidak merepresentasikan esensi-Nya.
Ironis, memang, bahwa orang-orang getol bicara tentang toleransi dan inklusivisme, tapi di hilirnya saja. Padahal, masalahnya ada di hulu. Masalahnya pada pandangan tentang Tuhan yang eksklusif. Dalam pengertian agama sebagai situasi keilahian yang menuntun kepada kebaikan, setiap orang melakukan kebaikan: Entah menyumbangkan hartanya, entah menemukan teori-teori ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, entah kebaikan apa saja, semua itu bernilai di sisi Tuhan dan pasti Tuhan mengapresiasinya. Sujiwo Tejo, penulis buku Tuhan Maha Syik 1 dan 2, pernah mengkritik soal wacana moderasi dan toleransi beragama yang digencarkan di Negeri ini hanyalah toleransi permukaan. Toleransi hilir. “Silakan kamu menjalankan agamamu, tapi agamaku yang paling benar.” Inilah toleransi hilir. Tampak luarnya toleran. Tapi dalam hati antarpemeluk agama yang berbeda tetap ada bara sekam rasa unggul.
Seharusnya agama-agama mengajarkan kebijaksanaan dan kearifan. Tapi, orang-orang yang mengaku beragama yang justru gaduh mempersoalkan siapa-siapa saja yang boleh masuk surga dan siapa-siapa saja calon penghuni neraka. Siapa yang benar, siapa yang sesat? Siapa yang terbekati, siapa yang dilaknat Tuhan?
Orang-orang beragama sibuk melakukan kategorisasi-kategorisasi berdasarkan logika kelompok, bukan atas kualitas-kualitas manusia. Misalnya, tetap dipersoalkan apakah seseorang dapat masuk surga jika bukan golongan agama “X”, walaupun yang bersangkutan sesungguhnya rajin berbuat baik, terutama untuk sesama manusia. Seseorang banyak jasanya bagi kehidupan manusia dan memenuhi hajat orang banyak tidak digolongkan sebagai penduduk surga kelak, hanya karena tidak bergabung ke dalam agama “X”. Jika perbuatan baik seseorang tidak berharga dan tidak bernilai hanya karena tidak termasuk dalam golongan agama “X”, berarti perbuatan Tuhan lebih sia-sia lagi, karena menciptakan, bahkan menganugerahkan karunia yang melimpah kepada orang-orang yang tidak beragama “X”.
Sekelompok orang, misalnya, sangat alergi dengan banyaknya rumah ibadah yang didirikan oleh komunitas yang bukan kelompoknya. Jika mengenal jati diri, niscaya logikanya akan menerima, bahwa semakin banyak rumah ibadah yang didirikan, terlepas dari siapa pun penggagas dan pendirinya, akan semakin baik karena begitu banyak dan bervariasi doa-doa yang akan dipanjatkan dari dalam rumah-rumah ibadah tersebut. Semua pasti untuk kebaikan. Kalaulah ternyata ada doa-doa yang dimaksudkan mencelakai seseorang atau sekelompok orang, pasti Tuhan menolaknya.
Tapi, orang-orang dengan konsep teologi masing-masing justru cenderung mempertanyakan, bahkan mengingkari legitimasinya, lantaran tidak berkesesuaian dengan pandangannya yang eksklusif. Mereka lupa bahwa kebaikan adalah nilai universal yang bisa lahir di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, tanpa tergantung kepada identitas keagamaan formal. Seperti halnya udara yang kita hirup, tidak pernah kita perdebatkan siapakah yang paling benar menghirup udaranya. Atau udara hanya bisa terhirup benar jika melalui kelompok tertentu, atau menurut pandangan tertentu.
Narasi keagamaan yang menumpuk sedemikian banyaknya, manakala diteliti lebih saksama, justru lebih merepresentasikan kecenderungan para pemangku otoritas keagamaan ketimbang murni ucapan-ucapan utusan Tuhan. Boleh jadi faktor inilah yang membuat jarak antara realitas kehidupan pada masa kenabian dengan pasca-kenabian—atau antara idealisme ajaran agama dengan realitas umat beragama—jadi begitu jauh. Kala agama mengajarkan inklusivisme dan toleransi tinggi, rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang bagi segenap alam semesta, umat beragama malah mempropagandakan eksklusivisme dan klaim kebenaran sepihak—sambil menegasikan golongan lain. Akibatnya, sungguh ironis, ceramah-ceramah agama saat mendengungkan pentingnya toleransi tetap membawa prinsip kebenaran sepihak: Bahwa, “kebaikan hanya diakui atau legitimated jika dilakukan oleh kita, atau kelompok kita”.
Tuhan adalah Kebaikan Absolut, maka bertuhan adalah berlaku baik. Kebaikan bisa lahir dari apa saja, oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ini tidak bisa mengacu kepada konsep teologi, tapi merupakan output hati nurani. Haji Hasan Mustapa, Sang Begawan Sirna Dirasa, mengajak kita untuk melakukan toleransi hulu. “Silakan kamu menjalankan agamamu, aku menjalankan agamaku, dan semoga di ujung nanti kita bertemu pada kebenaran yang sama.” []