Mula-mula kita mesti mengakui bahwa cinta adalah satu-satunya bahasa yang mampu dimengerti dan dipahami setiap manusia, bahkan semesta. Bahasa cinta bukan semata verbalistik namun lebih jauh daripada itu ialah bahasa hidup, bahasa yang melampaui ruang dan waktu serta batas-batas wilayah yang menyekat. Bahasa yang muncul dari rahim nurani ketulusan serta buah dari pikiran bijak. Sehingga hidup tanpa cinta sama sekali merupakan kepiluan yang sungguh-sungguh menyedihkan.
Cinta yang semakin ke sini semakin disalahkaparahi manusia meski -bila kita meminjam istilah kaum progresif- perlu dimurnikan lagi. Bila pun mau menyangkal bahwa cinta adalah fenomena yang sering dijumpai berupa patah hati, perselingkuhan dan permasalahan yang lainnya, mari kita lebih bijak menggunakan justifikasi dengan meminjam istilah Ayu Utami bahwa cinta itu menerangi sedangkan asmara membakar. Dengan pandangan semacam ini tentu akan lebih adil bahwa segala kerusakan bukan timbul atas dasar cinta namun ia adalah ulah asmara, sebuah ruang semu dan kondisi pilu yang begitu menjebak manusia bila tak mau berhati-hati dalam mengolah cinta.
Muhidn M. Dahlan mengutarakan bahwa cinta itu sejatinya membebaskan, dengan kata lain ia ingin menggambarkan bahwa cinta membuat manusia bebas dari jebakan semu kehidupan berupa materi, jabat, pangkat, pencapaian-pencapaian fatamorgana atau bahkan ego dirinya sendiri. Maka memiliki cinta artinya telah memberi ruang pada diri untuk berlaku adil atas hidup. Berlaku manusiawi dengan satu di antaranya ialah mencintai lingkungan baik mereka yang sesama kita terikat oleh jalinan masyarakat, keluarga, dunia akademis, pun kepada alam yang kita perlu mencintai dengan cara merawatnya.
Kembali atas pandangan awal dengan prinsip bahwa cinta adalah bahasa yang bisa dipahami semesta, sebagai manusia kita juga perlu adil membaca cinta dari ayat-ayat semesta yang sangat ragam dan jamak. Dengan kemampuan akal dan kreatifitasnya, intuisi dan imajinasinya serta bila meminjam istilah barat dengan bukti empirik, manusia mesti membaca situasi yang sedang dialaminya dengan kaca mata cinta. Hal demikian diperlukan guna tetap menjaga optimismenya di tengah ujian-ujian semesta yang kerap datang amat tak terduga.
Satu di antaranya ujian bagi manusia saat ini tentunya ialah COVID-19 yang masih melanda berbagai terutama di Indonesia meskipun di negara ibunya ia sudah reda, namun hal ini tentu memberikan pukulan telak kepada siapa pun. Mereka yang memiliki rencana dalam basis sosial harus terpaksa ditunda dan bahkan batal. Pandemi yang tak mengenal warna kulit, agama, profesi pun telah menjadi mimpi buruk yang harus segera disudahi.
Kebingungan, ketegangan, kegaduhan, dan polemik sudah menjadi efek samping dari situasi ini. Masyarakat dan terutama rakyat biasa yang penghasilannya didapatkan dari basis interaksi sosial harus menangis berdarah-darah meratapi nasib mereka. Sementara di sisi lain tentu memaksakan diri untuk melawan instruksi pemerintah adalah bukan tindakan solutif.
Adagium klasik mengatakan mentalitas seseorang dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, kehilangan pekerjaan. Kedua, tidak punya uang. Ketiga, lapar dan kehausan.
Mengacu dari ketiga hal tersebut kita perlu merenungkan kembali petuah seorang ateis bernama Nietzsche yang amat terkenal, ia mengatakan “Amor fati fatum brutum” yang artinya “cintailah takdirmu meskipun itu kejam“. Dalam hal ini penulis bukan berarti sok bijak atau terkesan religius, namun lebih dari itu penulis ingin mengajak bahwa sedemikian absurd dan kompleksnya hidup, manusia tentu tak elok kehilangan cinta dan harapan. Apalagi bagi kaum muslim.
Kecemasan, kecamuk batin sudah tentu meliputi semua. Tak hanya itu, bahkan hal demikian bila tak disikapi dengan bijak maka akan menyebabkan kebuntuan berpikir logis yang menyebabkan aksi-aksi non-normatif. Mari kita merentangkan pikiran dan menggelar ketabahan lebih luas dari biasanya. Memahami bahwa tragedi ini sudah sedemikian melanda sembari tetap menjadi bahasa cinta kepada Tuhan dan berharap semua lekas sirna.
Akhirul kalam
Cinta Tuhan kepada hamba-Nya sangat beragam bentuknya. Nabi Adam mesti dipisahkan dulu dengan Siti Hawa, Nabi Ayub mesti menanggung penyakit yang demikian mengerikan, bahkan sampai nabi terakhir Muhammad harus berjibaku uang tenaga dan segala yang dipunya guna berjuang demi tetap mendapatkan cinta Allah meskipun di sisi lain mereka adalah manusia ma’shum. Dengan berkaca kepada para nabi yang barang tentu menjadi uswatun kita sebagai muslim, dalam situasi seperti ini barangkali ujian Tuhan karena bentuk cinta kasih-Nya kepada hamba-Nya. [HW]
Wallahu A’lam Bishawab


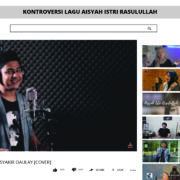










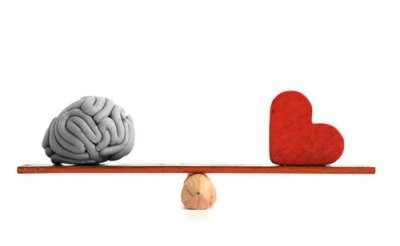










Mantap kak. Tidak dibiarkan seseorang yang mengatakan saya beriman maka Tuhan akan mengujinya.
yess