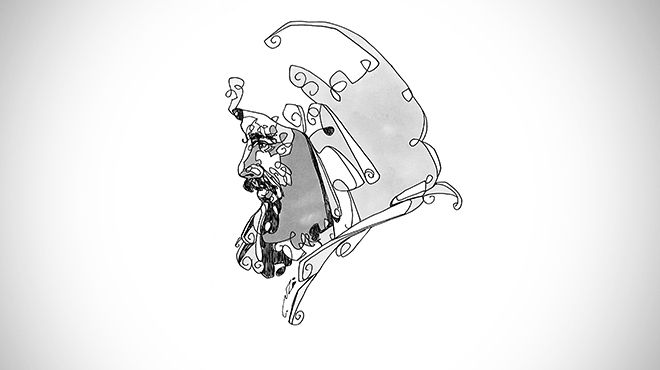Al-Jili menuangkan konsep-konsep tasawufnya secara utuh dalam kitabnya yang berjudul al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awa’il wa al-Awakhir. Kitab ini terdiri atas bab-bab yang berisikan perpaduan dari berbagai pokok bahasan. Adalah meliputi pembahasan tentang filsafat ketuhanan, alam, esensi ibadah dan lain-lainnya.
Namun demikian, yang tampak sebagai fokus perhatiannya adalah tentang konsep manusia yang dibahas secara khusus dalam satu bab tersendiri dengan judul al-Insan al-Kamil. Menurutnya, bahasan-bahasan dalam bab lainnya diperuntukkan sebagai penjelas terhadap bab al-Insan al-Kamil tersebut. Ia menyebutnya sebagai umdah (pokok) dari bab-bab lainnya.
Untuk dapat menggambarkan corak pemikiran tasawuf al-Jili secara tepat, maka perlu kiranya diketengahkan terlebih dahulu corak pemikiran tasawuf dalam perkembangannya sejak zaman Rasulullah. Yang jelas, dalam periodisasi sejarah, terbentuknya tasawuf itu melalui tiga tahapan.
Pertama, tahap kemunculan tasawuf yang ditandai dengan perilaku zuhud (sufi) dari kehidupan Rasulullah, para sahabat dan tabi’in. Mereka lebih berorientasi terhadap kehidupan yang abadi (akhirat). Kelompok ini dikenal dengan sebutan Ahl al-Shaffa. Sedangkan konsep wali atau quthb pertama kali dikenal dalam literatur para sufi yaitu, dengan munculnya figur Uways al-Qarni yang di identifikasi sebagai hamba yang shaleh.
Kedua, tahap al-tamkin (pembentukan), yaitu beralihnya konsep zuhud kepada konsep ma’rifah, dan zuhud dalam hal ini dipahami sebagai sarana menuju ma’rifah. Ma’rifah dijabarkan pertama kali secara sistematis oleh Dzun al-Nun al-Mishri. Konsep ma’rifah, pada kurun berikutnya ditarik oleh al-Hallaj pada pemahaman yang lebih ekstrim, yaitu manusia kamal (sempurna) sebagai gambaran Tuhan dan tempat tajalli (penampakan) Dzat Tuhan.
Ketiga, adalah tahap penyempurnaan, dimana konsep-konsep sebelumnya direkonstruksi secara lebih sistematis dengan menggunakan term-term filsafat Islam. Diantara tokoh-tokoh tasawuf pada masa ini adalah al-Suhrawardi, Ibn Arabi dan Al-Jili.
Pada tahap penyempurnaan di atas, ada juga beberapa kesamaan pandangan dari para sufi tentang kedudukan manusia sempurna. Persamaan-persamaan tersebut adalah: pertama, manusia sempurna sebagai poros dari segala yang ada (quthb); kedua, manusia sempurna sebagai perantara antara Allah dengan alam (wasithah); ketiga, manusia sempurna sebagai tempat penampakan (mazhhar) diri Tuhan; dan keempat, manusia sempurna sebagai tempat bercerminnya Tuhan (nuskhah) terhadap alam.
Pada tahap ini terjadi pertemuan antara pemikiran tasawuf dan filsafat. Pertemuan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada karya tulis al-Jili, al-Insan al-Kamil. Pertemuan itu terjadi karena antara tasawuf dan filsafat keduanya memandang objek yang sama tentang manusia, yakni bahwa manusia itu memiliki dua dimensi; dimensi lahir yang bersifat materi dan dimensi batin yang bersifat immateri.
Dimensi batin memiliki dua daya, yaitu akal (nazhariyah) yang berpusat pada otak dan daya rasa (dzawqiyah) yang berpusat pada qalb, masing-masing sebagai sarana menuju Tuhan. Pemikiran tasawuf dan filsafat juga mempunyai titik tekan yang sama dalam melihat manusia, yakni memiliki kecenderungan untuk melihat objek manusia yang bersifat immateri.
Dimensi immateri ini dipandang sebagai substansi dari manusia. Manusia mempunyai makna apabila dimensi substansialnya ini masih ada. Akan tetapi, jika sudah lepas dari diri manusia, maka sudah dikatakan mayat.
Sebagaimana layaknya seorang muslim, al-Jili senantiasa mendasari pandangan-pandangannya pada al-Qur’ann dan al-Hadits, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pendasaran pandangan-pandangannya terhadap al-Qur’an dan al-Hadits secara tidak langsung tampak lebih dominan.
Maksudnya, al-Jili lebih cenderung mendekati teks-teks wahyu dengan pendekatan substansial. Dalam arti, ketika ia mengartikan ayat tidak melalui makna harfî, akan tetapi mencari makna yang terdalam dari ayat tersebut. Makna-makna ayat yang diungkapnya sangat terkait dengan kecenderungan dan pemikiran-pemikiran dasarnya. Inilah yang senantiasa memengaruhi pemahamannya terhadap teks.
Landasan pemikiran al-Jili terhadap al-Qur’an dan al-Hadits dari semua hasil pandangannya tentang konsepsi al-Insan al-Kamil ditegaskan dalam sebuah statemennya yang menyatakan bahwa, setiap ilmu yang tidak didasari oleh al-Kitab dan al-Sunnah adalah sesat.
Akan tetapi, menurut al-Jili, kebanyakan manusia dalam mengkaji kitab-kitab tasawuf tidak mengetahui pertaliannya dengan sumber asal (al-Qur’an dan al-Hadits) karena kepicikan wawasan dan keilmuannya. Sehingga, timbul persepsi yang salah tentang berbagai konsepsi yang ada dalam pemikiran tasawuf.
Apabila al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar atau landasan pemikiran al-Jili, maka ta’wil, pengalaman ruhani dan al-Saqafah al-Sa’idah adalah metode dan sumber inspirasi al-Jili dalam merumuskan dan menghasilkan konsepsinya.
Ada perbedaan mendasar dari metode ta’wil yang digunakan oleh kalangan mutakallimun, yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok Mu’tazilah dengan kalangan sufi falsafi. Mu’tazilah dengan metode ta’wilnya menarik pengertian teks ayat pada pemahaman yang bersifat rasional. Sedangkan para sufi menarik pengertian ayat pada pemahaman yang bersifat dzawqiyyah (rasa), di mana rasa sebagai hasil dari pengalaman rohaninya. Mereka menyangsikan kebenaran ta’wil melalui pemikiran, penalaran dan logika.
Ta’wil menurut para ahli tafsir adalah menyingkap makna yang tertutup (tersembunyi, tersirat). Ta’wil juga dipahami sebagai mengalihkan makna ayat pada makna yang sesuai dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya, makna yang dimungkinkan oleh ayat tersebut tidak bertentangan dengan al-Kitab dan al-Sunnah melalui cara istinbath.
Karena itu, ta’wil sering kali berkaitan dengan istinbath, sementara tafsir umumnya didominasi oleh naql dan riwayah. Pembedaan ini mengandung satu dimensi penting dari proses ta’wil, yaitu peran pembaca dalam menghadapi teks dan dalam menemukan maknanya.
Peran pembaca di sini bukan sebagai peran mutlak, dala pengertian melalui ta’wil teks ditundukkan pada kepentingan subjektif. Ta’wil harus didasarkan pada pengetahuan mengenai beberapa ilmu berkaitan erat dengan teks, yang termasuk dalam konsep tafsir. Mu’awwil harus mengetahui benar seluk-beluk tentang tafsir, sehingga ia dapat memberikan ta’wil yang diterima terhadap teks. Yaitu ta’wil yang tidak menundukkan teks pada kepentingan-kepentingan subjektif, kecenderungan pribadi, dan ideologinya.
Seperti hermeneutika klasik dalam tradisi Barat, ta’wil di dalam tradisi Islam tumbuh dari latar belakang pemikiran yang memandang bahwa, bahasa merupakan wadah makna, dan adanya kesadaran bahwa semua teks keagamaan atau kerohanian memiliki makna batin yang tersembunyi di balik ungkapan lahir.
Dalam sejarah tasawuf, tradisi ta’wil bermula dari ikhtiar orang arif untuk memahami al-Qur’an secara lebih mendalam. Menurut mereka, ayat-ayat al-Qur’an digolongkan kedalam beberapa jenis, dan untuk tiap-tiap jenis diperlukan metode pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda.
Sebagai metode penafsiran atau ilmu tafsir, pada awalnya ta’wil dirintis oleh Ja’far al-Shadiq pada abad ke-8 dan kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh hermeneutika seperti, al-Sulami, Sahl al-Tustari, al-Qusyairi, al-Ghazali, Ibn Arabi, Rumi, Ruzbihan al-Baqli dan lainnya.
Sumber pemikiran al-Jili yang berasal dari al-Saqafah al- Sa’idah, lebih banyak didapatkan dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh gurunya melalui kitab-kitab karangan Ibn Arabi seperti, al-Futuhat al-Makkiyah dan Fushush al-Hikam dan sufi-sufi lainnya. Di samping ia juga menelaah secara langsung kitab-kitab para sufi tersebut.
Semuanya tampak melatarbelakangi lahirnya konsep al-Insan al-Kamil. Apabila dilihat corak pembahasannya, maka karya-karya tersebut adalah perpaduan antara filsafat dan tasawuf. Dengan demikian, filsafat juga merupakan sumber pemikiran al-Jili yang tidak langsung.
Sebenarnya, jika sumber-sumber tersebut ditelusuri lebih jauh, maka konsep yang dihasilkan para sufi sebelum al-Jili seperti, Ibn Arabi dengan konsep Wahdah al-Wujud, al-Busthami dengan teori al-Ittihad dan al-Hallaj dengan konsep hulul dan teori kenabiannya, serta al-Ghazali dengan teori cahayanya yang ada dalam kitab Misykah al-Anwar adalah kesinambungan pemikiran dengan filsafat Islam yang menyatakan bahwa, alam semesta ini berasal dari pancaran Tuhan. Hal ini tentunya sebagaimana dikemukakan oleh al-Farabi, sedangkan teori itu sendiri dipengaruhi oleh filsafat Plotinus dan Plato. Wallahu a’lam bisshawab. []