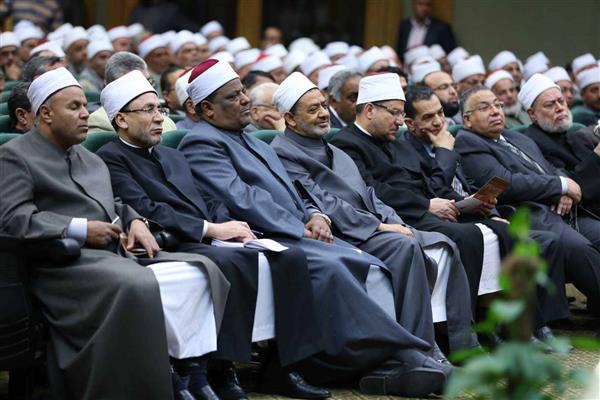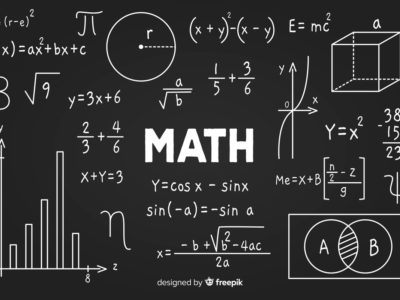Dulu, dulu sekali sebelum saya berangkat mondok, sekitar tahun 1998an, ketika musim kampanye adalah saat yang mendebarkan sekaligus menggembirakan. Mendebarkan karena bising suara knalpot blong para supporter partai politik akan menimbulkan kengerian bagi kami yang kebetulan bersimpangan arah ketika dalam perjalanan. Ada rasa kwatir yang besar bila mungkin ada sesuatu dalam kendaraan yang kami tumpangi ada sedikit saja tanda yang menunjukkan bahwa kami adalah pendukung partai lainnya.
Pun menjadi sebuah pertanda akan terjadinya kemacetan panjang, apabila kebetulan ada di belakang iringan mereka.
Namun kengerian dan kesebelan itu justru menjadi kegembiraan bagi jiwa kanak-kanak kami yang tidak sedang keluar rumah. Justru ketika tahu ada rombongan supporter partai politik yang akan pawai kampanye melewati jalan raya depan gang kampung, saya pasti dengan riang gembira berlari bareng dengan teman-teman menuju jalan raya, dan duduk tenang menunggu rombongan lewat. Tak lupa, kami akan bertanya kampanye partai apa yang akan lewat, dan simbol apa yang harus kami acungkan dengan jari kepada mereka. Acungan jari ini, biasanya tergantung pada nomer urut partai (yang mana waktu itu masih bisa diwakili hanya dengan jari satu tangan, tak harus meminjam jari kaki, atau bahkan jari teman di sebelah. Hehehe).
Sebenarnya ada hal lain yang juga sangat menggembirakan bagi jiwa kanak saya waktu itu, yaitu hiburan konser musik, dan yang paling utama: mendapatkan kaos gratis dan atau stiker dari partai politik. Tak peduli warnanya apa, dan tak peduli partai tersebut mewakili apa. Asalkan mendapatkan kaos gratis merupakan simbol kebanggaan bagi kelompok bermain saya waktu itu.
Semeriah dan sedahsyat apapun suasana kontestasi politik waktu itu, saya tak akan menemukan gaungnya ketika masuk ke lingkungan pondok. Saya hanya menemukan riuh perpolitikan dari koran yang menyebar di antara santri, juga diskusi-diskusi kecil dari segelintir santri. Selebihnya semua seperti tertelan dalam suara qori’ (pembaca kitab) di masjid, dan suara lalaran para murid madrasah diniyah ketika menadzamkan (menyanyikan bait-bait syair berbahasa arab yang berisi tentang materi pelajaran, biasanya ilmu gramatika arab) hafalan mereka.
Semakin besar, semakin saya faham bahwa bapak memang sangat menjaga netralitas pondok dari hingar bingar politik praktis. Bapak sering mengingatkan, bahkan dengan keras, kepada para pengurus dan para santri untuk tidak ikut-ikutan dalam pergulatan politik secara langsung ketika di pondok. Apabila ada santri yang ikut kampanye, maka dia akan ditakzir oleh keamanan pondok.
Pun ketika ada beberapa pengurus partai politik yang datang menawarkan posisi atau materi kepada bapak, maka pasti akan ditolak dengan halus oleh beliau. Bapak akan selalu menjawab bahwa maqam (saya belum menemu kata ganti yang tepat untuk menggambarkan kata maqam ini) beliau adalah ngaji. “Kulo tak ngaos mawon (saya tak ngaji saja)”, seringkali hanya begitu jawab bapak kepada para pengurus partai yang datang.
Tak hanya pengurus partai daerah, bahkan pernah datang seorang kiai besar yang terkenal menjadi dai skala nasional, yang juga telah menjadi pengurus pusat suatu partai politik mengajak bapak untuk ikut masuk dalam partainya. Dan ketika bapak matur seperti biasanya, sang kiai besar tersebut malah marah-marah dan mengeluarkan beberapa dalil agama juga dalil lainnya yang mengatakan bahwa kiai harus masuk partai politik. Bapak dianggap kurang bertanggung jawab pada lingkungan, pada umat, bila tidak ikut terjun langsung di partai politik.
Bapak hanya diam sambil mendengarkan apa yang kiai besar itu sampaikan, dan ketika ceramah sang kiai besar sudah selesai, bapak tetap tidak mau menerima ajakan beliau. Sang kiai besar langsung pamit pulang dengan kecewa.
Saya sendiri tidak pernah tahu alasan pasti kenapa bapak memilih untuk netral disetiap kontestasi politik di daerah kami. Beliau selalu ngendikan:”aku gak milih sopo-sopo, tapi sopo wae seng sowan mrene jalok dungo, yo tak dunga’ne (saya tidak memilih siapa-siapa. Akan tetapi siapapun yang datang sowan kesini untuk meminta doa, maka pasti akan saya doakan)”. Namun justru tanpa disangka-sangka, dalam pengajian ihya’ suatu ketika, beliau pernah ngendikan:”Kengeng nopo santri mboten kulo angsali nekani acara masalah politik. Enggeh lek pilihan politik e sami, lek mboten kan geh mboten sekeco kulo (alasan kenapa para santri tidak saya izinkan untuk mengikuti acara yang berbau politik adalah, karena saya berfikir, kalau memang pilihannya sama dengan saya tidak apa-apa. Akan tetapi kalau tidak sama kan saya yang tidak enak hati kepada mereka)”.
Sebuah alasan sederhana, namun sangat tepat menurut saya. Banyak sekali terjadi, dimana seorang santri yang masih mondok atau mungkin sudah kembali ke rumah, dengan terpaksa memilih satu partai atau satu calon pemimpin daerah atau bahkan negara, karena disuruh gurunya. Dia sebenarnya punya pilihan lain, namun takut dianggap tidak hormat pada guru, maka dia mengikuti petunjuk gurunya.
Saya tidak menyalahkan bila ada guru atau kiai yang menginstruksikan santri-santrinya untuk memilih satu partai politik atau satu tokoh calon pemimpin. Karena mungkin sang guru tersebut berniat membantu santrinya, yang telah dianggap selayak anak-anaknya sendiri, untuk memilih yang terbaik menurut beliau. Meskipun, bila diizinkan memilih, maka saya akan memilih berprinsip seperti bapak. Tetap netral saja, dan tidak mendukung kubu manapun di setiap kontestasi politik.
Tetap menyalurkan hak pilih, namun cukup itu menjadi pilihan rahasia pribadi saya.
Bapak hingga kini, dan semoga selamanya, istiqomah memilih jalan pedangnya dengan mengaji. Di masjid, madrasah, dan juga di rumah. Saya sendiri hingga kini masih tergopoh-gopoh mengikuti beliau dari belakang. Meskipun belum seteguh dan setekun beliau. Apalagi seistiqomah beliau, masih jauh sekali. Namun minimal saya mulai sedikit demi sedikit memahami pilihan beliau, dan selanjutnya menjadi pertimbangan saya untuk memilih jalan pedang pribadi dengan kesadaran penuh.
Proses pemilihan jalan pedang dalam berjuang ini selalu saya ingatkan kepada para teman-teman santri. Mereka adalah calon pejuang yang akan bertempur di medan laganya masing-masing. Tak terkecuali di medan laga perpolitikan. Saya tetap mendorong mereka jadi apa saja, karena memang seharusnya santri hadir di setiap lini. Namun satu pesan saya selalu: ”jadilah apa saja, dan dimana saja. Akan tetapi tolong selalu ingat jiwa santri kalian. Karena hal tersebut yang akan membedakan antara kita, dan yang lainnya. Jangan sampai melanggar hal-hal yang telah dilarang, karena itu justru akan mencoreng muka kita sendiri. Para santri”.
Semoga kita menjadi pejuang tangguh di setiap medan laga yang kita pilih untuk berjuang di dalamnya. []