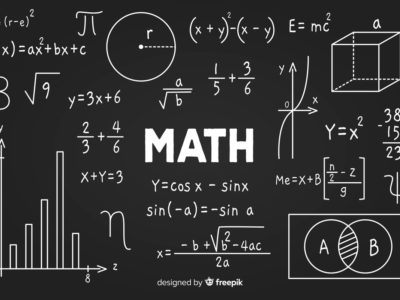Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan menolak kemungkaran. Datangnya Islam adalah bentuk kecintaan Tuhan (teosentrisme) untuk menjawab segala persoalan manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan (antroposentrisme).
Dua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam keberislaman seseorang. Di mana seseorang mengimani Tuhan, di saat bersamaan pula ia mencintai sesama.
Islam menempatkan ihwal kemanusiaan dalam sublim penghambaan yang luhur dan ‘arif sebagai manifestasi ketakwaannya kepada Tuhan. Beragama berarti menumbuhkan spirit kemanusiaan, bukan melakukan kekerasan kepada sesama dengan dalih agama.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Orang Islam adalah seseorang yang dengan lisan dan tangannya menciptakan kedamaian terhadap pihak lain”.
Kekerasan dan Ujian Keberagamaan
Saat ini, kelindan kekerasan atas nama agama banyak bertebaran tidak terbendung. Islam di Indonesia dalam putaran revolusi bumi belakangan ini sedang diuji oleh tuhan dalam beragam kelindan paham berislam yang menyimpang, baik masalah teologis, filosofis, dan sosiologis keberagamaan.
Sehingga perbincangan mengenai Islam yang damai dan humanistik dalam konteks berislam Indonesia kekinian. Ujian agama demikian mewujud dorongan moral untuk mereinterpretasi paham berislam yang kaffah dan mengasosiasinya dalam kehidupan berbangsa
Kita menyadari bahwa kepentingan manusia saat ini acap kali berdalihkan agama. Kekerasan, baik bentuk wacana maupun fisik, banyak berseleweran berlandaskan distorsi tafsir tekstual-skriptisis (radikalis)/kontekstual-liberal (liberalis) terhadap nash al-Quran dan sunnah al-Hadits.
Dalam hal ini, Islam bukan lagi agama sebagai karya agung Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. menjadi risalah kepada seluruh umat manusia, melainkan mewujud ideologi keagamaan pihak tertentu.
Kekerasan sekarang bukan lagi menjadi pelarian alternatif sebagai jalan terakhir untuk melawan kemungkaran. Kekerasan sudah bertransformasi menjadi “nalar kekerasan” karena mencari dalil sebagai legitimasi atas revolusi, menjadi “budaya kekerasan” karena menjadi pelarian tunggal dari permasalahan, dan manjadi “agamaisasi kekerasan” karena terus merasa absah melakukan kekerasan atas nama agama.
Hal ini tentu bertentangan dengan al-Quran surah al-Hujaraat ayat 13:
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
Mengaktifkan Daya Kritis Muslim
Dari sini, dipandang perlu menghidupkan kembali daya kritis sebagai seorang muslim tanpa menafikkan apresiasi terhadap kreasi keberagamaan. Seperti seorang intelektual muslim Indonesia, Aksin Wijaya, yang menawarkan Islam yang humanistik-argumentatif dengan cara melepaskan tafsir tunggal dan otoritatif terhadap pesan Tuhan dalam al-Quran.
Selaras dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib, bahwa al-Quran adalah “seribu wajah” dari pesan Tuhan kepada umatnya. Itu bentuk otoritas manusia yang diberikan Tuhan untuk menemukan tanda-tanda keagungan-Nya.
Maka, sudah seyogianya al-Quran dilepaskan dari kecenderungan subjektif dan jeratan ideologis dengan terus menggali pesan Tuhan yang sakral dan universal, baik dengan hermeneutika historis, linguistik, filosofis, dan kontekstualis.
Dalam ihwal gender, misalnya, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisaa’ (4): 34 yang berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Aksin Wijaya memberikan kebugaran makna teks dengan metode pembacaan post-strukturalisme terhadap ayat tersebut.
Pertama, meletakkan lafaz “qawwam” pada struktur “cabang” dan mengangkat lafaz “ar-rijaal” dan “an-nisaa” pada struktur “pusat” dalam proses pemaknaan.
Selanjutnya, memaknai kedua kata tadi dengan konstruksi sosial yang saat ini sedang trend disuarakan, yakni “ar-rijaal” sebagai “maskulin” dan “an-nisaa” dengan “feminim”. Dengan itu, maskulin yang identik dengan keperkasaan patut mengayomi (qawwam) feminim yang identik dengan lemah lembut, terlepas dari kondisi biologis di antara keduanya.
Dengan ini, tidak didapati bias gender dan marginalisasi terhadap perempuan atas dalih agama (Aksin Wijaya, 2021: 19)
Juga perbincangan mengenai konsep bernegara khilafah Islamiyah yang kerap melahirkan ijtihad kekerasan. Hal itu didorong oleh sikap dialektika-dikotomis dalam memandang realitas dan kebenaran. Sikap dialektika menganggap bahwa tidak ada pendapat ketiga dalam potensi kebenaran, yang ada hanya “saya benar” dan “anda salah”.
Sikap dikotomis adalah menutup diri dari kemungkinan pendapat orang lain. Dua sikap ini mengakibatkan Islam didakwahkan dengan penuh kekerasan karena ingin mewujudkan kehendak purifikasi dan formalisasi agama.
Padahal jika ditilik sejarah pemikiran politik Islam dan dasar pijakan perpolitikan Islam dalam al-Quran maupun al-Hadits, tidak ditemukan dogma religius yang menentukan bentuk kenegaraan tertentu. Begitu juga tidak didapati kata yang menujukkan bahwa Rasulullah Saw. sebagai raja, melainkan sebagai penyampai risalah.
Maka, sejatinya mendakwahkan Islam di Indonesia tidak perlu diformalkan, tetapi dengan melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya lokal untuk mendatangkan maslahah ‘ammah (Gus Dur, 2020).
Jika kita menghidupkan kembali daya kritis sebagai seorang muslim, seperti yang dicontohkan Aksin Wijaya dengan “kebugaran hermeneutika” atau Gus Dur dengan konsep “Islam pribumi”, paham radikalisme dan paham senada tidak mempunyai ruang kebenaran dalam masayarakat untuk mengekspresikan kehendaknya.
Beragama di Indonesia akan hangat bergulir dari waktu ke waktu dalam bingkai keharmonisan humanisme.
Akhirnya, inti dari seorang muslim sejati adalah hadir menjawab permasalahan umat akan varian wacana beragama dalam konteks berislam Indonesia, seorang muslim harus dengan tegas membedakan di mana letak pesan esetoris Tuhan—yang tentu terus dicari—dan kosntruksi sosial dalam teks keagamaan.
Sehingga kita beragama dengan “Islam” bukan beragama dengan “pemikiran Islam” atau “ideologi Islam”. []