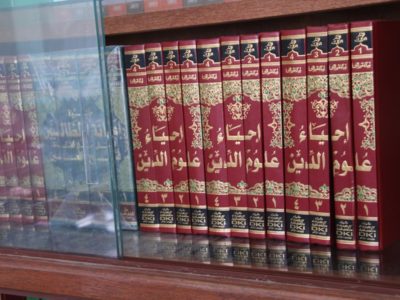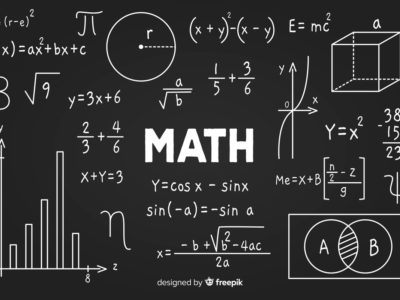Pada awal tahun 2022 kemarin, dunia riset di Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan terkait dileburnya lembaga-lembaga riset di Indonesia seperti Eijkman, Batan, BPPT dan kawan-kawan menjadi satu naungan yaitu BRIN (Badan Riset Nasional). Awal mula kehebohan tersebut banyak yang menyayangkan keputusan yang terkesan membunuh masa depan riset nasional karena harus memberhentikan pioner-pioner yang kontribusinya tak terhitung jumlahnya. Banyak yang memikirkan bagaimana nasib para pegawai yang belum berstatus PNS sedangkan mereka telah lama, bahkan ada yang mengabdi puluhan tahun, di lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan peleburan lembaga-lembaga ini hanya mengakomodir yang berstatus PNS dan peneliti yang memiliki kualifikasi pendidikan strata-3.
Memang riset di Indonesia selama ini seperti kurang memiliki tempat yang utama di hati Pemerintah dari tahun ke tahun. Anggaran riset yang digelontorkan oleh pemerintah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN maupun ASIA memang tergolong sangat rendah. Anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia paling rendah di antara negara-negara di ASEAN. Pada 2019 dan 2020, proporsi dana riset hanya 0,31 persen dari PDB, bandingkan dengan Singapura yang mencapai 2,64 persen atau Malaysia 1,29 persen dan di negeri Korea Selatan, anggaran penelitian dan pengembangannya mencapai proporsi 4,35 persen dari PDB . Banyak negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tren ekonomi global saat ini semakin bergantung pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini pula yang menjadikan para peneliti berpendapat bahwa riset bukanlah “fokus utama” pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa ini.
Apabila kita telisik lebih jauh, sebenarnya peneliti di Indonesia memang tak harus dan tidak seharusnya terlalu bergantung atau berharap terhadap Pemerintah untuk memperhatikan dunia riset di Indonesia. Hal ini karena memang Pemerintah pasca Reformasi hanya Presiden BJ. Habibie saja yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini. Presiden-presiden setelahnya sudah terlalu sibuk dengan urusan politik, ekonomi, dan permasalahan pribadinya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Suhadi Kholil dalam status Media Sosialnya, dengan nada geram ia mengatakan kenapa kita tidak mencontoh petani di Indonesia yang sejak puluhan tahun nasibnya tak juga menentu, meskipun merekalah aset berharga yang menopang kehidupan bangsa ini. Mas Suhadi Kholil juga mengatakan kenapa kita harus terlalu sibuk mengikuti permainan politik dalam riset dan lembaga riset Pemerintah? Lebih baik kita kerja tulus, dan berusaha meningkatkan kualitas riset yang kita miliki agar manfaatnya lebih terasa bagi kehidupan masyarakat luas dengan mengabaikan metakognisi yang tak dimiliki oleh orang “awam” di dunia riset.
Memang terkadang apabila kita melihat kekacauan politis dalam bidang riset di Indonesia rasanya membuat kita ingin menyerah dalam menekuni bidang ini. Akan tetapi setelah saya renungkan kata-kata Mas Suhadi Kholil saya berpikir, “Benar juga ya, sudah puluhan tahun petani negeri ini diberikan janji-janji yang manis yang ingin menyejahterakan kehidupan mereka dan tak kunjung terwujud, justru semakin hari kebijakan pemerintah lebih banyak merugikan para petani Indonesia. Sebagai contoh harga pupuk subsidi dan non-subsidi naik rata-rata 15 %, sedangkan cuaca ekstrim berupa La Nina sedang melanda Indonesia, yang tentunya mempengaruhi hasil pertanian.
Seringnya apabila terjadi lonjakan harga bahan pokok yang disebabkan oleh krisis komoditas pangan, maka para petanilah yang menjadi kambing hitam masyarakat dan Pemerintah. Tidak cukup sampai disitu, karena kegagalan para petani memenuhi swasembada pangan yang dicita-citakan oleh Pemerintah, dijadikannya untuk memotong anggaran subsidi bagi petani. Bukan hanya hal itu, seringnya para petani menjadi korban para koorporat atas bisnis perusahaan mereka dengan mengimpor hasil-hasil pertanian dari luar negeri yang hasil jelas lebih bagus dibandingkan dari petani dalam negeri, meski demikian para petani dengan sabar tetap bertahan hingga menjadikan anak-anaknya bernasib lebih baik”.
Kenapa pembahasan ini menarik bagi saya. Entah ini karena nasib yang sedang apes atau cuma kebetulan, karena menjadi peneliti dan petani keduanya adalah profesi saya. Seperti yang Putut Ea (Kepala Suku Mojok.Co) katakan, “hidup ini brengsek dan kita dipaksa harus menjalaninya”. Jadi seperti anekdot-anekdot yang beredar di media sosial, saya hanya berusaha bertahan hidup dari “tenangnya” hidup di wilayah pedesaan Kabupaten Kediri. Di mana profesi menjadi peneliti sekaligus dosen di bidang keagamaan hanya terlihat keren di mata masyarakat tetapi sangat memprihatinkan di dalam dompet. Sehingga terpaksa double job menjadi petani karena hal tersebut lazim dilakukan oleh para dosen di wilayah ini.
Banyak yang salah paham terkait profesi peneliti dan dosen ini, di mata masyarakat pedesaan memang cukup prestis tetapi sangat proletar di kasta dunia kampus. Lho kok bisa? Iya kasta tertinggi di dunia dosen sebuah universitas adalah para pejabat struktural dan para dosen senior, peneliti (apalagi pemula seperti saya) seringnya jadi “ban serep” ketika para pejabat dan para dosen senior tersebut membutuhkan “syarat” kepangkatan.
Saya pribadi sih menikmati saja menjadi “ban serep” tersebut, selain nambah pengalaman dan agar terus bisa belajar riset agar lebih baik, lumayan hasilnya bisa membeli pupuk untuk tanaman yang di sawah, yang harganya setiap harinya mengalami kenaikan yang signifikan –dan gaji menjadi dosen tidak akan cukup untuk menutupinya. Cerita ini hampir berbau-bau sadomasokis, seperti senang sekali menyengsarakan diri sendiri dan mengikuti sistem yang “sudah rusak sejak dalam pikiran pembuatnya”. Yang bisa kita lakukan sebagai peneliti hanya berharap di masa yang akan datang ada “seseorang sejenis presiden BJ.Habibie” dan ada petani yang bisa menjadi “Presiden”. []