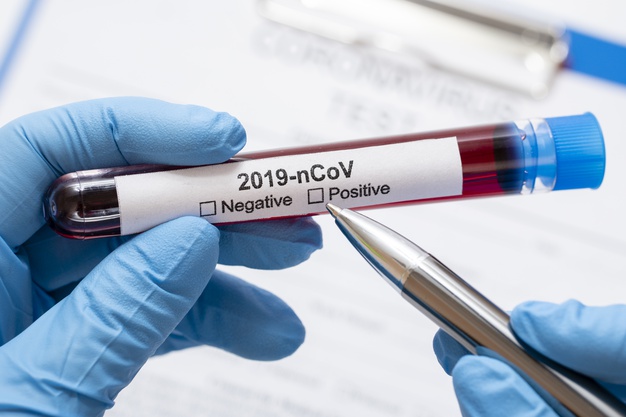Kita pasti pernah mendengar kisah tentang seorang Sahabat yang membiarkan untanya begitu saja, tanpa menambatkannya secara patut. Melihat itu, sang Nabi bertanya kepadanya, mengapa dia tidak menambatkan untanya. Sahabat itu dengan penuh percaya diri menjawab bahwa dia bertawakal kepada Allah. Dengan tegas dan penuh bijaksana,
Nabi dawuh:
Ikatlah untamu lalu bertawakkallah kepada Allah.”
Apa yang dilakukan oleh Sahabat di atas adalah gambaran dari paham teologi fatalistik. Teologi fatalistik adalah aliran teologi yang ajaran dasarnya memandang manusia seperti kapas yang gerakannya sepenuhnya ditentukan oleh arah angin. Jika angin bertiup ke barat, kapas itu akan bergerak ke barat. Intinya, ke mana pun angin bertiup, kapan akan bergerak searah.
Teologi fatalistik melihat manusia sepenuhnya sebagai agen pasif. Manusia sama sekali tidak memiliki daya untuk membuat pilihan dan melakukan ikhtiar (usaha). Dalam hidupnya, manusia sama sekali tidak memiliki pilihan, kecuali pasrah apa yang sudah ditakdirkan. Di sini, takdir dipahami sebagai ketetapan Tuhan, given, tak bisa diubah, dan harus diterima begitu saja dan apa adanya.
Cara pandang teologi fatalistik pada akhirnya berkonsekuensi pada makna keshalehan. Karena seluruh gerak dan sejarah manusia telah ditentukan oleh Tuhan, dan kesalehan adalah kepatuhan total terhadap seluruh ketetapan Tuhan itu, maka menjadi manusia shaleh berarti hidup tanpa ikhtiar. Dalam teologi fatalistik, keshalehan bersinonim dengan kepasifan hidup. Menjadi orang shaleh berarti tidak membuat pilihan-pilihan, tapi pasrah dengan ketentuan.
Menjadi orang shaleh dalam kerangka teologi fatalistik berarti tidak melakukan upaya-upaya, karena setiap upaya dianggap sebagai menentang keputusan Tuhan, atau setidaknya tidak menerima apa yang sudah ditetapkan Tuhan.
Sebetulnya, tidak ada manusia yang sungguh-sungguh penganut teologi jenis ini. Se-ngeyel apapun seseorang terhadap kebenaran teologi fatalistik ini, dia tidak akan berani sungguh-sungguh menerapkan dalam hidupnya secara konsisten. Tidak mungkin ada orang yang berani berjalan dengan penuh kepasrahan di tengah jalan raya saat kendaraan sedang berlalu lalang sambil meyakini bahwa jika Tuhan menakdirkannya untuk selamat, dia akan selamat begitu saja. Bahkan dalam urusan yang paling sepele pun seseorang pasti akan melawan teologi ini, misalnya, seseorang perlu menyuapkan makanan ke dalam mulutnya agar perutnya kenyang yang dengannya dia tetap bisa survive sebagai makhluk hidup, sekalipun dia meyakini sepenuhnya bahwa hidup dan mati adalah urusan Tuhan.
Mengapa teologi fatalistik gagal sejak dini? Jawabannya adalah karena dia mengingkari sunnatullah (hukum alam). Jika ada orang yang merawat kesehatannya agar tidak sakit, atau berobat saat dia menderita sakit, orang itu bukan sedang melawan takdir Tuhan, tapi melaksanakan sunnatullah. Sunnatullah ini merupakan hukum alam yang bisa dikenali melalui pengalaman pengindraan dan direfleksikan melalui rasio. Hukum yang dihasilkan melalui proses pengindraan dan rasionalitas inilah yang disebut dengan sains (ilmu pengetahuan).
Apakah sebelum ada sains, manusia tidak bisa mengenali hukum alam? Bisa! Manusia dengan perangkat indra dan rasionya sejak dulu telah mampu mengenali hukum alam. Itulah mengapa kita menemukan berbagai local genius (kecedasan lokal) dari nenek moyang kita. Yang membedakannya dengan sains adalah bahwa local genius itu tidak tersusun secara logis dan sistematis yang membuatnya bisa dibuktikan kebenarannya (verifiable) atau dibongkar kesalahannya (falsifiable) layaknya sains di era modern.
Jadi, bahkan pada masyarakat tradisional dengan tingkat pengetahuan yang rendah pun teologi fatalistik ini gagal memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengapa? Sekali lagi, itu karena teologi jenis ini bertentangan secara mendasar dengan will to survive yang merupakan kekuatan terendah manusia dalam memproteksi hidupnya.
Apakah teologi fatalistik memiliki manfaat? Jawabannya adalah “Ya”. Tapi, manfaatnya lebih bersifat personal daripada sosial. Dalam beragama, kita memerlukan sikap husnudhon (prasangka baik) kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah ini akan membuat seseorang memiliki kestabilan emosi dan ketenangan jiwa. Orang yang selalu berpasrah dan berprasangka baik kepada Allah lebih memiliki ketegaran dalam menghadapi gelombang kehidupan yang tidak jarang terasa menyakitkan.
Akan tetapi, sikap ini tidak bisa diseret melebihi batasnya hingga melahirkan sikap fatalistik dalam menghadapi hidup. Jika sikap pasrah kepada pemberian Tuhan diseret terlalu jauh, maka kita tidak akan melakukan upaya apapun dalam hidup. Tiba-tiba Tuhan dijadikan sebagai stempel atas kemalasan dan kebodohan-kebodohan kita.
Saat ini, ketika kita tengah menghadapi epidemi virus corona atau Covid-19, sikap fatalistik ini bisa berakibat fatal. Atas nama Tuhan, kita sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebagaimana yang disarakan berdasarkan protokol medis. Apalagi ada kecenderungan acara-acara keagamaan kolosal tetap dijalankan dengan dalih yang terdengar sepenuhnya bersifat fatalistik.
Alasan yang diberikan biasanya adalah: “Tuhan akan menyelamatkan kita karena kita sedang melakukan ibadah kepada-Nya”; atau “Jika Tuhan menghendaki, maka kita tidak akan tertular virus sekalipun kita melakukan kontak massif dengan orang-orang yang terinfeksi virus”.
Bayangkan, betapa bahayanya sikap seperti ini. Sikap fatalistik dalam beragama masih bisa diterima sejauh itu terkait dengan keshalehan individual. Namun, jika ia memiliki konsekuensi pada keselamatan orang banyak, hal itu sangat berbahaya. Di tengah epidemi corona seperti ini, teologi fatalistik jelas bisa berakibat fatal.
Jika ada orang yang ingin nderek dawuh (ikut sabda) tokoh agama, nderek-lah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad: “Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah!” Dalam konteks epidemi virus corona saat ini, dawuh itu bisa bermakna: “Ambil langkah yang tepat untuk melindungi dirimu dan orang-orang di sekitarmu dari infeksi Covid-19, lalu bertawakkallah kepada Allah.