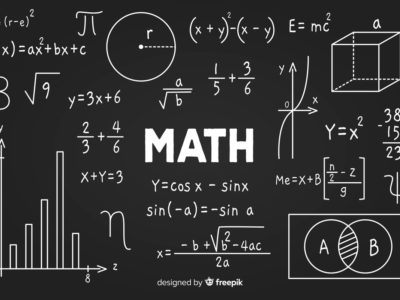Buku Kambing dan Hujan adalah buku kedua Makhfudh Ikhwan, setelah Buku Dawuk yang saya baca bulan lalu.
Keduanya sama sama menjuarai lomba elite sastra nasional yaitu ; Dewan Kesenian Jakarta dan Lomba Kusala Sastra Khatulistiwa.
Jika suatu hari saya bertemu dengan para juri lomba itu, saya ingin mengucapkan kata bangga, pinilaian anda sangat sangat tepat Pak!
Hihihi, pede amat? Siapa aku ini? Sudah jelas lah beliau beliau berkompeten dalam memilih.
Jujur, sudah bertahun tahun lamanya sejak saya manten anyar, saya mencari buku yang ceritanya sejenis kambing dan hujan ini.
Karena saya belum lagi menemukannya, saya coba gunakan logika lama (jika kamu ingin membaca sebuah buku dan kamu tidak menemukannya, maka… Engkau sendirilah penulisnya)
Dengan terpaksa, saya yang manten anyar itu mencoba menulis sendiri. Tapi karena terkendala waktu, keilmuan dan juga ruang gerak untuk riset. Saya pun meninggalkan tulisan saya sendiri itu dengan masih menyisakan harapan, barangkali suatu hari menemukannya.
Dan hamdalah sebulan yang lalu, sahabat literasi saya, owner Alalkids dan kopi Papupa, merekomendasikan pada saya buku ini.
Baru saja datang dari Pak Pos, saya tak sabaran membukanya. Dan ketika sampai pada lembar ketiga part awal, saya langsung jingkrak jingkrak. Horeee… Ini dia buku yang selama ini saya cari.
Oke, saya mulai cerita ya?
Jadi begini kisahnya, di awal part, kita akan disuguhkan drama, seorang gadis yang tengah harap harap cemas menunggu kedatangan seseorang dari seberang gang desa. Namun, ketika kemudian akhirnya lelaki itu datang, ia justru mengajaknya kembali pulang ke rumah dan menawarkan untuk mengantarnya kembali pulang.
Sambil cemberut, sang gadis terpaksa naik motor yang melenggang kembali masuk gang dengan berbisik “pokoknya harus sama kamu. Aku nggak mau yang lain”
“Ya, kita hadapi bersama, kita komunikasi dengan ortu baik baik” jawab si lelaki.
Berhenti disini, eitss. Jangan salah faham kalau ini kisan roman picisan ya! dengarkan dulu. Jauh jauh dari itu …
Lalu, novel pun menyuguhkan cerita flashback ke awal pertemuan, dimana gadis tsb, bernama Fauziyah Binti Fauzan berasal dari dusun Tegalcentong, bertemu dengan Muftahul Abrar Bin Iskandar dalam sebuah perjalanan dalam bus.
Hanya perkenalan biasa, antara dua manusia yang satu desa dan kebetulan ketemu di jalan.
Tapi rupanya, pertemuan biasa itu berujung pada kesan kesan yang tak biasa hingga lambat laun, keduanya mantap memilih datu sama lain untuk jadi pasangan halal.
Permasalahannya adalah, Fauziyah adalah anak Kiai Dusun Centong yang menguasai Masjid selatan yang beragama islam tradisional sangat kental (Baca; Wong NU) .
Dan Miftahul Abrar adalah, anak dari Pak Iskandar, Sesepuh dari Masjid utara dusun Centong, yang beragama islam pembaharu yang militan (Baca; Wong Muhammadiyah).
Fauziyah dan Mif yang telah jauh jauh kuliah ke surabaya dan Yogya, berharap kekolotan orang tua meluntur ketika menyadari anak anaknya berpendidikan tinggi dan jaman telah berubah. Meski tentu tersimpan cemas yang luar biasa dalam benak keduanya, karena Pak Kandar dan Pak Fauzan adalah Kiai yang sama sama kuat pada jamaah masing masing, dimana telah tercipta tembok kokoh antara masjid selatan dan utara itu. Alias tidak rukun. Tentu saja, hehehe
Meski nanti ketika keduanya telah mengutarakan niat masing masing, Fauziyah dan juga Mif tidak mendapat jawaban jelas dari ortu masing masing, tapi keduanya, tidak pula mendapat dampratan orang tua. Yang ada, kedua orang tua masing masing justru menceritakan sebuah kisah masa lalu, ya, 40 tahun yang lalu, sebelum mereka lahir ke dunia.
Kisah yang sangat dekat dengan sejarah penyebaran islam di Centong.
Alur cerita akhirnya masuk pada cerita yang dituturkan Pak Kandar, tentang anak bernama Is yang bersahabat sangat dekat dengan Mat, sering menggembala bersama di Gumuk Genjik, sampai kambing kambing Mat pun, Is yang memberikan nama.
Sayangnya, masa masa asik bersama itu akan segera berkurang ketika ahirnya Mat diantar ke pesantren oleh keluarganya, di sebuah pondok di jawa timur. Tetapi, mereka tetap dapat menyambung kerinduan dengan saling berkirim surat. Mat juga menghibur Is anak gembala yang cerdas dan miskin itu, dengan berkata, “kau tak perlu sedih Is, aku akan pulang membawakan banyak kitab dan kau bisa meminjamnya”
Dan memang benar, Is yang cerdas dan semangat itu memang akan selalu merindukan Mat beserta kitab kitabnya hingga ia akan melahapnya habis habisan ketika masa itu tiba. Mat selalu mengagumi kesemangatan Is dalam belajar, tak seharusnya ia hanya menjadi anak penggembala saja di rumah dan tak punya kesempatan untuk belajar ke pesantren.
Tahun demi tahun, persahabatan mereka tak pernah lekang oleh jarak.
Namun, pada tahun ketiga Mat di pondok, Is mengirim surat pada Mat, isinya mengabarkan bahwa Is sangat bahagia sekarang, karena telah datang lelaki muda bernama Cak Ali yang rela menghidupkan masjid dan mengajari Is dan teman temannya mengaji di Langgar. Cita citanya untuk dapat mengaji di desanya sendiri telah terwujud.
Mat turut bahagia dengan kabar itu, tahun demi tahun, ia melihat pribadi Is sangat lekat dengan tarbiyah Cak Ali.
Namun belakangan, Mat mulai mendengar desas desus gejolak perpecahan di dusun Centong yang disebabkan oleh ulah Cak Ali dan anak buahnya, yang berbeda dengan islam orang tua Centong pada umumnya, bahkan, mereka menunjukkan pemberontakan itu dengan membangun mushalla sendiri segala.
Mat yang meyakini kebaikan akhlak Is dan Juga idolanya, Cak Ali itu, ia tidak serta mempercayai info dari bapak nya tentang kerusuhan yang mereka buat.
Namun, pikiran Mat buat terbuka dikala ia dipertemukan dalam sebuah acara pesantren dengan Mas Ali Qomarullaili dari sunda.
Dari Mas Ali ini, Mat mendapatkan wawasan yang lebih luas. selain fokus menelaah seluruh materi pesantren, Cak Ali juga memasukkan pemahaman yang aktual, termasuk ilmu ilmu krusial dari Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asyari.
Lambat laun Mat menjadi faham, dengan siapa Is belajar di langgar Tegal centong. Dan kenapa para orang tua merisaukan kemilitansian Cak Ali dan bala balanya meskipun terkesan baik.
Antara Mat Dan Is sama sama memiliki tokoh spiritual dibalik perkembangan pribadinya, dan anehnya, kedua tokoh itu sama sama bernama Ali. Kebetulan yang unik bukan?
Hingga pada suatu hari, ketika perpecahan di Centong sudah semakin kuat, Mat Dijemput oleh Bapak dan Pakliknya untuk pulang Ke centong karena telah dianggap siap dan ditunggu masyarakat untuk berdakwah demi menanggulangi pemikiran sarkas dan menimbulkan perpecahan dari kaum pembaru tersebut.
Kisah masih begitu panjang dan pelik, karena dakwah Mat di dusunnya harus berhadapan dengan bala sahabatnya yang memang memiliki semangat pejuang. Tak bisa diremehkan.
Ah, rasanya saya ingin memotongnya sampai disini saja, dan mulai membuat kesimpulan sekaligus spolier, bahwa Mat adalah muhammad Fauzan ayah Fauziyah dan Is adalah Pak iskandar ayah Mif.
Ya, dulu sekali bapak mereka bersahabat sangat dekat. Dan ternyata keduanya adalah bagian dari pelaku sejarah penyebaran islam di Tegalcentong, dua masjid yang sama sama kuat itu.
Oya, aku lupa menyinggung soal Yatun, kembang desa yang ditaksir Is dalam surat suratnya untuk Mat. Belakangan, tanpa dinyana-nyana, Yatun justru menjadi istri Mat. Tentu saja itu semakin meregangkan persahabatan keduanya, meski pada kenyataannya, Mat sama sekali tidak menikahi Yatun dengan cara menikung. Hehehe
Jadi penasaran kan, sama alurnya?
Oke lanjut, sebenarnya, dalam tiap alur cerita Kambing dan Hujan, kita akan belajar cara berpikir tawasut seperti pemikiran penulisnya, ia menceritakan alurnya dengan detail tanpa sekalipun menghakimi tiap tokoh, tanpa tendensius kepada salah satu ormas baik itu MU atau NU.
Semuanya diceritakan, baik dan buruknya tiap tokoh, tanpa sekalipun terlewat. termasuk Mat yang terkena dampak jelek merokok di usia muda seperti umumnya santri jawa, juga termasuk sikap Is yang dikit dikit suka ngomongin bid’ah, layaknya ulama besar saja, padahal, ngaji di Langgar saja dia belum khatam.
Begitu kuat tokoh2 yang ada di dalamnya, sampai kita tidak masalah ketika mendapat nama nama berjejalan di dalamnya, kayak Lik Manan, Gus Dul (bukan Gus sperti yang kita tahu) Mujibat, Pak Kamituwo, Anwar dll dsb.
Menurut saya, penulis novel ini adalah seorang pecinta sejarah yang pantang menyalahkan orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Ia jadi sangat obyektif dan matang dalam berpendapat.
Tentu saja itu dapat mempengaruhi kita sebagai pembacanya.
Lantas,
Bagaimana dengan kisah Fauziyah dan Miftahul Abrar? Apakah orang tua keduanya merestui hubungan itu? bagaimana dengan masyarakat sekitar menyikapi kisah cinta keduanya yang dianggap terlarang?
Di akhir cerita, kita juga akan disuguhkan bagaiman euforia lebaran di Centong, yang selalu selisih satu hari antara masjid utara dan selatan, lalu kita pun disuguhkan olok olok antar masyarakat selatan dan utara yang koplak koplak, lucu lucu, macam meme-meme yang tersebar di instagram itu looh.
Kita akan sedikit menertawakan ketidakdewasaan kita sendiri dalam menyikapi perbedaan, bagaimanapun kita mungkin pernah terlibat kejadian serupa.
Hahaha.
Sekali lagi novel ini, membuat saya menangis sesunggukan karena novel ini merepresentasikan bahwa perbedaan itu rahmat, bahwa bagaimana pun kita adalah saudara, tidak semestinya perbedaan kecil melenyapkan ribuan persamaan yang patut kita renungkan.
Bahwa syariat adalah jalan. Dan perdamaian juga kasih sayang adalah tujuannya. Allah maha pengampun dan maha penyayang, seperti kutipan dalam mukaddimah kitab sullam taufiq (tujuan tujuan kita belajar adalah, mencari rida Allah, dan supaya kita sebagai manusia, saling menyayangi dan mengasih)
Berbeda pendapat dan beradu argumen itu sah sah saja, syaratnya dengan ilmu dan kedewasaan.
Dan ketika usai adu argumen tetap ditemukan perbedaan dalam sudut pandang, disebabkan oleh latar atau sosiologi, tetaplah bersabar dan hargai orang lain, kita tidak di lahirkan untuk mendikte orang lain, kita dilahirkan untuk mencari jalan menuju Allah.
Dan ingat, dalam Al-Quran, bukankah Allah menggunakan bahasa ‘jalan’ dengan kata jamak? Sehingga menyiratkan bahwa jalan menuju kepadanya itu memang tidak sesederhana 10 adalah 5 tambah 5.
Tapi, bisa jadi 1+9 atau 2+8, atau 4+6 dan lain dan sebagainya.
Ah, saya kira cukup sampai disini saja.
Maafkan saya sebagai pe-review yang masih abal-abal.
Selamat membaca,
Kambing dan Hujan.
***
Oya, sekedar info, saya juga memiliki cerita yang menyerempet tentang perbedaan cara berislam dalam Kumpulan cerpen Lipstick. Salah satunya, berjudul; Singapore Senja itu.
Antologi 175 halaman. Berisi 13 cerpen saya bersama teman literasi yang kini sedang pasca sarjana di Prancis. [HW]