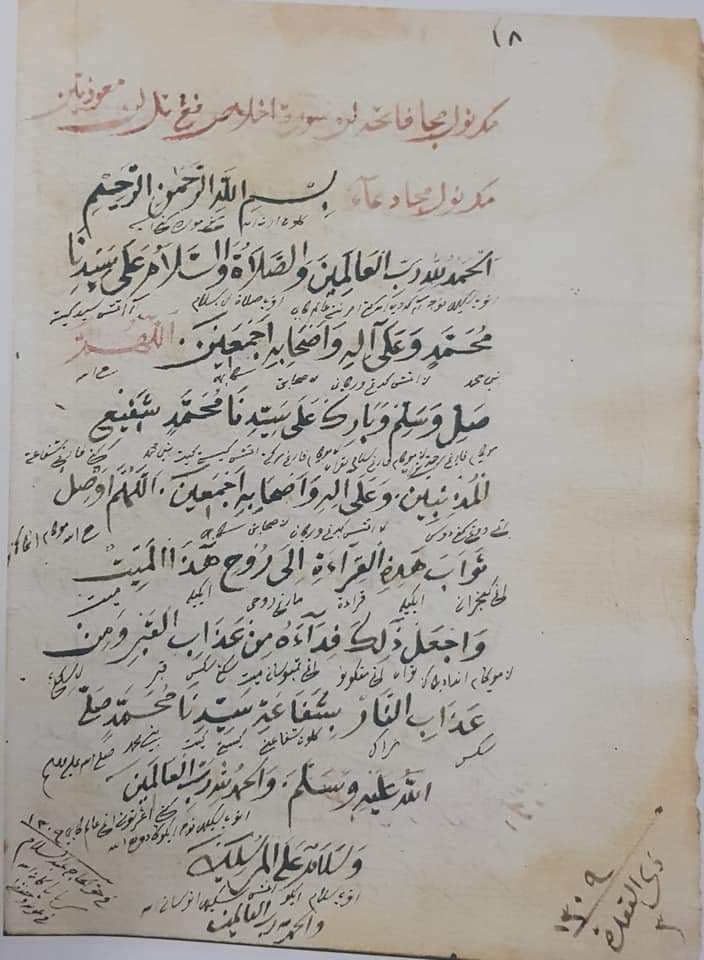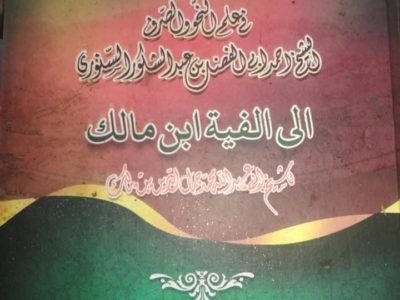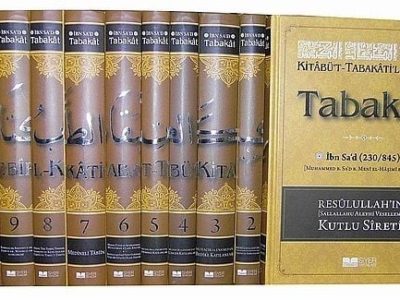Anda sering dengar kitab al Hikam kan? Itu adalah kitab tasawuf babon yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah as Sakandari, orang Mesir. Kitab al Hikam ini banyak dikaji oleh para kiai sepuh di banyak pesantren di Indonesia. Biasanya pengajian dilaksanakan secara mingguan atau selapanan (36 hari sekali).
Di Pesantren Tambakberas Jombang, Kiai Jamaluddin Ahmad mengadakan pengajian ini tiap malam Selasa. Seminggu sekali. Di Masjid Al Muhibbin itu beliau menjelaskan dengan detail apa yang dianggit oleh Ibnu Athaillah itu. Penjelasan itu seringkali disertai contoh dan permisalan yang sering mengena pada diri kita sebagai pribadi dan masyarakat.
Di Masjid kampung saya sendiri, Gus Rojih Ubab Maimoen (menantu Kiai Kafa Lirboyo) dari Sarang mengisi pengajian al Hikam tiap selapanan. Para jamaah yang sepuh yang tidak bawa kitab, mendapat lembaran foto kopian sedikit tentang materi yang sedang dikaji. Begitu juga dengan pamannya Gus Rojih, yakni Gus Wafi (KH. Wafi Maimoen) juga terkenal sering mengaji kitab al Hikam.
Gus Ulil Absor Abdalla, menantunya Gus Mus (KH. A. Mustofa Bisri Rembang) yang biasanya mengaji online kitab Ihya’ di bulan Ramadan (sudah sering mengadakan kopdar ngaji Ihya’), juga tak ketinggalan menerangkan isi al Hikam dengan ramuan bahasa yang renyah, dan terkumpul dalam buku “Menjadi Manusia Rohani”. Dan masih banyak lagi di beberapa pesantren dan majlis-majlis ta’lim lainnya.
Di Pesantren Lirboyo Kediri, pengajian al Hikam yang diikuti oleh para alumni ini disampaikan oleh KH. Anwar Mansur, sesepuh pesantren yang juga Rois Syuriah PWNU Jawa Timur. Pengajian ini disampaikan tiap selapan sekali. Tepatnya pada tiap Kamis Legi.
Pengajian al Hikam di Lirboyo ini berbeda dengan banyak pengajian di tempat lain. Kalau umumnya pengajian al Hikam ini dijelaskan dengan detail sedemikian rupa oleh Kiai yang membaca supaya para hadirin faham dengan isi kandungannya. Tapi tidak demikian di Lirboyo. Di Lirboyo mengaji kitab ini hanya diberi makna “gandul” saja. Seperti layaknya ngaji kilatan di pesantren-pesantren.
Padahal sebenarnya jika kita “hanya” ingin mendapatkan makna “utawi iki iku”, itu sudah banyak tersedia di toko-toko kitab. Bisa pilih makna ala Pondok Pethuk atau Pondok Kwagean. Kitab makna “gandul” dari dua pondok itu yang banyak beredar di pasaran.
Selain hanya diberi makna tanpa ada keterangan dan penjabaran, Mbah Yai Anwar itu sosok yang apa adanya. Maksud saya, jika beliau sulit memberi makna ya mengaku kesulitan. Bahkan dulu waktu saya masih nyantri, beliau terkadang “hutang” makna suatu kalimah yang tidak diketahuinya. Ini bagi saya sangat luar biasa, di tengah banyaknya orang dan ustaz-ustaz karbitan yang mengaku alim dan mempunyai banyak pengetahuan, juga bisa menjawab berbagai macam permasalahan, beliau bahkan mengaku tidak tahu dan sulit memahami suatu kata atau kalimat dalam sebuah kitab.
Bagi saya, sosok Mbah Yai Anwar inilah orang alim sejati, ilmuwan sesungguhnya. Kalau tidak tahu ya mengaku tidak tahu. Tidak asal menyampaikan apa yang tidak diketahuinya. Dan mengaku tidak faham dan tidak tahu itu sama sekali tidak mengurangi kealiman beliau.
Saya jadi teringat sosok Mbah Kiai Abd. Karim (kakek KH. Anwar Manshur) yang memberi makna kitab tanpa ada rujuk dhamir. Karena itulah, ada salah satu santri yang terbersit dalam hati dan meragukan kealiman sosok Mbah Yai Sepuh itu. Lantas Mbah Karim dawuh:
الضمير في الضمير فمن لم يعرف مرجع الضمير فليس له ضمير
“Dhamir itu di dalam hati, siapa yang tidak tahu marji'(kembali)nya dhamir, berarti tidak punya hati”
Santri yang ngrasani dalam hati tersebut seketika sadar akan kekhilafannya.
Jadi, sebenarnya apa yang didapat ketika para alumni yang jumlahnya ribuan itu datang mengaji al Hikam ke Lirboyo? Bahkan banyak dari alumni yang sudah menjadi pengasuh pesantren, punya santri ratusan bahkan ribuan, ada dosen yang sudah bergelar Doktor dan seterusnya. Bahkan saya yakin ada yang sudah memberi pengajian kitab al Hikam di daerahnya sana. Lantas, apa tujuan mereka dengan susah payah datang dari jauh (banyak yang dari luar propinsi) “hanya” maknani al Hikam beberapa menit saja?
Tujuan itu sejatinya bergantung masing-masing pribadi. Ada yang datang sekalian sambang anaknya yang sedang mondok di Lirboyo, ada yang kangen sudah lama tidak mengecup tangan kiai, ada yang ingin ketemu kawan lama dan sekedar ngopi di warung Dipokerti, Akrab, Juwet ataupun Nafis (sekaligus bayar utang. Hehe). Ada juga yang mengaji sekaligus melakukan lobi bisnis, lobi politik bahkan ingin lobi cari calon besan. Hehe. Ada juga yang memang murni ngalap berkah mengaji pada kiai sepuh dan diakhiri “sowan” ke maqbarah.
Bagi saya, tujuan terakhir inilah yang paling penting. Ngalap berkah. Kalau misalnya hidup kita di keluarga dan masyarakat “kurang bersih atau kurang baik” maka mengaji ini bisa jadi momen ngalap berkah dan membersihkan hal-hal yang kurang bersih tersebut. Namanya saja ngalap berkah, berharap adanya kebaikan dalam hidup. Kembali menjadi santri yang mencari berkahnya kiai dan berkahnya kitab-kitab salaf.
Mengembalikan jati diri sebagai seorang santri ini penting, mengingat hidup di masyarakat yang serba penuh persaingan. Terkadang sikut sana sikut sini. Lha kalau seorang alumni pesantren ingat bahwa ia adalah seorang santri, maka jangan sampai terbawa arus negatif di masyarakat. Seorang santri harus berada pada rel “shiratal mustaqim”. Itulah esensinya. Soal ngorok (ngopi+rokok), guyon, dan gojlok-gojlokan itu hanya sekedar bumbunya saja. Wallahu a’lam.