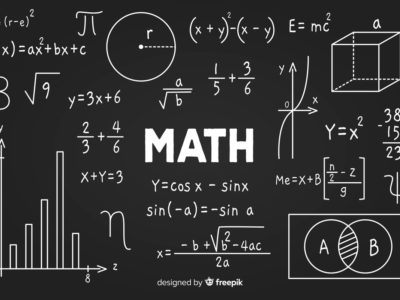Sejarah pembentukan Negara negara Muslim (khususnya setelah berhentinya kolonialisme Eropa), tidak dapat dilepaskan dari wacana pembentukan negara sebagai kelanjutan dari motivasi untuk menjunjung norma syariah. Maka, timbullah kemudian problem tentang interrelasi agama dan negara. Problematika interrelasi antara negara dan hukum Islam bukanlah suatu hal yang sama sekali baru jika ditinjau dari ilmu tentang negara atau ilmu tentang hukum (termasuk dalam khazanah studi ketatanegaraan Islam, (siyâsah syar’iyyah). Dalam khazanah ilmu ketatanegaraan Islam, minimal dikenal dua karya monumental, yaitu al-Ahkâm al-Sulthâniyyah al-Mâwardî (975-1058 M) dan al-Siyâsah al-Syar’iyyah Ibn Taymiyyah (1263-1328 M). Al-Mâwardî yang nama lengkapnya adalah Abû Hasan ‘Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-Mâwardî adalah ulama dari mazhab Syafii, sementara Taqiy al-Dîn Ahmad ibn ‘Abd al-Shamad ibn Taymiyyah adalah ulama mazhab Hanbali. Dari biografinya, al- Mâwardî dikenal sebagai hakim dan penasehat istana Abbasiyah. Sedang Ibn Taymiyyah lebih dikenal sebagai seorang pemikir independen yang dilingkupi oleh kekhawatiran akan terancamnya dinasti-dinasti besar Islam setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol (1258 M).
Terkait dengan negara dan hukum Islam, walaupun al-Mâwardî dan Ibn Taymiyyah berbeda mazhab, namun keduanya sepakat bahwa negara Islam (Muslim) harus sepenuhnya terikat kepada hukum Islam dan dalam negara yang demikian, maka supremasi syariah sebagai sumber dari segala sumber hukum dijunjung tinggi. Sementara terkait dengan kepemimpinan Islam yang tunggal, keduanya berbeda pendapat. Bagi al-Mâwardî, kekuasaan Islam itu harus berada dalam satu kepemimpinan (khilâfah) tunggal secara multinasional. Sedangkan menurut Ibn Taymiyyah kekuasaan Islam itu dapat saja terbagi ke dalam beberapa negara dan kepemimpinan (independent state) asal mereka merupakan negara yang saling terikat secara misi (semisal bentuk konfederasi/uni/persemakmuran). Terlepas dari persamaan dan perbedaan yang ada diantara keduanya, jika dianalisis dari sosiologi perkembangan pemikiran hukum, maka model pemikiran al-Mâwardî dan Ibn Taymiyyah dapat digolongkan ke dalam pemikiran dengan titik tolak pada upaya konservasi kesatuan umat Islam sebagai satu entitas hukum (legal entity) di dalam suatu negara. Dengan kata lain, corak pemikiran yang demikian adalah bagian dari cara yuridis demi mengokohkan solidaritas mekanis (mechanical solidarity, asas personalitas keislaman) berdasarkan syariah.
Model pemikiran hukum dengan pola konservasi solidaritas mekanis menghendaki agar masyarakat diikat oleh suatu aturan norma yang dianggap sebagai nilai bersama yang baku dan tercipta secara ilahi (given) dan final. Selanjutnya, negara diberikan kewenangan dan tugas utama sebagai penjaga nilai-nilai yang dapat menopang tujuan terciptanya solidaritas tersebut (al-dîn asâs wa al-imâm hârisuh). Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, pemikiran yang demikian dalam kurun waktu yang panjang telah hidup dan dapat dipertahankan sampai runtuhnya dinasti khilâfah Islâmiyyah terakhir dan terkuat serta terlama (lebih dari enam abad), yakni Turki Usmani pada tahun 1922 M. Runtuhnya dinasti Turki Usmani (1924 M), dominasi kolonialisme Eropa dan kegagalan untuk revitalisasi sistem khilâfah, mengindikasikan dengan jelas setidaknya dua hal, yaitu: (1) Dari perspektif geopolitik, bentuk kekhalifahan sebagaimana dipraktekkan oleh dinasti Turki Utsmani tidak mungkin lagi dapat berjalan. Seiring dengan itu, muncul perasaan dan ide kebersamaan (solidaritas) yang lebih berorientasi pada patriotisme geografis. (2) Menguatnya ide patriotisme geografis lambat laun memunculkan konsep kedaulatan kebangsaan (nasional).
Kedaulatan nasional, termasuk di dalamnya kedaulatan hukum, menghendaki adanya kontrak sosial kemasyarakatan dan konsensus sosial yang baru yang—ternyata—tidak dapat semata-mata didasarkan pada satu doktrin agama yang homogen karena heterogenitas masyarakat kebangsaan itu sendiri. Dengan kata lain, lahirlah ideologi nasionalisme dan terciptalah negara dengan pola dan semangat kebangsaan sebagai ganti negara agama (teokrasi) dan semisalnya. Dalam alur demikian masyarakat Islam terkonstruksi. Maka tidak mengherankan jika realitas yang terjadi hingga sekarang, fenomena negara kebangsaan (nation state) merupakan bentuk dari mayoritas negara-negara Muslim baru yang berdiri seiring dengan melemah dan lenyapnya kolonialisme Eropa. Negara kebangsaan tersebut diikat oleh standarisasi norma dan nilai yang merupakan derivasi dari semangat dan ideologi nasionalisme.
Dalam konteks semangat kebangsaan, nasionalisasi hukum secara lambat tetapi nyata berjalan di seantero negara-negara baru tersebut. Sebagai hukum agama yang dikonstruksikan dengan tujuan terciptanya dan terjaganya solidaritas mekanis (mechanical solidarity) dengan pengaturan pola-pola interaksi antar subyek hukum yang telah ditetapkan atau ditafsirkan sebagai bagian dari wahyu, maka hukum Islam mendapatkan tantangan dan menimbulkan kompleksitas persoalan dari dan pada lingkungan makro sosial-politik negara kebangsaan tersebut. Akibatnya, dalam dinamika negara kebangsaan tersebut, hukum Islam pada aspek pidana (jinâyat) adalah hukum yang paling besar mendapatkan tantangan dan paling kecil, sulit, problematis dan rumit kemungkinannya untuk dapat diterapkan. Sementara, hukum personal (al-ahwâl al-syakhshiyyah) karena bersifat perdata dan secara langsung terkait erat dengan identitas personal-kultural diusahakan untuk tetap bertahan atau direformulasi, bahkan mengalami proses positivisasi dengan cara kodifikasi (taqnîn) dan institusionalisasi. Dengan kata lain, sesungguhnya proses kodifikasi dan instititusionalisasi hukum keluarga di dunia Islam tersebut cenderung ’dipaksakan’ sebagai agenda islamisasi yang dianggap masih mungkin dalam konteks sosial-kenegaraan yang secara radikal sudah berubah.
Wallahu Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq. [HW]