Mula ngelmu mulet patraping sarengat // Ilmu harus mengikuti aturan syariat
Mung arjaning dumadi // Agar membawa keselamatan hidup
Dadya pra manungsa // Sehingga umat manusia
Tinuduh mrih utama // Terbimbing menuju keutamaan
Utameng cipta pamuji // Keutamaan dalam beribadah
Bait-bait di atas adalah potongan Serat Sastra Gendhing Sultan Agung Pupuh Durma yang membuka buku anggitan Muhammad Arif Albani berjudul Santri Pesantren Indonesia Siaga Jiwa Raga menuju Indonesia Emas 2045. Buku tersebut adalah hasil pengembangan dari makalah yang ia presentasikan dalam kegiatan yang cukup bergengsi yakni, al Multaqo ad Dawli Lil Bahts ‘an Afkar ath Thullab wa Dirasat Pesantren (Mu’tamad) yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama pada 2021 sebagai rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional.
Buku bersampul cerah dengan corak merah putih serta potret santri memegang bendera Merah Putih tersebut jika dibaca dengan menggunakan semiotika hendak memberi arti bahwa pesantren dan nasionalisme merupakan dua entitas yang koheren dan selalu menguat-kokohkan satu sama lain. Arif membagi buku tersebut kedalam empat fregmen. Pertama, ialah fragmen potret pesantren era pra kemerdekaan. Kedua, fragmen sumbangsih pesantren pasca kemerdekaan. Sementara fragmen ketiga adalah potret kemandirian pesantren dan yang terakhir ialah fragmen bungai rampai gagasan pilihan dari peserta Mu’tamad 2021.
Dalam fragmen pertama, Arif mengelaborasi kapan Islam mulai masuk ke Nusantara, tepatnya di Kalingga Jepara pada abad ke 7 sekitar tahun 651 M yakni di masa kehalifahan Sayyidina Ustman ibn Affan (hal 7). Ia menuturkan bahwa penamaan pesantren sebagai tempat pendidikan keislaman senyatanya ialah bentuk adaptasi dari istilah Pashraman (ashram) pendidikan agama Hindu-Budha. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bisa berbaur dan tidak anti terhadap budaya di “luar dirinya”. Selama sebuah budaya tidak menyalahi syariat Islam, Islam dapat mengakomodirnya. Inilah yang disebut Presiden Soekarno, mewarisi apinya bukan abunya. Nilai Islam atau subtansi ajaranya dipertahankan, sementara bungkus dan hal yang bersifat luar bisa diwujudkan dengan berbagai rupa. Sederhanya, yang penting itu isinya bukan bungkusnya.
Pesantren ternyata tidak hanya menghasilkan individu-individu yang hanya mendalam pengetahuan agamanya, melainkan juga menghasilkan tokoh-tokoh teknokrat, pejuang kemerdekaan maupun negarawan. Itu bisa dilihat dari profil Pakubuwono II, Raden Ngabehi Ronggowarsito hingga Pangeran Diponegoro adalah para santri Pesantren Gerbang Tinatar Ponorogo. Sebuah pesantren yang telah berdiri di abad ke 14. Itu belum menghitung sekian tokoh Nasional lainnya semisal HOS Cokroaminoto lalu Bung Karno. Kesemuannya adalah hasil tempaan di surau-surau yang jauh dan terasing dari hingar bingar modernitas secara fisik, namun memiliki pemikiran-pemikiran yang revolusioner dan visioner.
Fragmen kedua bisa kita jumpai fakta bahwa terdapat banyak nama insan pesantren yang turut terlibat dalam kemerdekaan dan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa menyebut KH. Hasyim Asy’ari dengan Resolusi Jihadnya yang kemudian menjadi landasan teologis untuk melawan tentara sekutu yang memasuki Surabaya pada tahun 1945. Bahkan jauh sebelum itu, terdapat nama KH. Wahab Hasbullah yang telah memperkenalkan nama Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Spirit nasionalisme Kyai Wahab bergema sejak tahun 1916 dengan menggubah mars Syubbanul Wathan. Mars yang liriknya sangat patriotik dan nasionalis. Salah satu petikan syairnya ialah “Indonesia biladi anta unwanul fakhoma” (Indonesia negaraku, engkau panji martabatku) Hal 23.
Kyai Wahab bukan saja ikut menginisiasi bedirinya organisai Nahdalatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan ataupun Nahdlatul Wathan hingga Tasywirul Afkar (Organisasi intelektual), ia juga turut mendirikan organisasi Nahdlatul Tujjar yang memiliki konsentrasi membangun kemandirian ummat. Di sini menjadi kian jelas bahwa pesantren tidak hanya membangun dhahir tetapi juga batin. Ia tidak hanya membentuk segi intelektual maupun spiritual, bahkan lebih daripada itu ia berorientasi membangun kemaslahatan masyarakat luas, tidak hanya berpikir untuk diri semata (hlm 71).
Potret kemandirian pesantren menjadi fragmen yang cukup menarik disimak. Arief memberikan beberapa contoh pesantren yang tidak hanya fokus pada kegiatan tafaqquh fid din (pendidikan agama) melainkan juga aktif terlibat dalam usaha kemandirian pesantren. Sebagai contoh, ia menyebut Pondok pesantren Tanbihul Ghafilin Banjarnegara. Pesantren tersebut telah membangun kemandirian ekonominya dengan memiliki RSI Banjarnegara. Meski tenaga medis masih dari pihak “luar”, akan tetapi untuk administratif, kebersihan dan umum telah dikelola sepenuhnya oleh para santri. Tidak hanya itu saja, ponpes tersebut juga memilik lini bisnis lainnya, semisal air mineral dan bengkel las yang kesemuannya dikerjakan oleh para santri (hal 91).
Upaya-upaya semacam ini patut untuk diapresiasi dan dikembangkan di pesantren, mengingat kemandirian ekonomi mutlak diperlukan untuk menopang segala macam kebutuhan pesantren. Jika pesantren memiliki kreatifitas untuk mengembangkan berbagai usaha, tentu hasilnya akan sangat “terasa”. Sebab pesantren telah memiliki segmentasi pasar yang jelas, minimal komunitas pesantren sendiri. Belum lagi jika pesantren mengembangkan bisnis retail seperti Pesantren Sidogiri Pasuruan dengan Toko Basmalah-nya dengan melibatkan jejaring alumni, tentu ini bisa dijadikan percontohan bagi pesantren-pesantren pada umumnya.
Hadirnya buku yang dianggit oleh alumni Ponpes Tebuireng ini tentu makin menyemarakan khazanah kepesantrenan. Buku ini bisa dijadikan rujukan untuk mampu melihat dengan utuh apa itu pesantren. Keunggulan buku ini terletak pada keluasan penulis dalam menguak histori pesantren berkenaan dengan keberadaan pesantren-pesantren di masa paling salaf di bumi Nusantara ini. Ketekunannya menelisik dan mendokumentasikan sejarah panjang pesantren jelas harus kita acungi secangkir kopi. Penulis juga menyediakan bukunya di play store, yang membuatnya lebih mudah dan efisien bagi para pembaca untuk menjangkaunya. Bahkan dalam buku ini tersedia barcode untuk mendengarkan mars Syubbanul Wathan.
Setelah membaca buku ini, kian tergambar jelas bahwa Pesantren memiliki modal besar untuk mampu membangun bangsa, bukan hanya sekadar generasinya semata. Mimpi membangun bangsa dengan modal pendidikan pesantren jelas bukan sekadar utopia belaka. Tak berlebihan jika angka populasi santri kian menanjak dari masa ke masa. Boleh jadi isi benak mereka adalah, “Pesantren it’s my dream!”. []
Judul Buku: Santri- Pesantren Indonesia Siaga Jiwa Raga Menuju Indonesia Emas 2045
Penulis: Muhammad Arief Albani
Tebal Halaman: xxiv + 132 Halaman
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Penerbit Zahira Media Publisher.
Peresensi: Muhammad Saiful Umam







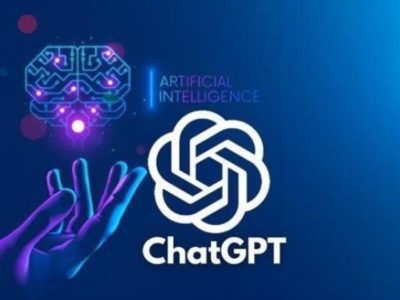
















Alhamdulillah…Mantap sangat