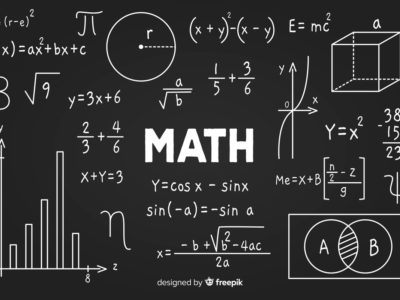Suatu ketika, Sayyidina Mu’adz bin Jabal radliyallahu ‘anhu memanjangkan salatnya. Beliau membaca Surat Al-Baqarah. Maklum, beliau masih muda. Semangat pula. Karena nggak tahan saking lamanya, salah seorang makmum mufaraqah (memisahkan diri), lantas salat sendiri biar lebih tingkat. Dia harus segera membereskan pekerjaannya sebagai peternak dan peladang.
Sayyidina Muadz bin Jabal radliyallahu ‘anhu lantas menudingnya bersikap layaknya kaum munafiq. Tidak terima dengan tuduhan ini, orang itu lapor kepada Kanjeng Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar pengaduan ini, beliau memanggil Sahabat Mu’adz dan memberi nasehat kepadanya agar memilih surat yang pendek apabila menjadi imam bagi para pekerja, lanjut usia, ataupun orang yang memiliki hajat. Boleh memperpanjang bacaan, asalkan pada saat shalat sendiri.
Dalam memberi peringatan dalam kejadian di atas, Rasulullah menyebut apabila di antara umatnya ada yang menjadi al-munaffirun atau orang-orang yang membuat orang lain lari menghindar dari agama. Pengennya berislam dengan tegas, tapi malah membuat orang lain jeri, jera, ngeri, phobia, dan menjauh dari Islam.
Coba kita cermati di medsos. Dalam kurun dua tahun terakhir banyak meme maupun artikel tentang Islam yang keras, sangar, dan kaku. Mengutip ayat secara serampangan, atau memutilasi hadis yang terlepas dari konteksnya.
Hadis tentang larangan isbal, misalnya, dibuat dengan meme yang khas. Biasanya juga disertakan iklan jualan celana cingkrang. Juga diberi komentar yang keras dan mengancam. Padahal dalam beberapa syarah hadits, para ulama memberikan ulasan mengenai konteks larangan isbal ini. Soal celana cingkrang, saya sih santai saja. Itu pilihan masing-masing orang. Dalam bersarung-pun, saya memilih untuk tidak isbal, atau tidak “klengsreh”, tidak menjuntaikan kain hingga lantai.
Dalam konteks lain, juga banyak. Misalnya kutipan fatwa ulama tertentu mengenai larangan menyematkan nama suami di belakang nama istri. Biasanya juga disertai dengan kutipan ayat dan hadis secara serampangan. Padahal, banyak pendapat ulama lain yang lebih lentur dan luwes mengenai kebolehan menambahkan nama suami di belakang nama istri. Misalnya, Ibu Tien Soeharto, Bu Khofifah Indar Parawansa, dst, sebagaimana adat di tanah air sejak dulu. Tapi, untuk menunjukkan “ketegasan” dan “keteguhan” sikap dalam beragama, ada di antara saudara-saudara kita yang memilih pendapat yang keras, kaku, dan garang lantas memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dalam banyak kasus yang saya jumpai, mereka yang menganut pola pikir semacam ini cenderung menjadi hakim bagi orang lain, tapi menjadi pengacara ulung bagi dirinya.
Kutipan ayat dan hadisnya benar, tapi salah penempatan. Ibaratnya, obatnya benar, tapi diagnosanya salah. Akhirnya overdosis. Juga malapraktik. Fatal. Padahal, ayat Al-Qur’an tidak bisa dilepaskan dalam konteks turunnya (asbabun nuzul). Karena itu butuh bantuan ulama untuk menguraikan isinya. Uraian ini disebut tafsir. Demikian pula dengan hadis. Kitab hadis berjibun. Karena memahami hadis juga butuh korelasi dengan realitas ketika diucapkan (asbabul wurud), maupun menguraikan maksud dari sabda Nabi, maka banyak sekali kitab syarah hadits.
Dari peristiwa seperti ini, yang banyak berseliweran di sekitar kita, saya ingat komentar Khalid Abou el-Fadl, cendekiawan Amerika bermadzhab Maliki, yang saya kutip dalam salah satu buku terbaiknya, “Musyawarah Buku”. Katanya, “….dari masjid ke masjid, aku menjumpai beberapa orang yang menganggap semakin keras dirinya dalam beragama, semakin saleh pula dirinya.”
*
Dalam beragama, level saya masih tahap awam. Karena itu saya suka membaca interaksi Kanjeng Rasulullah dengan para sahabatnya yang awam. Dari kelompok Badui, wong cilik, orang biasa, dan bukan dari kalangan Kibaris Shahabat.
Orang biasa, sangat biasa, badui, awam, memiliki cara masing-masing dalam meraih surga. Karena itu, ketika mereka ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, amalan apa yang bisa membuat mereka masuk surga, jawabannya beda-beda. Disesuaikan dengan konteks dan latar belakang penanya. Jika penanya tidak akur dengan orangtuanya, beliau menjawab amalan pengantar ke surga itu bernama berbakti kepada orangtua. Tatkala penanya kurang baik bertetangga, maka Kanjeng Nabi dawuh jika salah satu ciri penghuni surga itu adalah berbuat baik kepada jiran-nya. Jika si penanya merupakan sosok pemarah, maka Kanjeng Nabi dawuh jika salah satu amal utama yang dicintai Allah dan Rasul-Nya adalah menahan amarah. Bahkan, ketika ada pemuda yang meminta izin untuk berzina, Kanjeng Nabi pun menjawab dengan jawaban yang disesuaikan logika anak muda tersebut hingga mengurungkan niatnya melampiaskan nafsu di jalan yang dilarang.
Betapa beliau shalllallahu alaihi wasallam sangat “nguwongke uwong“, memanusiakan manusia, bahkan kepada anak-anak kecil, seperti Sayyidina Anas bin Malik, dan saudaranya yang bernama kunyah Abu Umair. Abu Umair, yang masih kecil ini punya burung peliharaan yang dikasih nama an-Nughair. Biasanya ketika berkunjung ke kediaman Abu Thalhah, ayahnya Abu Umair, beliau shalllallahu alaihi wasallam menghampiri anak kecil itu sembari menanyakan kondisi burung kecil peliharaannya, “Ya Aba Umair, ma fa’ala an-nughair? [Wahai Abu ‘Umair ada apa dengan si Nughair?”]. Dalam riwayat lain, ketika burung kecil itu mati, Kanjeng Nabi beberapa kali mengajaknya bercanda dengan menanyakan kabar burung kecil itu, hingga Abu Umair merasa diperhatikan oleh beliau.
Dalam interaksi semacam para sahabat yang polos ini, biasanya Rasulullah lebih banyak tersenyum, bahkan tertawa, karena keluguan mereka. Para sahabat yang polos, apa adanya, tapi loyal. Dari Badui yang lugu, orang miskin yang melanggar larangan bersetubuh di bulan Ramadan, ibu sepuh berkulit hitam yang menjadi takmir masjid Nabawi, hingga ahlus shuffah yang nderek Kanjeng Nabi dan sebagian menjadi abdi ndalemnya. (Interaksi keseharian Kanjeng Nabi dengan ahlus shuffah diuraikan dengan bagus oleh KH. Sholahuddin Munshif, pengasuh PP. Ali Ba’alawi, Kencong, Jember, melalui karyanya Ithafu Dzawi-l-‘Iffah Bi-Fadhaili Ahlis Shuffah).
Akhirnya, mari beragama dengan gembira, dengan bahagia. Wallahu A’lam Bisshawab. [HW]