Sesekali, tidak ada salahnya kita gunakan suryakanta rohani untuk menziarah-teladani sirah dan pekerti Kanjeng Nabi. Dari sanalah setidaknya filsafat kenabian akan kita dapati. Lazim kita ketahui bahwa para Rasul niscaya memiliki empat karakteristik utama, yakni pribadi yang kejujurannya paripurna (shiddiq), terpercaya serta memiliki integritas moral (amanah), penyampai risalah Ilahi (tabligh) alias tidak pernah korupsi ayat, serta memiliki kecerdasan agung (fathanah). Empat sifat ini menjadi modal bagi para Rasul, dan khususnya Nabi Muhammad Saw sendiri dalam membangun peradaban, terutama setelah beliau dan para sahabatnya hijrah ke Yatsrib (Madinah).
Bahkan, beliau adalah pribadi yang Al-Amin jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, hal ini benderang ketika beliau berniaga lintas negara ke Syam (Suriah) dan memang beliau tak pernah berdusta seumur hidup. Dan, dengan fathanah-nya, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau fiat disepakati bisa menyelesaikan konflik yang berujung pertikaian tribalistik dalam peletakan hajar aswad, pasca renovasi Ka’bah setelah Mekah diterjang banjir bandang. Hanya satu atribut yang beliau belum laksanakan dan menunggu risalah atau wahyu, yakni tabligh.
Nah, begitu sang Nabi menerima wahyu untuk tabligh—oleh karena itu beliau disebut muballigh (penyampai), satu gelar yang kelak banyak disalahpahami sebagai profesi oleh umatnya, terutama saat ini, di mana pseudo ustaz menjamur bak cendawan di musim hujan. Sebagai penyempai dan penganjur kesalehan, tentu Allah SWT membekali kecakapan nabawi dengan tugas profetik, yakni: “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi (1) saksi atas keesaan Tuhan (2) pembawa kabar gembira, (3) pemberi peringatan, (4) penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan (5) sebagai pelita yang menerangi.” (QS. Al-Ahzab: 45-46)
Bagaimanakah pengejawentahan nilai-nilai shiddiq-amanah-tabligh-fathonah dalam keindonesiaan kita hari ini? Sehingga, kalau kita membangun peradaban, tentulah peradaban yang profetik, kalau kita mencanangkan kurikulum pendidikan, pastinya kurikulum yang nabawi, sains profetik, sosiologi kenabian, kebudayaan yang insani, industri yang humanis,politik (meski agak sulit) yang profetik juga. Bisakah? Bagaimana memulainya?
Ada ujar-ujar Arab klasik bahwa pikiran adalah pangkal segala perbuatan (innama al-afkar ummahatul af’al). Itu artinya perubahan-perubahan besar pada pola sikap dimulai dengan mengubah pola pikir, tanpa terkecuali perubahan dan perbaikan peradaban manusia. Logika terbaliknya, kekacauan dan berbagai benturan yang terjadi dan menyelamatkan malapetaka di seluruh korpus negeri ini adalah berangkat dari pola pikir bangsa ini juga. Gaya hidup yang acakadut, birokrasi yang jauh dari mangkus dan sangkil, semua bermuasal dari pola pikir, dari filsafat hidup.
Namun demikian, dalam hemat saya, banyak yang masih sebatas formalitas saja meneladani baginda Nabi Saw, misalnya (maaf) pakaian, jenggot, atribut dan asesoris semata, mengapa bukan cara berpikir Nabi yang kita tiru, mengapa bukan kecerdasan nabawi dan filsafat profetik beliau yang kita duplikasi untuk kemudian kita jadikan kurikulum di sekolah-sekolah, khususnya lembaga pendidikan Islam?
Indonesia sebagai bangsa (dalam hemat saya) belum memiliki metodologi berpikir yang ajeg yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak usia dini, sehingga tindakan dan perilaku bangsa ini, misalnya yang kerap dipertontonkan oleh oknum-oknum pemangku kebijakan, sungguh tidak mencerminkan cara berpikir yang profetik, entah itu shiddiq, pun juga amanah. Tak percaya? Tengok saja betapa lembaga anti rasuah kerap dikadali buaya, difetakompli, diserimpung gerak-langkahnya, bahkan nyaris bernasib sama dengan klepon.
Sekali lagi dalam hemat saya (yang tidak hemat-hemat amat), jika pemerintah kini mencanangkan revolusi mental, perang melawan korupsi, white color crime dan extra ordinary crime lainnya, saber pungli, fullday school, dll., mengapa bukan kecerdasan ala Nabi saja yang kita canangkan dan dikurikulumkan secara berjenjang melalui lembaga-lembaga pendidikan? Pintar itu gampang, tapi jujur…?!
Dalam eksemplar sejarah Orde Lama, segar dalam ingatan kita “politik sebagai panglima”, sementara itu Orde Baru mencanangkan ”ekonomi sebagai panglima”, dan ironisnya, belakangan ini “agama menjadi panglima” dengan politisasi dan komersialisasi agama. Sampai-sampai, bencana alam, air mata sosial, perasaan bahagia, pengangguran, industri, kriminalitas, sains, kesenian, film, buku-buku, internet, politik dan semua aspek dalam hidup ini harus mendapat restu (lembaga) “agama” dan standar-standar tertentu dari pemangku agama. Apa yang kemudian terjadi? Sentimentalitas dan tak jarang berujung kekerasan atas nama agama.
Segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama merentang sejak 9/11, rangkaian bom bunuh diri, pembakaran gereja dan persekusi terhadap minoritas yang mencoreng-moreng agama hingga koyak-moyak dan boyak. Memang, kekuasaan, kekuatan, dan wewenang bagi terjadinya kekerasan ini sangat berjalin-jemalin dengan politik global, akan tetapi “kebangkitan” agama bukan lagi kebangkitan sebagaimana ia diwahyukan pertama kali dan diajarkan para Nabi. Alih-alih menjadi suluh, penjernih dan pendamai, (oknum) agamawan malah menjadikan agama sebagai pendeta, pengekang, dan segala bentuk banalitas lainnya.
Lagi pula, Sinergi antara agama dan nasionalisme yang tertuang dalam falsafah Pancasila “hanya” menjadi slogan, ia belum menjadi cara dan metodologi dalam pola pikir-pola sikap bangsa Indonesia, terutama generasi muda, generasi milenial, gen Z yang native internet dan teknologi yang kerap kepo (knowing every particular object), terjebak kerap meringkuk dalam candala dan ketaksaan sikap.
Akibatnya apa? Jelas, kita kerap bergerak ragu, jalan di tempat, terombang-ambing dalam harapan dan putus asa, terbawa candramawa, terbang hilang arah, melangkah hilang arti: disorientasi. Kabar baiknya apa? Meski belum signifikan, pesantren telah sejak lama mengajarkan falsafah kenabian. Cara berpikir profetik ini tercermin dalam sinergi antara akal dan wahyu. Lebih terang, negara adalah produk akal, agama adalah wahyu. Di Pesantren rintisan para ulama, hal ini telah lama sinergi. Hubungan antara Tuhan dan manusia, agama dan Negara telah lama berjalin-jemalin dengan damai dan indah.
Bukti nyata adalah—selain bentuk negara bangsa yang bernama NKRI—tak satupun dari santri pesantren (khususnya pesantren Nahdliyyin) yang menjadi teroris dan intoleran. Sudah saatnya cara berpikir Nabi ini kita ajar-sebarkan, tanpa kecuali di medsos, agar menyentuh aspek-aspek terdalam dari kemajuan dan sisi-sisi terjauh dari modernitas, baik itu bangunan ilmu pengetahuan, industri dengan berbagai revolusinya, serta berbagai gerakan-gerakan sosial. Sekurang-kurangnya, salah satu ajaran Nabi, seperti hijrah tidak disalahpahami dan kemudian dikapitalisasi dan menjadi gerakan pemutlakan pendapat, sampai-sampai roti, ayam goreng dan klepon harus menjadi mualaf. Oleh karena itu (sekali lagi melalui medsos), tutorial Berhenti Menjadi Abu Jahal harus sesering mungkin dipancar-tularkan. Apa sebab? Hijrah tak harus “melaju”, tapi juga “berhenti”, yakni berhenti merusak kemanusiaan kita sendiri, berhenti mengotori nur muhammad dalam diri.
Dengan filsafat kenabian, hijrah sangat mungkin digagas sebagai gerakan nasional untuk bangkit dari kesadaran dogmatis menuju kesadaran kritis, dari sikap religius tapi nyebelin menuju beragama dengan riang-gembira merayakan perbedaan pendapat, dari pembangunan segala apa yang dehumanistik menuju peradaban yang manusiawi. Jika tidak, agama dan Negara akan terus mengalami benturan dan ledakan, dan lamat-lamat bahtera besar bernama Indonesia akan karam oleh lubang-lubang kebocoran yang kita buat sendiri.
Bagaimana agar ber-Indonesia dan beragama dengan keren? Saran terbaiknya, ikut bedah buku saja, sambil makan klepon dan minum teh!. [HW]









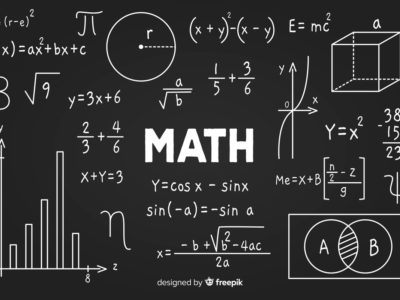














[…] Ada yang melihatnya dari perspektif komunikasi media, agama, hingga menggunakan alat analisis filsafat bahasa. Akan tetapi yang menjadi sorotan beberapa orang adalah ide kreatif dan etika pemasaran […]