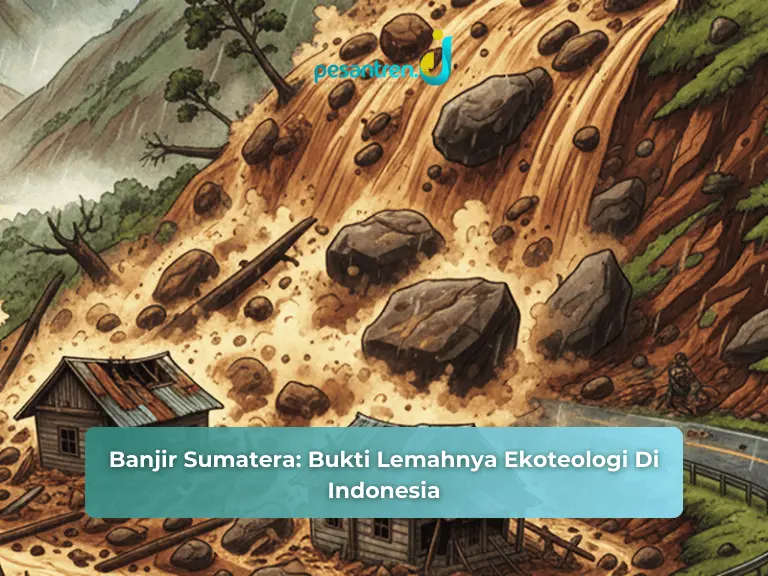Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan sekadar musibah alam yang datang tiba-tiba. Ia adalah potret telanjang dari rapuhnya relasi manusia dengan lingkungan, sebuah relasi yang dalam kajian ekoteologi semestinya diikat oleh kesadaran spiritual, etika ekologis, dan tanggung jawab moral terhadap alam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ekoteologi sebagai fondasi penghormatan manusia terhadap ciptaan belum sungguh-sungguh mengakar dalam praksis sosial dan kebijakan publik kita.
Banjir di Sumatera, baik di Sumatera Barat, Riau, Aceh, maupun Sumatera Selatan, hampir selalu memiliki pola yang sama: curah hujan ekstrem, hutan gundul, alih fungsi lahan, sedimentasi sungai, dan buruknya tata kelola lingkungan. Kombinasi faktor itu memperlihatkan bahwa manusia bukan hanya korban, tetapi sekaligus pelaku utama dari rangkaian kerusakan ekologis. Jika ekoteologi memandang alam sebagai entitas yang harus dihormati dan dirawat sebagai bagian dari amanah ilahi, maka banjir di Sumatera menunjukkan betapa amanah itu telah diabaikan.
Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Ar-Rum [60]: 41 yang menyebutkan bahwa "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia".
Frasa tersebut berasal dari Q.S. Ar-Rum [60]: 41, menuju pada entitas bahwa kerusakan ini terjadi akibat tindakan manusia seperti eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, pembunuhan, dan perbuatan maksiat lainnya. Tujuan Allah menampakkan kerusakan ini adalah agar manusia merasakan sebagian akibat perbuatannya, sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Permasalahannya adalah apakah manusia itu sendiri sadar dengan perbuatan yang telah ia lakukan.
Secara lengkap bunyi dari Q.S. Ar-Rum [60]: 41adalah:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Ekoteologi yang Gagal Menjadi Kesadaran Publik
Ekoteologi merupakan kajian lintas disiplin yang menggabungkan pemahaman keagamaan dan filosofi lingkungan. Ia menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak absolut untuk mengekspolitasi alam. Dalam banyak tradisi agama, bumi dipandang sebagai titipan, bukan milik mutlak. Sayangnya, nilai ini belum mewarnai perilaku kolektif kita.
Di berbagai daerah di Sumatera, deforestasi berlangsung masif dalam kurun dua dekade terakhir. Hutan-hutan dirambah demi sawit, tambang, dan pemukiman baru. Padahal, bagi masyarakat lokal, hutan dulunya bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang spiritual yang dihormati. Kini, relasi itu berubah menjadi relasi instrumen: alam hanya dipandang sebagai komoditas.
Ketika ekoteologi tidak menjadi kerangka berpikir yang membumi dalam masyarakat, maka keputusan-keputusan ekologis hanya didasari pertimbangan ekonomi jangka pendek. Dampaknya—banjir, longsor, hilangnya keanekaragaman hayati, dan rusaknya ekosistem—dirasakan secara nasional. Krisis ekologis yang berulang ini hanyalah gejala dari krisis kesadaran spiritual ekologis yang lebih dalam.
Eksploitasi atas Nama Pembangunan
Salah satu indikator lemahnya ekoteologi adalah cara pembangunan dijalankan. Banyak proyek di Sumatera mengusung narasi “kemajuan” tanpa memikirkan daya dukung lingkungan. Jalan dibuka menembus hutan lindung, tambang dibolehkan masuk ke daerah resapan, dan industri dibiarkan mengubah lanskap ekologis tanpa perhitungan jangka panjang.
Pemerintah daerah dalam beberapa kasus berada dalam posisi dilematis: tekanan ekonomi dan politik sering mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada investasi daripada kelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan kita belum inklusif terhadap nilai-nilai ekoteologi. Pembangunan seharusnya berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekadar pertumbuhan. Namun realitas di Sumatera membuktikan bahwa keberlanjutan masih menjadi jargon daripada prinsip operasional.
Di sinilah persoalan utamanya: ekoteologi tidak dilibatkan sebagai fondasi moral dalam kebijakan publik. Ia hanya menjadi wacana akademik, tidak menjadi pedoman kebijakan. Padahal, jika konsep ekoteologi dihidupkan dalam proses pengambilan keputusan, kerusakan ekologis dapat dicegah sejak awal.
Ketergantungan pada Darurat dan Logistik
Ketika banjir terjadi, respons yang sering muncul adalah bantuan logistik, evakuasi, dan status darurat. Tentu saja langkah-langkah tersebut penting untuk menyelamatkan nyawa. Namun, pola respons yang sama setiap tahun menunjukkan bahwa kita lebih sibuk memadamkan dampak daripada mencegah akar masalah.
Ekoteologi yang kuat seharusnya mendorong transformasi dari pola reaktif ke pola preventif. Ia mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab secara moral untuk memelihara keseimbangan alam sebelum bencana terjadi. Tetapi yang terjadi di Sumatera justru sebaliknya: kawasan resapan dibiarkan berubah menjadi perkebunan monokultur, sungai dikeruk pada musim kering tetapi dibiarkan penuh sampah pada saat musim hujan, dan masyarakat tidak dididik untuk memahami perilaku alam.
Ketika alam dipahami hanya sebagai objek, maka manusia lupa bahwa setiap kerusakan akan kembali menghantam mereka sendiri. Banjir Sumatera adalah “pesan ekologis” yang diulang-ulang, tetapi belum sepenuhnya kita baca.
Kerusakan Spiritual dalam Hubungan Manusia–Alam
Salah satu kritik paling tajam dalam ekoteologi adalah bahwa krisis ekologi merupakan krisis spiritual. Manusia modern hidup teralienasi dari alam: mereka merasa tidak lagi memiliki keterhubungan emosional, etis, maupun religius dengan lingkungan. Padahal, dalam banyak nilai kearifan lokal Nusantara, alam ditempatkan sebagai “gurator”—guru, pelindung, sekaligus penjamin kehidupan.
Di Sumatera, banyak komunitas adat yang sebenarnya memiliki prinsip pengelolaan alam yang bijak, seperti larangan menebang pohon besar, menjaga mata air, dan sistem ladang berpindah yang tidak merusak hutan. Namun, nilai-nilai ini kian hilang tergerus modernisasi yang tidak ramah lingkungan.
Jika ekoteologi difungsikan secara benar, ia dapat menghidupkan kembali kesadaran bahwa alam adalah bagian dari keberadaan spiritual manusia. Akan tetapi, tanpa revitalisasi nilai-nilai ekologis dalam pendidikan, agama, dan budaya, kerusakan akan terus berlanjut. Banjir hanyalah manifestasi dari “kekosongan nilai” tersebut.
Kebutuhan Mendesak: Revolusi Paradigma Ekoteologi
Banjir di Sumatera sebenarnya bisa menjadi momentum untuk melakukan rekonstruksi paradigma ekoteologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada tiga langkah strategis yang dapat digagas, yaitu;
Pertama, reinterpretasi ajaran keagamaan secara ekologis. Institusi agama memiliki peran besar dalam membentuk moral publik. Ajaran tentang amanah menjaga bumi, larangan merusak alam, dan keharusan memperlakukan lingkungan dengan kasih harus disampaikan dalam konteks hidup modern. Khutbah, kajian, dan pendidikan keagamaan perlu memasukkan ekoteologi sebagai materi penting.
Kedua, kebijakan lingkungan berbasis etika ekologis. Pemerintah perlu menempatkan etika ekologis sebagai prinsip utama. Setiap proyek harus dievaluasi bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi moral ekologis. AMDAL tidak boleh menjadi formalitas, tetapi instrumen etis untuk menentukan apakah sebuah proyek layak dijalankan.
Ketiga, revitalisasi kearifan lokal. Sumatera memiliki banyak tradisi ekologis yang harus dihidupkan kembali. Penguatan lembaga adat, pendidikan berbasis budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mengembalikan harmoni manusia–alam.
Banjir sebagai Cermin, Bukan Sekadar Bencana
Banjir Sumatera bukan sekadar bencana alam yang menyedihkan; ia adalah cermin yang memantulkan kelemahan ekoteologi kita. Setiap pohon yang ditebang tanpa pertimbangan, setiap sungai yang dijadikan tempat sampah, dan setiap kebijakan yang mengabaikan keseimbangan ekologis adalah langkah kecil menuju bencana besar.
Selama ekoteologi tetap menjadi wacana abstrak dan tidak menjadi kesadaran hidup yang dijalankan secara kolektif, maka banjir akan terus datang, semakin besar, semakin merusak, dan semakin menunjukkan bahwa manusia telah gagal menjalankan amanah menjaga bumi.
Banjir Sumatera adalah bukti. Kini tibalah saatnya menjadikannya pelajaran—sebelum alam mengambil alih dan menuntut dengan cara yang jauh lebih keras.