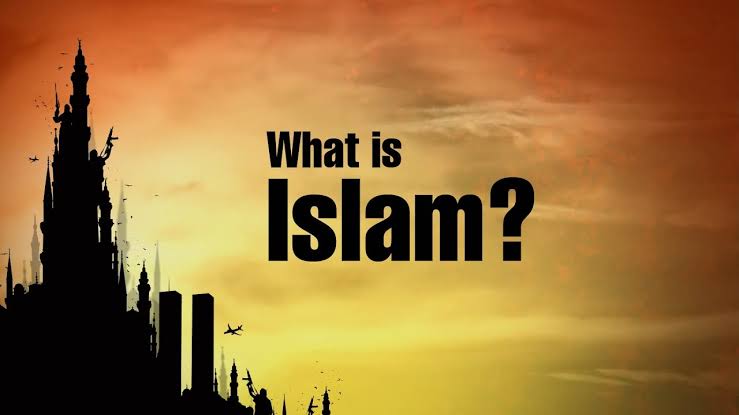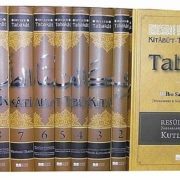اوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَاۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ
“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?”
Ayat ini ditafsirkan secara beragam oleh para mufassir, dari ulama klasik hingga kontemporer, berikut beberapa poin yang bisa kita kutip:
Pertama: Mula-mula Imam ar-Razi mengememukakan bahwa ayat ini menunjukkan dalil tentang eksistensi Sang Pencipta yang Esa, tanpa sekutu bagi-Nya. Susunan dan keteraturan kosmik tidak akan kita saksikan bilamana terdapat dua tuhan. Ayat ini ibarat penguat tentang ayat sebelumnya. Di sisi lain, ayat ini juga menjadi sebentuk penolakan kepada kaum pagan (ubdat al-autsān) yang menghaturkan ibadahnya kepada hal-hal yang tak mendatangkan manfaat atau bahaya sama sekali. Inilah hubungan antar ayat dengan pembahasan sebelumnya.
Terdapat persoalan dalam redaksi a wa lam yarallażīna kafarū, kata yara memiliki dua pengertian: “penglihatan indera” dan “pengetahuan”. Makna yang pertama tidak tepat sama sekali dalam konteks ini. Agaknya ia bertentangan dengan ayat dalam al-Kahfi: 51,
مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْۖ
“Aku tidak menghadirkan mereka (mahluk) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri…”
Karena tidak seorang pun tidak hadir dan melihat proses penciptaan, maka pemaknaan “penglihatan indera” tentu tidak tepat.
Sementara, jika diartikan “mengetahui” juga terdapat problem. Sebab, materi (ajsām) memang berpotensi berpadu atau terpisah, sementara justifikasi bahwa alam semesta mulanya berpadu lalu kemudian terpisah hanya diperoleh melalui informasi wahyu semata; padahal objek yang sedang diajak bicara adalah orang kafir yang tak mempercayai kabar samawi. Lantas, bagaimanakah menjadikan ayat ini sebagai argumen yang tepat dalam konteks ini?
Imam ar-Razi memberi tiga alasan untuk merespon persoalan ini: (a) Ketika kita menetapkan kenabian Muhammad Saw dengan seluruh mukjizat yang membenarkan hal tersebut, lalu kita jumpai rangkaian alam semesta yang sangat teratur dan indah, dan amat jauh dari keburukan dalam penataannya, tentu hal ini memperkuat argumentasi ketauhidan yang hendak dibangun. (b) Keterpaduan dan keterpisahan bagi alam semesta adalah sesuatu yang mungkin secara rasional (mumkin ‘aqly), sebab alam memang berpotensi memiliki sifat demikian, manakala alam terpatu secara aktual, atau terpisah, misalnya, tentu hal itu menunjukkan ada “sebab” yang mengaktualkannya. Karena sesuatu yang berstatus mungkin tidak bisa disebabkan oleh yang berstatus mungkin juga, niscaya ia disebabkan oleh sesuatu yang niscaya-ada. Dengan demikian, ayat ini sangat tepat untuk menunjukkan akan eksistensi Sang Pencipta. (c) Orang Yahudi dan Nasrani telah mengetahui informasi ini melalui kitab Taurat, karena di antara isi kitab tersebut terdapat penjelasan bahwa mulanya Allah menciptakan substansi tunggal (jauhar), lalu berubah menjadi air dan menjadi muasal bagi alam semesta. Sementara itu, mereka berada pada garda yang sama dengan orang kafir untuk memusuhi Nabi Saw, karenanya al-Quran memperuntukkan ayat ini kepada orang kafir, berdasar pengetahuan mereka yang diperoleh dari orang Yahudi.
Di lain tafsir, Syaikh Tabathaba`i memunculkan jawaban berbeda. Baginya, yang dimaksud dengan allażīna kafarū adalah orang-orang musyrik, yang menganggap bahwa Allah memiliki anak, atau ada tuhan lain selain Allah. Mereka memang meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam, tetapi pengaturan dan penataan semesta ini dilakukan oleh tuhan lain, entah malaikat, jin dan lain sebagainya. Karena itu ayat ini menjelaskan tentang kesatuan alam, pada mulanya, lalu memecah dan terpisah antara satu dengan yang lain, guna menunjukkan bahwa penciptaan memang tak pernah terpisah dengan pengaturan dan penataan alam. Sehingga asumsi orang musyrik tertepis sama sekali.
Kedua, Imam asy-Sya’rawi pandangan unik tentang ayat ini. Bagi beliau, ayat ini adalah anjuran untuk “merenungi” penciptaan, bukan melihat dan mempersaksikan sejak permulaan kejadian. Ketika manusia melihat susunan semesta yang menakjubkan, sudah barang tentu ia akan mempertanyakan, “Dari manakah alam ini berasal?” Sebab secara tabiat, diri manusia telah diinstall sebuah piranti lunak berupa “rasa ingin tahu” (kuriositas), lebih-lebih terhadap hal yang luar biasa semisal alam semesta ini! Lalu, kenapa orang-orang kafir itu tidak merenung sama sekali?
Dari segi bahasa, kata ru`yah di dalam al-Quran memang digunakan dengan makna yang tidak tunggal, semisal di surah al-Fil: 1
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِۗ
“Tidakkah engkau (Muhammad) melihat (tara) bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?”
Mungkinkah nabi Muhammad Saw bisa menyaksikan peristiwa itu? Sementara Nabi baru lahir pada tahun tersebut? Tentu tidak. Dengan demikian makna ru`yah di sini bukanlah “penglihatan indera”, melainkan “pengetahuan/ renungan”.
Namun demikian, Anda tetap bisa melempar pertanyaan, “Bukankah penglihatan indera lebih kuat dan nyata? Kenapa al-Quran tidak menggunakan kata ru`yah dengan makna inderawi saja?”
Sebenarnya, kata Imam asy-Sya’rawi, dalam ayat ini seakan Allah mengatakan kepada Nabi Saw, “Engkau (Muhammad) benar, engkau tidak melihat peristiwa pasukan bergajah dengan indera penglihatanmu. Tetapi Aku (Allah) telah mengabarkan hal tersebut kepadamu!” Dan kita tahu bahwa kabar dari Allah pasti lebih tepat ketimbang penglihatan indera kita. Sebab, penglihatan kita kadang masih menipu pemiliknya, sementara berita dari Allah pasti tak ada tipuan di dalamnya.
Jadi, penggunaan kata ru`yah dalam redaksi a wa lam yarallażīna kafarū jelas merupakan kritik keras terhadap mereka yang menyaksikan alam semesta sembari mengabaikan sama sekali tentang pelajaran di dalamnya. Karena hal itu seakan mendustakan kabar yang pasti benar dari Allah Swt.
Tentang keagungan renungan dan tafakur, Imam ar-Razi menceritakan tentang sebuah riwayat, manakala ada seorang pemuda yang merebahkan diri untuk beristirahat, lalu ia mengangkat kepala untuk melihat bintang dan benda-benda langit yang lain. Seketika ia berkata, “Aku bersaksi, bahwa semua benda langit ini pasti memiliki Tuhan dan Pencipta, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku.” Lalu Allah memandangnya dengan pandangan kasih sayang dan mengampuninya. Kemudian, Nabi Saw mengomentari peristiwa ini dan bersabda,
لا عبادة كالتفكر
“Tiada ibadah yang melibihi tafakur!”
Karena, lanjut Imam ar-Razi, berpikir dapat menghilangkan sifat lalai dan menumbuhkan rasa khasy-yah dalam hati, sebagaimana air menyuburkan tanaman.
Ketiga: Redaksi annas-samāwāti wal-arḍa kānatā ratqan fa fataqnāhumā (… bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya). Dalam al-Mufradātnya, Imam ar-Raghib menjelaskan bahwa ratq berarti “berkumpul, menyatu” sementara antonimnya ialah fatq yang bermakna “berpisah”.
Imam ar-Razi menyertakan beberapa pendapat para ulama tentang ayat ini, antara lain: (a) Ibn Abbas Ra, ratqan sebagai sesuatu yang menyatu, lalu Allah memisahkan keduanya dengan mengangkat langit dan memposisikan bumi sebagaimana saat ini. Pendapat ini, dalam hemat Imam ar-Razi, menegaskan bahwa penciptaan bumi lebih dahulu daripada langit. Bumi dibiarkan sebagaimana adanya dan langit di angkat, bersama dengan seluruh lapisannya, sehingga berada di atas. (b) Pendapat Imam Abi Shalih dan Imam Mujahid, bahwa ayat ini memiliki makna seluruh lapisan langit mulanya sesuatu yang padu dan tunggal, lalu Allah menjadikannya tujuh lapis; pun demikian dengan bumi. (c) Pendapat Ibn Abbas Ra, Imam Hasan dan mayoritas ahli tafsir bahwa langit dan bumi mulanya adalah sesuatu yang rapat dan padat, Allah memisahkan (meretakkan) langit dengan hujan; dan bumi dengan ditumbuhi tanaman dan aneka pepohonan. Hal itu senada dengan ayat berikut,
وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الرَّجْعِۙ. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِۙ
“Demi langit yang mengandung hujan; dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,” (QS. Ath-Thariq: 11-12)
Pandangan ini diperkuat dengan penggalan ayat selanjutnya wa ja’alnā minal-mā`i kulla syai`in ḥayy (…dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air;). Kata al-mā`i (air) pasti memiliki hubungan dengan penggalan ayat sebelumnya, di langit ia menjadi hujan, sementara di bumi dalam bentuk sumber kehidupan bagi tanaman dan mahluk hidup lainnya. (d) Pandangan Abu Muslim al-Isfahani yang menakwil kata fatq (terpisah) sebagai “penciptaan” dan “kejadian semesta”. Dengan takwil demikian, adalah baik menjadikan kata ratq (bersatu) sebagai metafor dari “ketiadaan alam”. (e) Pendapat yang mengatakan bahwa ratq adalah “malam” dan fatq sebagai “siang”, sebagaimana firman Allah,
وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖنَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَۙ
“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari (malam) itu, maka seketika itu mereka (berada dalam) kegelapan”. (QS. Yasin: 37)
Jadi, alam semesta pada mulanya diselimuti gulita, lalu Allah ‘pisahkan’ dengan menampakkan siang yang benderang.
Namun demikian, takkala Imam ar-Razi ditanya perihal pendapat yang lebih relavan dan berkelindan di antara teks tersebut, beliau menjawab, “Yang jelas, langit dan bumi yang kita pahami mulanya berpadu, berarti keduanya sama-sama telah ada, lalu keduanya terpisah. Dengan demikian, pendapat keempat dan kelima adalah yang paling lemah. Sementara pendapat pertama merupakan yang lebih kuat, disusul kemudian dengan pendapat kedua yang menjadikan langit sebagai rangkaian tujuh lapis, demikian pula dengan bumi. Lalu pendapat ketiga yang menganggap langit dan bumi, pada mulanya, adalah benda padat tanpa celah sedikit pun, lalu keduanya terpisah, langit menurunkan hujan dan bumi ditumbuhi tetanaman yang beragam.”
Sebagian ahli tafsir menyebutkan—dan sebagaian yang juga menyetujui pendapat ini—bahwa yang dimaksud dengan ratq sebagai kondisi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, takkala ia dalam status tidak-ada. Dan kata fatq untuk menunjukkan bahwa sebagian telah terpisah dengan bagian yang lainnya, manakala keduanya ada dan tercipta. Ini merupakan cara baca untuk menjelaskan tentang kebaruan alam semesta, yang “ada” setelah sebelumnya “tiada”. Dan niscara segala sesuatu yang baru, membutuhkan Pencipta. Demikian, kutipan dari Syaikh Thabathaba`i.
Tambahan (lagi) dari Syaikh Thabathaba`i, ayat ini bukan sekedar ajakan menuju tauhid, namun juga membantah asumsi tetang tuhan-tuhan lain yang ikut serta dalam menata dan mengatur jagad raya ini. Dan sudah barang tentu bahwa Dzat yang menciptakan alam juga mengaturnya, baik seluruh lapisan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.
Keempat: Ayat-ayat yang menceritakan perihal penciptaan, keteratuan dan muasal alam semesta, yang dikenal sebagai al-ayat al-kauniyyah, memang cukup melimpah ruah tersaji dalam al-Quran. Para ulama dan ilmuan saat ini tentu menerima bahkan tak sedikit dari para peniliti di luar Islam yang mengakui kebenaran al-Quran. Ini tak lain karena kebenaran al-Quran memang menjangkau seluruh masa dan putaran waktu.
Hal ini juga terbukti, manakala al-Quran turun di suatu masyarakat yang belum mengenal banyak tentang hal-hal ilmiah—penemuan mutakhir dan teori semisal gravitasi, relativitas umum, relativitas khusus dan sejenisnya—al-Quran tetap diterima sebagai kitab yang berisi kurikulum kehidupan (manhāj al-hayāh). Al-Quran bukan kitab sastra, teori ilmiah, hukum atau disiplin ilmu lainnya, namun ia mencakup seluruh bentuk narasi ilmiah. Jadi ia merupakan kitab inspirasi, bukan kitab dengan fokus pada keilmuan tertentu. Jika kita buat permisalan, ia ibarat sumber mata air. Semua orang bisa mengambil air darinya. Dari air itu kemudian dibuat aneka minuman, makanan, bahkan untuk membersihkan diri dari lumut-lumut lesu akibat polusi kehidupan. Air yang manusia bawa, tentu bukanlah sumber mata air itu sendiri, sekalipun semua air berasal darinya. Begitulah narasi sederhana tentang hubungan al-Quran dan disiplin pengetahuan yang ada.
Bila ada orang yang menyoal, “Kenapa al-Quran tidak menjelaskan penciptaan alam dengan detail? Bukankah ia kitab kebenaran, yang tak memiliki keraguan di dalamnya?” Dalam menjawab hal semacam ini, mari kita renungi, seandainya al-Quran menerangkan bahwa bumi ini bulat, ada gaya gravitasi di dalamnya, bahwa planet ini hanya sekian dari jutaan planet lain di ruang angkasa, mungkinkah ajaran ini akan diterima oleh manusia empat belas abad silam? Pasti sulit menerima kebenaran seperti itu. Orang-orang Arab terdahulu pasti menganggap al-Quran sebagai mitos dan penuh unsur tipu-tipu. Bila memang gagal diterima di masa Nabi Saw, bagaimana mungkin ia bisa sampai di tengah-tengah kita saat ini?! Demikianlah mukjizat al-Quran, ia adalah burhān, kebenaran yang dapat bertahan di seluruh zaman.
Tentang hubungan al-Quran dan pengetahuan sains, Imam asy-Sya’rawi berpendapat bahwa al-Quran hanya membahas sekilas, memberi simbol dan isyarat sederhana, agar bisa dijumpai kebenarannya dengan optimalisasi akal dan pengetahuan manusia. Dengan cara itu, akan muncul kebenaran satu persatu, lalu temuan dan teori sains baru yang menunjukkan betapa benar apa yang termaktub dalam al-Quran.
Para ulama, sekalipun berangkat pada titik tolak yang sama: menyakini dan mencintai al-Quran, tetapi berada pada dua kutub berbeda dalam konteks hubungan al-Quran dengan sains: (a) Ada yang begitu gemar dengan penemuan ilmiah dan mengatakan bahwa apa yang disingkap oleh para ilmuan sudah tersebut di dalam al-Quran. (b) Ulama yang lebih memilih berpegang pada teks al-Quran, tanpa membincang teori ilmiah tertentu untuk mengurai penjelasan dari ayat al-Quran. Hal ini mereka lakukan karena rasa khawatir bahwa suatu teori ilmiah bisa keliru di masa yang akan datang, lalu al-Quran menjadi korban tabrak lari dari kesalahan teori ilmiah tersebut.
Posisi yang tepat, bagi Imam asy-Sya’rawi, adalah membedakan mula-mula tentang “teori ilmiah” dan “kebenaran ilmiah”. Teori ilmiah adalah hipotesis yang mengandung kemungkinan benar dan (atau) salah; ia belum mendapati kebenaran final saat diuji sekarang—lebih-lebih di masa depan dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Sementara kebenaran ilmiah, adalah temuan yang tak lagi bisa disangkal kebenarannya. Ia kebenaran kokoh yang sudah terbukti. Dengan demikian, tentu tak ada persoalan menghubungkannya dengan al-Quran.
Imam asy-Sya’rawi lalu mencontohkan tentang temuan ilmiah yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Orang-orang yang menolak dengan dalil dari teks sakral keagamaan akan terperangah manakala kebenaran ilmiah menyatakan bahwa mereka salah. Lebih-lebih ketika ditemukan alat untuk melihat berbagai benda langit, semisal matahari, bulan dan beberapa planet berbentuk bulat, kenapa bumi mustahil pula berbentuk demikian?
Di sisi lain, beliau juga memberi peringatan, utamanya terhadap orang yang segera mencocokkan suatu temuan dengan ayat di dalam al-Quran. Semisal, ketika dunia sains menemukan tujuh planet yang mengitari matahari: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus dan Uranus; lalu ditafsirkan bahwa tujuh langit (as-samawat as-sab’) yang dimaksud dalam al-Quran adalah tujuh planet itu. Sementara kita ketahui saat ini planet yang mengitari matahari ternyata lebih dari itu, lantas apakah jika demikian al-Quran menjadi keliru? Tentu tidak. Karena antara al-Quran tidak sama dengan tafsir tentangnya. Hal ini merupakan kesalahan yang terjadi manakala kita terburu-buru menyimpulkan tentang temuan sains, padahal ia semata teori yang masih diperselisihkan kebenarannya (teori ilmiah), belum dibuktikan dan berstatus kebenaran ilmiah.
Kelima: Dalam penggalan ayat wa ja’alnā minal-mā`i kulla syai`in ḥayy, a fa lā yu`minụn (… dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?) dapat mengundang tanya, “Bagaimana jika dihubungkan dengan ayat lain yang menyiratkan bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas (lihat QS. Al-Hijr: 28), dalam hadits disebutkan malaikat dicipta dari cahaya, dan nabi Adam As dibuat dari tanah (lihat QS. Ali Imran: 59)? Bukankah tidak setiap yang hidup berasal dari air?” Imam ar-Razi mengomentari pertanyaan ini dengan jawaban bahwa sebuah kata (al-lafz) yang bersifat umum, tentu ada indikator (qarinah) khusus yang berlaku di dalamnya. Di sisi lain, sebuah argumen harus dibangun berdasarkan hal konkret yang bisa dipersaksikan secara umum agar ia tak luput dari tujuan. Karenanya, sudah tentu dalam ayat ini ada pengecualian tentang penciptaan malaikat, jin, nabi Adam As dan nabi Isa As, karena orang-orang kafir tidak melihat persitiwa tersebut sama sekali.
Para ahli tafsir, lanjut Imam ar-Razi, memang berbeda pendapat soal kulla syai`in ḥayy, (…segala sesuatu yang hidup…), sebagian menganggapnya dari genus hewan saja; sebagian yang lain memasukkan tumbuhan dan pepohonan dalam kategori ini juga, dengan alasan kebutuhan tanaman dan pepohonan kepada air yang menjadikannya tumbuh, tetap basah, menjadi hijau, merubah kuncup menjadi mekar dan berbuah. Pendapat ini tentu relevan dengan ayat yang sedang kita bahas. Bilamana ada yang menolak menyebut tumbuhan sebagai sesuatu yang hidup, kita bisa membantah dengan ayat al-Quran yang menyatakan bahwa bumi pun dibolehkan mendapat status “hidup”, semisal pada ayat ini,
مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا
“…Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan (air) itu dihidupkannya bumi yang sudah mati?…” (QS. Al-Ankabut: 63)
Imam al-Qusyairi memberi corak lain, beliau berpendapat bahwa segala sesuatu diciptakan dengan air, karena asal kejadian dari hewan dan perkembangbiakannya dengan gen tertetu, yaitu sperma, yang ia adalah bagian dari genus air. Sains modern, Syaikh Thabathaba`i menimpali, juga telah membuktikan tentang hubungan sifnifikan antara kehidupan dengan air.
Dalam analisis bahasa, Imam asy-Sya’rawi menambahkan, wa ja’alnā minal-mā`i kulla syai`in ḥayy, (…dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air;) untuk menunjukkan bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan manusiawi (al-hayāh al-insāniyyah) semata, atau kehidupan yang memiliki unsur lembab, lembut, basah juga masuk dalam kategori ini. Hewan dan tumbuhan, atau jenus yang lebih rendah dari keduanya, juga hidup bergantung pada air, jika tiada air, maka mati dan musnahlah kehidupan mereka. Dengan pembacaan seperti ini, ayat ini tidak bermakna bahwa air (secara dzātiyah) merupakan substansi segala yang ada—tetapi unsur air (sifat-sifat lembut, lembab ataupun basah)lah yang ada dalam tiap jenis kehidupan.
Selanjutnya, pembuktian ilmiah juga menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki jenis kehidupan yang sesuai dengannya, dan di dalamnya terdapat unsur ‘air’ sebagai sumber. Mari renungi ayat berikut,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ…
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu…” (QS. Al-Anfal: 24)
Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi panggilan Allah dan rasulNya, agar mendapatkan “kehidupan”; padahal mereka adalah orang yang masih hidup. Jadi apakah makna kehidupan yang dijanjikan Allah? Hidup yang dijanjikan ini adalah kehidupan akhirat dengan kualitas yang lebih bernilai. Karena hidup saat ini memiliki batas, sementara orang beriman yang memenuhi seruanNya akan mendapat hidup abadi, yaitu kehidupan akhirat nanti.
Terkadang, kata “rụh” juga dibuat sebagai istilah untuk satu unsur yang masuk dalam materi dan menyebabkan materi itu dapat hidup, sebagai tersebut dalam al-Hijr: 29,
فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ…
“Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya, dan Aku telah meniupkan ruh (ciptaan)-Ku ke dalamnya…”
Karenanya, al-Quran yang diturunkan dari langit untuk memberi hidayah kepada penduduk bumi disebut “rụh”, malaikat pembawa wahyu juga disebut sebagai “rụh”; karena ia memberi kehidupan abadi, yang tak akan sirna sama sekali. Demikian ulasan tentang hubungan antara air dan kehidupan.
Ketujuh: Pembacaan dengan tafsir Isyāri, sebagaimana tersebut dalam al-Bahr al-Madīd, juga cukup unik, bagi Syaikh Ibn ‘Ajibah, ayat ini memberi isyarat, “Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikaan bahwa ruh (langit) dan nafsu (bumi) mulanya adalah sesuatu yang menyatu lagi keras, ia mati karena kebodohan yang diidapnya, lalu Kami pisahkan keduanya dengan anugerah pengetahuan dan rahasia ketauhidan?” Maknanya adalah sebagian ruh dan nafsu pada mulanya mati, sampai keduanya berteman (berguru) dengan para pendidik spiritual (ahl at-tarbiyyah), sehingga keduanya dianugerahi pengetahuan dan keimanan. “Lalu Kami jadikan dari air gaib—(mā`al-ghaib) yang diperoleh dari percikan keazalian—segalanya hidup. Apakah mereka masih tidak percaya tentang air ini di sisi para pendidik spirual tersebut?” Imam al-Qusyairi menambahkan, bila kehidupan jiwa diperoleh dari air langit takkala dikonsumsi tubuh, maka kehidupan hati disebabkan oleh air rahmat, kehidupan hati nurani (asrār) dari air takzim (pengagungan).
Delapan: Hubungan antara redaksi a wa lam yarallażīna kafarū (Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui…) dengan penutup ayat a fa lā yu`minụn (…maka mengapa mereka tidak beriman?) merupakan penguat antara pengetahuan dengan keimanan. Seakan Allah berkata, “Jika kalian tahu, kalian akan beriman. Bilamana pengetahuan kalian tiada, maka sulitlah keimanan itu diperoleh.” Hubungan seperti ini bisa kita jumpai dalam ayat yang lain, misalnya,
…يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ…
“…Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)
Karena Allah memuliakan iman dan ilmu, demikian juga seluruh sarana yang mengantarkan kita pada dua kemulian tersebut, tak terkecuali melakukan permenungan, misalnya. Wallahu a’lam.
Al-Anbiya: 31
وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْۖ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ
“Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia (tidak) guncang bersama mereka, dan Kami jadikan (pula) di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.”
Ayat ini mencakup beberapa penjelasan dari para ahli tafsir, antara lain:
Pertama: Dalam redaksi wa ja’alnā fil-arḍi rawāsiya an tamīda bihim (Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia [tidak] guncang bersama mereka) Imam ar-Razi mengutip pendapat yang menyatakan bahwa kata rawāsiya berarti “gunung”, ia termasuk bagian dari bumi. Ibn Abbas Ra mengatakan bahwa bumi dikelilingi air, ia terombang-ambing bersama seluruh yang ada di dalamnya, sebagaimana perahu di tengah samudera. Lalu Allah mengokohkannya dengan gunung—agar bumi tidak goncang sehingga layak ditempati oleh mahluk di dalamnya.
Imam asy-Sya’rawi mengulasnya lebih terperinci, selain dihubungkan dengan ayat yang lain, beliau juga menguatkannya dengan temuan sains modern. Kata rawāsiya adalah bentuk plural dari kata rās yang berarti kokoh (tsābit), selain itu al-Quran menyebut gunung dengan autād (pasak), sebagai gambaran fungsi gunung sebagai pasak yang menyangga keseimbangan bumi, seperti dalam ayat berikut:
وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًاۖ
“dan gunung-gunung sebagai pasak” (QS. An-Naba`: 7)
Lalu Allah menyebutkan alasan penciptaan gunung dengan firmannya an tamīda bihim (agar ia [tidak] guncang bersama mereka). Maksudnya adalah gunung itu berfungsi menguatkan bumi agar tidak bergerak tanpa keseimbangan. Jika memang bumi telah diciptakan dengan dengan kokoh (seimbang), tentu tidak diperlukan gunung untuk mengokohkannya. Firman Allah tentang gunung di ayat yang berbeda,
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِۗ
“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan…” (QS. An-Naml: 88)
Zaman sekarang tentu tak asing dengan ayat ini, karena sains telah membuktikan bahwa gunung juga bergerak, sekalipun dari sudut pandang kita ia tetap dan tak beranjak barang seinci pun dari tempatnya. Lantas, dari mana kita bisa meyakini gerakannya? Analogi yang diberikan al-Quran adalah “…padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan…” Gerak awan tidak diperoleh dari dirinya, melainkan hembusan angin yang menerpa dan membawanya pada tempat tertentu, begitu pula dengan gunung yang bergerak sesuai dan bersamaan dengan rotasi bumi. Kita sulit merasakan gerakan tersebut, karena kita berada di bumi, sehingga kita tidak merasakan gerakan bumi dan gunung. Mari kita buat permisalan agar lebih mudah dipahami, seandainya kita berada di atas kapal pesiar yang sangat besar, lalu kita duduk di atas kursi, dengan meja dan seluruh hidangan di atasnya. Sepintas lalu kita tidak akan menganggap bahwa kursi, meja dan apapun di atasnya bergerak, padahal sebenarnya ia bergerak seirama dengan gerakan kapal menuju arah tertentu.
Kedua: Makna dari penggalan ayat wa ja’alnā fīhā fijājan subulal la’allahum yahtadụn (dan Kami jadikan di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk), Imam az-Zamakhsyari berkomentar bahwa makna al-fāj (bentuk tunggal dari al-fijāj) adalah “jalan yang luas” (ath-thāriq al-wāsi’). Sementara dalam Ma’ālim at-Tanzīl, dijelaskan bahwa al-fāj bermakna “jalan luas yang terhampar di antara dua gunung”. Di dalam al-Quran terdapat frasa yang mirip, yaitu pada surat Nuh: 20,
لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
“Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.”
Apa perbedaan sederhana antara frasa fijājan subulan dengan subulan fijājan? Imam az-Zamakhsyari memberi uraian singkat, yang pertama untuk menunjukkan ada jalan luas di sana. Sementara pada frasa kedua, untuk mengabarkan ketika awal diciptakan, jalan yang luas telah ada di sana.
Dalam tafsir al-Mizān, disimpulkan bahwa Allah menciptakan gunung agar gerak bumi seimbang, lalu diciptakan jalan luas pada gunung tersebut agar manusia mendapat petunjuk manakala hendak pergi ke suatu tempat.
Sementara dalam Khawāthir-nya, Imam asy-Sya’rawi melengkapi dengan penjelasan bahwa kata ganti fīhā bisa diperuntukkan bumi maupun gunung, karena di sana sama-sama ditemukan “jalan luas” untuk manusia melakukan perjalanan, sekalipun di gunung lebih banyak jalan mendaki dan menurun.
Demikian pula dengan redaksi la’allahum yahtadụn (…agar mereka mendapat petunjuk), bisa memiliki dua makna: (a) Petunjuk terhadap eksistensi Sang Pencipta; atau (b) Petunjuk menuju tempat yang dituju oleh manusia. Kedua makna ini tidak bertentang dan dapat digunakan pada tafsir (penjelasan) ayat ini.
Ketiga: Dalam narasi khas tafsir Isyāri, Syaikh Ibn ‘Ajibah menerjemahkan begini, “Kami jadikan bagi bumi nafsu itu gunung akal untuk menguatkan dan menyeimbangkannya agar tak terjerat oleh hawa jahat yang membuatnya celaka. Dan Kami jadikan di dalamnya berbagai jalan untuk ditempuh agar sampai kepada ke hadirat Kami. Jalan tersebut berupa metode riyādhah (olah-jiwa) dan berbagai bentuk mujāhadah (kesungguhan batin); sekalipun jalannya beragam tapi memiliki satu tujuan. Agar mereka terbimbing dan mendapat arahan untuk sampat ke hadirat Kami.”
Syaikh Najmuddin al-Kubra memaknai lebih unik, bahwa wa ja’alnā fil-arḍi rawāsiya an tamīda bihim adalah isyarat untuk wali abdal, karena mereka merupakan pasak bumi (autād al-ardh), seluruh penduduk bumi memperoleh anugerah melalui keberkahan mereka. Wa ja’alnā fīhā fijājan subulal la’allahum yahtadụn bermakna bahwa para wali itu menuntun manusia, melalui petuah-petuah mereka, pada jalan menuju Allah. Imam al-Qusyairi juga berkomentar, sebagaimana bumi memiliki jalan untuk ditempuh menuju suatu tempat yang diinginkan, begitu juga Allah menjadikan berbagai macam jalan untuk sampai kepadaNya, melalui lisan para pendidik spiritual agar menjadi petunjuk bagi sang murid, teladan pagi penempuh spiritual dan panutan yang mempermudah mereka sampai kepada Allah.
Allāhumma ihdinaṣh–ṣhirāṭhal-mustaqīm. Amiin. [HW]