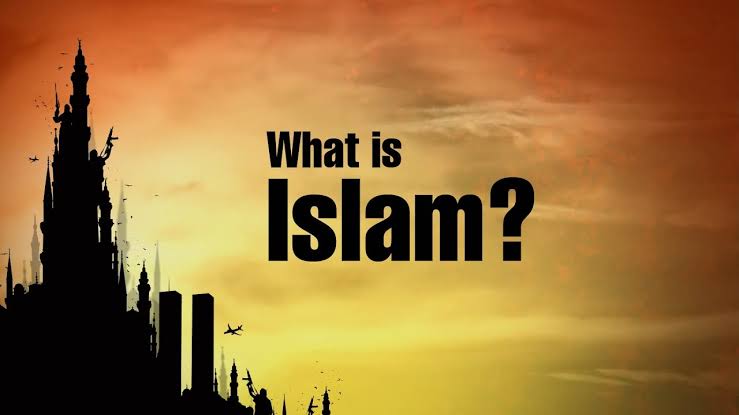Siapa yang layak berbicara islam? Pertanyaan demikian rasa-rasanya amat dan sama seekali relevan untuk ditanyakan kepada diri kita dan kondisi lingkungan sosial kita saat ini. Pasalnya sederhana saja, Islam sebagai agama yang menjadi pegangan mayoritas umat beragama di Indonesia memiliki fase tantangan baru, tentu saja tantangan ini tidak datang dari ruang hampa atau tiba-tiba.
Tak perlu kiranya kita beranjak jauh untuk mengurai sejarah hanya demi membicarakan soal ini, cukup sedikit membuka ingatan masa lalau dimana kita perlu menanyakan mengapa dulu tidak semua orang mampu dan berani berbicara islam? Sedangkan saat ini amat marak bahkan hampir semua berbicara islam? Dari ulama, akademisi, ustadz hijrah, brother atau sister fillah, dan kadang-kadang mereka yang hanya belajar islam lewat media pun turut begitu vokal dalam membicarakan Islam. Lalu lantas layakkah manusia-manusia di atas tadi untuk berbicara Islam?
Islam saat ini laksana pakaian seksi yang diperebutkan semua orang, baik para politisi, artis, kaum hijrah dan siapapun saja yang mempunyai visi misi tertentu tak terkecuali produk-produk layanan masyarakat dari mulai pakaian, makanan, make up dan lain sebagainya. Didukung semakin menggilanya media, semua yang berbicara islam dalam bahasa jawa orak tedeng aling-aling atau terjemah bebasnya tidak menggunakan batas.
Tentu bila kita membandingkan dengan dahulu akan terasa sangat berbeda, mari kita buka ingatan kita sejenak dengan masuk kedalam peristiwa hidupnya ulama besar bernama Imam Malik yang memiliki kitab fenomenal Al-Muwatha. Dulu Imam Malik pernah ditanya tentang perihal dan Imam Malik dengan segenap kerendahan hatinya mengatakan saya kurang tahu.
Hal tersebut amat berbanding terbalik bila kita saksikan saat ini, diamana para dai dan ustadz yang kredibilitasnya masih samar mampu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan, baik itu dalam bidang akidah, fiqh, sosial masyarakat dan lain sebagainya.
Apalagi yang lebih parah adalah mereka yang turut berbicara islam acapkali tak memiliki standarisasi kemampuan yang jelas. Academic standing mereka pun kadang kali memunculkan pertanyaan, dan expertise mereka selalu menimbulkan pertanyaan yang juga besar di kalangan ahli untuk sekedar menanyakan apa latar belakangnya sehingga begitu berani bertutur islam dengan amat entengnya.
Imam Al-Ghazali mengatkan yang terilhami dari kalimat yang diucapkan oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi, bahwa ada enpat tipikal manusia yang memiliki pengetahuan dan caranya menyikapi pengetahuan tersebut.
Pertama adalah Yadri Wa Annahu Yadri. Ialah manusia yang tahu dirinya tahu, dialah manusia yang berpengetahuan dan menyadari serta mendialektikakan ilmu pengetahuannya sebagai mana mestinya.
Kedua, adalah Yadri Wa Laa Yadri Annahu Yadri. Manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, adalah manusia yang sejatinya dirinya berpengetahuan namun dirinya tidak menyadari, barangkali karena lemah nya kepekaannya terhadap kondisi sekita atau matinya indera kritisnya untuk menangkap hal-hal yang terjadi.
Ketiga adalah Laa Yadri Wa Annahu Laa Yadri. Manusia yang tahu bahwa dirinya tak tahu, adalah manusia yang menyadari tentang keterbatasannya tentang pengetahuan seghingga dirinya termotivasi untuk diam dalam apa yang tidak diketahuinya dan terdorong untuk terus belajar.
Dan yang terakhir adalah La Yadri Wa Laa Yadri Annahu La Yadri. Manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, adalah manusia yang sok pintar dan begitu menggema memamerkan kebodohan, dan yang sangat melucukan kadang kali kebodohan itu dibungkus dengan label agama sehingga seolah dirinya orang yang layak berbicara agama. Menyedihkan memang
Walahu A’lam Bishawab