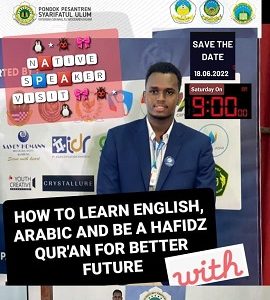Bukan tanpa alasan kala itu para ulama menolak penggunaan mesin cetak, terutama dalam tradisi Al-Qur’an. Di awal penggunaannya, produk Al-Qur’an mesin cetak memang memiliki banyak kesalahan. Isu adanya campuran bahan-bahan najis semakin mempertegas penolakan. Belum lagi eksistensi pemain cetak awal yang notabene ‘kaum kafir’. Masalah kecil namun syarat nuansa Islam, seperti adab, jelas jauh dari kata perhatian. Namun demikian, tahukah jika Imam ‘Ashim dan Hafsh ternyata menjadi ‘raja’ teknologi cetak modern?
Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Imam ‘Ashim yang wafat pada tahun 128 H. atau sekitar 744 M. dan Imam Hafsh yang wafat pada 180 H. atau 796 M., merajai tekonologi modern yang baru ditemukan paling tidak, enam setengah abad berikutnya oleh Johannes Gutenberg, tahun 1428 M?. Jawabannya, ada di tangan anda.
Hampir dapat dipastikan mushaf yang ada di tangan anda saat ini merupakan versi bacaan Imam ‘Ashim dari jalur riwayat Hafsh. Versi ini bahkan digunakan mayoritas muslim di seluruh dunia dengan prosentase 95% dari seluruh populasi mushaf yang ada. Disusul riwayat Warsy dari bacaan Nafi‘ sebanyak 3%, kemudian bacaan Ibn ‘Amir sebanyak 1%, riwayat Qalun dari Nafi‘ sebanyak 0,7% dan riwayat Al-Duri dari Abu ‘Amr dengan 0,3%.
Dominasi bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh ini lah yang saya maksudkan ketika keduanya disebut ‘raja’ teknologi cetak modern. Bagaimana tidak, berkat teknologi anyar ini lah bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh menghegemoni mushaf di seluruh dunia.
Semuanya bermula ketika Abraham Hinckelmann (1652-1692) menerbitkan mushaf dari manuskrip-manuskrip yang ia kumpulkan. Mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Hamburg ini, setelah melalui kajian perbandingan, menunjukkan bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh sebagai versi utama. Besar kemungkinan, hal ini disebabkan manuskrip-manuskrip acuannya telah lebih dahulu menggunakan versi ini.
Pilihan ini cukup memberi keuntungan terhadap bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh, mengingat mushaf Hamburg masuk dalam kategori pionir pencetakan teks Al-Qur’an. Sehingga penelitian generasi berikutnya selalu dilakukan dengan menginduk pada mushaf edisi ini. Dari sini, hegemoni ‘Ashim riwayat Hafsh tanpa disadari telah terbentuk dengan sendirinya.
Mungkin ini pula yang menjelaskan mengapa mushaf edisi Mesir awal mengacu bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh. Melalui percetakan Al-Bahiyyah pada tahun 1890 M., pemerintah Mesir juga melakukan pencetakan mushaf Al-Qur’an. Tak tanggung-tanggung, pencetakan ini bahkan melalui penelitian khusus. Sayang, karena kualitas cetakan yang kurang maksimal, mushaf edisi ini kurang diminati publik sehingga tidak tersebar secara massif.
Hampir empat puluh tahun berselang, Mesir kembali melakukan pencetakan Al-Qur’an. Kali ini bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh menuai sukses besar. Tepat pada tahun 1924/1925 M., sejumlah ulama, ahli Al-Qur’an dan pakar bahasa dikumpulkan guna melakukan kajian mendalam. Perbaikan dan terobosan dilakukan. Hasilnya, sebuah mushaf dengan standar penyusunan yang tinggi berhasil disusun. Standar ini ditunjukkan dengan konsistensi penggunaan rasm utsmani, penanda ayat Madinah dan Mekkah, penanda di setiap juz dan petunjuk cara membaca. Kesuksesan ini juga tak lepas dari kualitas cetakan yang maksimal.
Puncak dominasi ‘Ashim riwayat Hafsh sendiri terjadi ketika pemerintah Saudi Arabia memilihnya sebagai acuan mushaf induk Madinah melalui Mujammma‘ Malik Fahd li Thiba‘ah al-Mushaf al-Syarif. Melanjutkan sukses edisi Mesir 1924, mushaf ini semakin menarik dengan kualitas khath yang marketable: ramping dan indah. Meski faktor keberhasilan sebenarnya lebih ditunjang upaya distribusi massalnya yang dilakukan secara cuma-cuma: sepuluh juta mushaf setiap tahunnya. [HW]