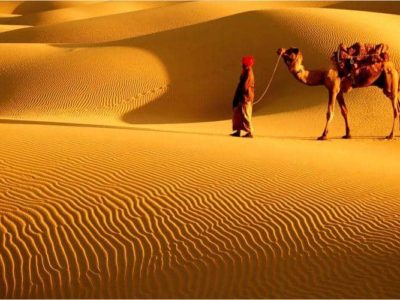Lazim kita tahu bahwa perubahan dan peradanan dunia dimulai dari teks, dari karya para leluhur, para ilmuwan. Tak tanggung-tanggung, Tuhan dan iman sekalipun hadir dan memperkenalkan diri kepada umat manusia sebagai teks, baik teks sebagai tulisan, maupun teks sebagai pengalaman spiritual. Apapun itu, perjumpaan dengan teks adalah perjumpaan yang merubah dunia dan pandangan jagad seseorang hingga sekian generasi.
Sehingga, mengabaikan teks berarti merencanakan kemunduran peradaban
Inilah setidaknya yang ditanamkan oleh Pesantren dan para Kiai. Ini pula yang lamat-lamat menjadi karakter para santri yang selama belajar di Pesantren berdialektika dengan teks dari berbagai peradaban melalui kitab kuning.
Salah satu kekhasan Islam Indonesia yang tidak ada di belahan dunia lain adalah kaum santri, kaum sarungan. Hal ini bukan semata karena tiap tahun lebih dari empat juta anak belajar di Pesantren dan lebih dari enam juta lainnya belajar di Madrasah Diniyah yang rerata menjadi bagian dari Pesantren, tetapi lantaran santri adalah identitas yang akan terus dibawa dan dibela sampai mati.
Santri, pada prinsipnya adalah para sarjana yang bukan hanya “non formal”, tetapi memang sengaja menolak formalitas dan apalagi formalisme menara gading. Meraka adalah kaum terpelajar yang sederhana dan bersahaja, rela membaur mengabdi tanpa embel-embel publisitas apapun di tengah masyarakat pedesaan dan pedalaman. Sebuah fakta mencengangkan mengingat para sarjana lulusan perguruan tinggi bonafid biasanya enggan pulang kampung dan membangun desa. Dalam filsafat Jawa disebutkan bahwa: urip kuwi urup, urip kuwi urap (hidup itu menyala dan bercahaya, hidup itu membaur dan bermasyarakat). Falsafah ini santri banget!
Sementara itu, seorang pakar gramatika asal Mesir, syaikh Syarafuddin Yahya al-‘Imrithi asy-Syafi’i (w. 989 H) menyatakan dalam salah satu karya monumentalnya bertajuk Ad-Durrotu al-Bahaiyyah atau yang lebih dikenal Nazham al-‘Imrithi, yakni ’idzil fata hasba’tiqadihi rufi’ # wa kullu ma lam ya’taqid lam yantafi’ (Idealnya pemuda harus memiliki keyakinan yang tinggi, sebab tanpa keyakinan, apapun tidak akan berguna). Kumpulan puisi Nahwu (gramatika) ini sangat karib di telinga para santri dan menjadi kurikulum wajib di Pesantren, bahkan sebelum tamat Sekolah Dasar, saya dan rerata kaum sarungan telah menghafal seluruh bait puisi (manzhumah) itu.
Ajaran Syaikh Imrithi ini telah mendarah daging di Pesantren, bahwa santri harus mantap hati, bulat tekad dan yakin seyakin-yakinnya kepada Ilmu dan barakahnya, kepada kitab kuning dan barakahnya, kepada guru dan barakahnya, kepada Pesantren dan barakahnya, kepada Nabi Muhammad Saw dan syafaatnya, bahkan kepada Tuhan dan ampunan serta cinta-kasihNya. Nah, di atas keyakinan itulah santri melangkah. Pun juga Kiai, ia sungguh-sungguh yakin bahwa perjuangan itu akan berbuah dan merambah, yakin bahwa kerajaannya di langit bukan di bumi. Lantas, bagaimana untuk sampai pada keyakinan sedemikian itu?
Sekali lagi, syaikh Imrithi memberi wejangan dalam kumpulan puisi yang sama, wan nahwu awla awwalan an yu’lama # idzil kalamu dunahu lan yufhama (Tata bahasa lebih utama untuk dipelajari, karena teks tidak akan dipahami tanpa itu) Agama adalah kalam (teks), masyarakat adalah teks, Negara adalah teks, pendidikan adalah teks, genarasi muda adalah teks, nasib adalah teks, hidup dan matipun adalah teks.
Pesantren merentangkan khazanah Islam dari awal datangnya hingga kini, juga lanskap peradaban dari sekian imperium, bahkan prisma-prisma pemikiran dari berbagai tafsir dan Kitab Suci. Sebuah warisan yang generasi milenial dan gerombolan cuti nalar sangka ada di Medsos. Padahal, dunia maya tak pernah memberikan geneologi (sanad) ilmu dan pembentukan moral secara utuh.
Nah, di zaman gila Medsos, mabuk agama dan kesurupan politik seperti sekarang ini, bahkan teks-teks anyir berlendir semacam hoaks dan ujaran kebencianpun bisa menggerakkan massa untuk memenangkan pemilu, Brazil adalah contoh baru-baru ini, serta berbagai perang saudara, juga penggulingan rezim di Timur Tengah dan kawasan Teluk satu dekade terakhir.
Apapun yang terjadi, perjuangan tertinggi manusia adalah memenangkan akal sehatnya dari kesia-siaan pola pikir yang kerdil dan pola sikap nan jumud. Dan, ini dimulai dari teks. Tidak perlu bakat untuk bekerja keras, sebab semua kemenangan berasal dari berani memulai. Ya, belajar sembari berjalan. Manakala Anda berhenti belajar, Anda berhenti memimpin, dan apabila Anda berhenti memimpin, Anda berhenti manjadi manusia. Agar tetap waras, membaca dan mendiskusikan teks (buku/kitab) harus dijadikan gaya hidup generasi milenial. Sesuatu yang telah sejak enam abad lalu hingga kini menjadi gaya hidup santri. Apa sebab?
Karena literasi bukan sekadar mambaca-menulis, ia juga upaya menganalisa bentuk teks, manafsir, merenangi lautan makna serta membangun pola pikir dan pola sikap, agar tetap seimbang di tengah laju peradaban. Sungai bermuara ke laut, sejarah mengalir ke langit. Jangan berhenti menulis, karena peradaban akar terhenti.