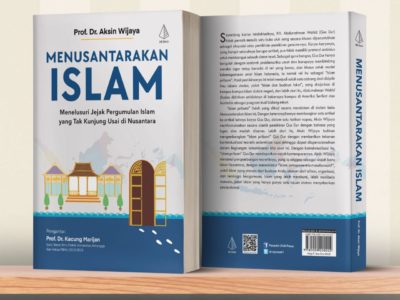Ada dua gejala minder dalam beragama. Dua pola ini berawal dari tengok-menengok agama lain. Pertama, melihat ajaran agama lain, membandingkannya dengan doktrin agama sendiri, lantas mencari titik kenyamanan. Jika agama lain memperbolehkan begini, seharusnya agamaku juga boleh begitu. Jika di agama lain, misalnya, tidak ada definisi soal aurat, maka sewajarnya jika agamaku tidak lagi memberi batasan soal hal beginian. Ini wilayah manusiawi, kok. Jika agama lain oke-oke saja makan ini itu yang enak, maka aneh jika santapan kayak begitu malah dilarang agamaku. Di setiap agama ada pemeluk model begini. Islam ada, Kristen juga, Katolik iya, Hindu pula, dan seterusnya. Jika mempertanyakan lantas mencari jawaban, sah-sah saja. Sebab, insting yang harus disyukuri oleh manusia adalah insting penasaran. Rasa ini yang melahirkan adanya ketertarikan, penemuan, dan konsep pemikiran yang tertata rapi, lantas terus berdialektika.
Keminderan seperti ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Pada akhirnya, gugatan ini akan melahirkan keraguan. Lantas berimbas pada perlawanan, laten maupun manifes, meminjam istilah Robert K. Merton. Karena berkaitan soal agama, yang berlandaskan keyakinan, maka gugatan-gugatan semacam ini alih-alih melahirkan pencerahan, justru malah memunculkan ambiguitas. Dalam perkembangannya, pola ini lebih sinkretik. Ajaran Lia Eden misalnya. Ada gado-gado ajaran berbagai agama yang didoktrinkan sedemikian rupa hingga membentuk “ajaran baru” yang diyakini pemeluknya. Soal keyakinan memang tidak bisa diadili, hanya dalam prosesnya terjadi “benturan-benturan” yang membuat keyakinan ini meredup, mengerdil, lantas hilang. Kalaupun masih tersisa, hanya ada artefak pemikiran yang merembes secara acak. Jika kita belajar historisitas agama, akan lebih memahami pola seperti ini.
Di wilayah Ushul Fiqh, ada yang disebut Syar’u Man Qablana, alias syariat Islam yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Baginda Rasulullah. Bagi saya teori ini menarik jika dipakai dalam kajian lintas iman. Juga telaah aspek sosiologis-antropologis atas doktrin agama-agama lain, khususnya yang disebut agama samawi. Tentu, tanpa harus terjebak pada “menyamakan semua agama”. Bagi saya, ada beberapa kesamaan dan perbedaan di setiap agama. Yang sama tidak perlu dibedakan, yang berbeda tidak perlu disamakan, meminjam istilah KH. Hasyim Muzadi. Bagi saya, semua agama hanya sama di dalam konstitusi kenegaraan Indonesia. Dalam arti dijamin kebebasan menjalankan keyakinan dan keberagamaannya.
Soal konteks bergaul dalam ruang beragama ini, saya terpesona oleh Gus Dur. Beliau intens menjalin komunikasi dan relasi dengan para pemuka agama lain, sembari menjadi bagian representasi agama mayoritas di Indonesia. Dia menginginkan Islam sebagai pengayom yang baik bagi agama lain di tanah air, walaupun, sebagaimana nasib para penggerak kerukunan, caci-maki datang dari saudara seimannya. Gus Dur lebih beruntung, karena beliau tidak mengalami nasib seperti Gandhi, yang dibunuh ekstremis Hindu, hanya gara-gara dianggap lebih peduli terhadap nasib kaum muslim di India menjelang Partisi. Baik Gus Dur maupun Gandhi tetap percaya diri dengan ajaran agamanya, tanpa harus bermain-main dengan pola sinkretisme, atau mencerca ajaran agamanya sembari bermanis muka dengan cara saru: menertawakan sakralitas agama di depan pemeluk agama lain. Tidak. Keduanya tidak setolol itu. Hidup tidak seanjing itu, kawan! Meminjam istilah arek-arek pergerakan!
Mereka berdua sudah terjun dalam ruang sosial, bergerak pada aras yang sama, sembari mencari titik temu dengan penganut agama lain. Keduanya membumi, tidak elitis.
Jika masih kesulitan menemukan orang yang percaya diri dengan ajaran agamanya dan kebangsaannya, kita pantas menoleh pada Haji Agus Salim. Muslim yang saleh, asketis, punya sikap perwira, tanpa mau mengendus-endus takzim di hadapan kaum berkulit langsat. Banyak sekali cerita soal keteladanan Haji Agus Salim dalam berislam dan bernegara dengan selera humor yang sangat jenaka. Dia punya marwah yang terjaga kuat. Dia adalah legenda. Terhormat di mata kawan, bermartabat di mata lawan. Ah, kok malah ingat legenda Barcelona, Carlos Puyol, ya. Brutal saat bermain, punya karakter yang kuat, dihormati kawan, disegani lawan.
Oke. Lanjut pada sikap minder yang kedua. Biasanya ini ada pada pemeluk agama yang bersemangat namun tidak dilandasi dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran agamanya. Sepotong-sepotong. Setiap agama punya model pemeluk kayak begini, walaupun hanya segelintir namun terasa menjengkelkan.
Di Islam, yang begini tidak banyak, tapi berisik. Biasanya berulah menggunakan teks agama dengan ceroboh. Misalnya, menjelang Idul Fitri, tersebar larangan memberi sangu kepada anak-anak kecil (padahal orang dewasa juga pengen. Khakhakhakh). Alasannya, budaya bagi-bagi sangu pada hari raya meniru budaya Tionghoa pada Imlek dengan memberi angpau. Olalaaaa. Padahal, setiap ajaran agama memberi semangat untuk berderma, bukan monopoli agama tertentu. Dan, keutamaan menjadi dermawan ini sudah menjadi bagian dari integral agama Islam.
Juga doktrin konyol bahwa Tahlilan, ziarah kubur, dan tumpengan njiplak tradisi Hindu. Pola indoktrinasi semacam ini perlu dicegah dengan cara memberi penguatan melalui jawaban yang rasional dan pas, agar sikap inferior ini bisa dihambat. Rasa minder yang menganggap apabila tidak ada ruang inovasi yang baik dalam ajaran Islam. Mencurigai kebaikan yang identik dengan agama lain, seolah-olah tidak ada motivasi berbuat baik dalam agamanya.
Wallahu A’lam Bishshawab. []