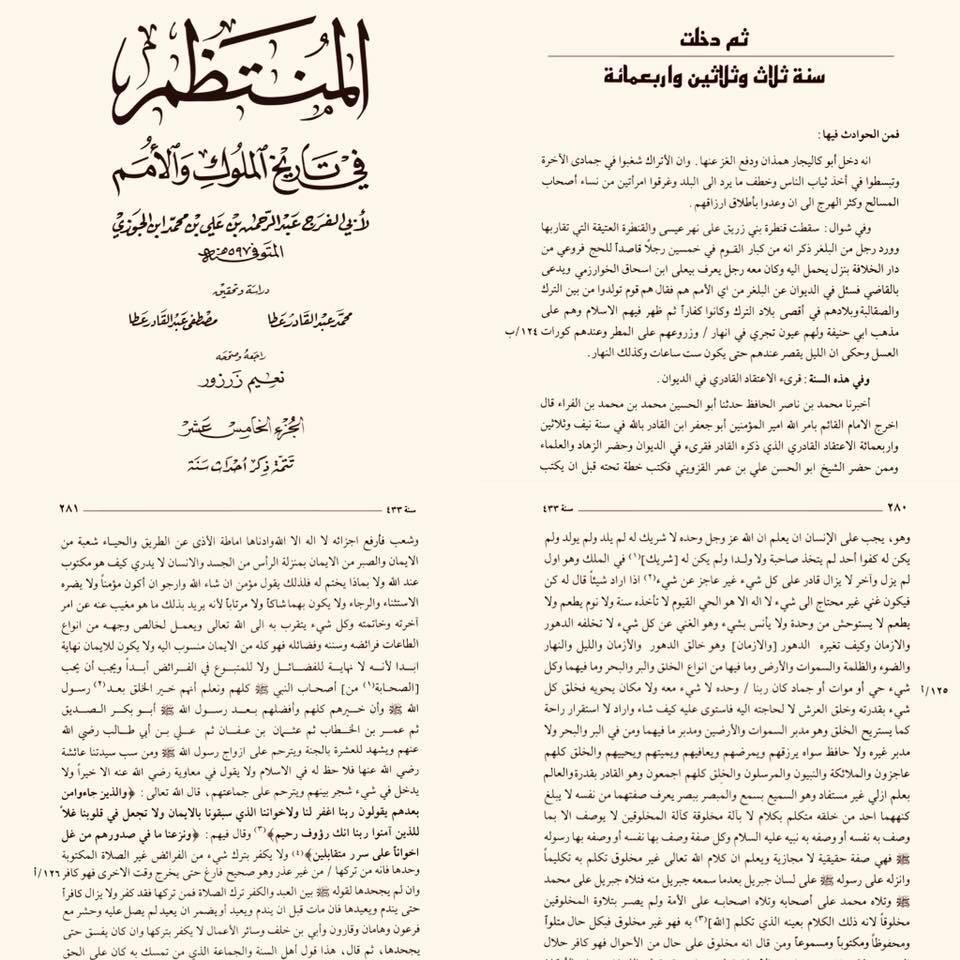Anak haram bukan dilahirkan atas keinginannya sendiri. Begitupun Bimbingan Belajar (Bimbel), bukan inti persoalan dalam pendidikan. Ia adalah bentuk-bentuk reaksi atas sistem pendidikan kita yang memisahkan antara proses belajar dan standar kelulusan.
Bimbel menjadi sukses karena berhasil mengantarkan peserta didik mereka untuk sampai pada standar kelulusan yang diciptakan oleh sistem pendidikan Nasional. Bimbel adalah produk komersial yang menawarkan jasa untuk menutupi lubang dalam sistem pendidikan nasional.
Jadi ketika banyak bimbel menjamur, bukan karena bimbel berhasil membelah diri, namun karena lubang yang menganga begitu besar dan terus membesar dalam sistem pendidikan kita dan asesmen yang dibentuk memang selalu menciptakan kesenjangan baru.
Masalah utamanya adalah cara sistem pendidikan menentukan kelulusan seseorang untuk mencapai nilai tertentu agar bisa masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau lembaga yang dimaksud.
Untuk bisa masuk ke sekolah Favorit, unggul (atau penggerak?), proses belajar di sekolah ternyata tidak bisa menunjang faktor pendorong kelulusan atau membuat seorang peserta didik lulus, atau diterima di sebuah lembaga yang dituju. Seorang anak sekolah SD, SMP dan SMA yang ingin menuju sekolah favorit mereka tidak hanya bisa mengandalkan proses belajar tempat mereka bersekolah.
Mengapa? karena asesmen sumatif (yang menentukan kelulusan) selalu berjarak dengan proses belajar itu sendiri. Soal yang dibuat bukan materi yang diajarkan di sekolah. Padahal secara umum, soal dalam sistem ujian kuantitatif seperti UN, UNBK, UTBK dan lainya berbasis pelajaran yang diajarkan di sekolah atau berkaitan dengan apa yang mereka pelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya.
Hal ini disebabkan soal yang dibuat tidak berdasarkan pengalaman riil siswa ketika belajar di sekolah. Pertanyaan dalam soal tes Universitas dan tes masuk sekolah tertentu, sebagian besar tidak pernah diberikan guru dalam proses belajar yang nyata.
Inilah akar persoalan yang membuat bimbel lebih efektif dalam meluluskan peserta didik pada lembaga atau jenjang pendidikan yang klien mereka tuju. Yaitu sistem tes yang menggunakan bentuk soal pilihan ganda (begitupun pilihan ganda kompleks) yang sebenarnya tidak dapat mengukur kualitas seorang anak secara menyeluruh.
Asesmen semacam inilah akar persoalannya. Hal ini saya terangkan, saat berdiskusi dengan Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemdikbud Ristek, Asrijanty Ph.D. Pertama saya mengurut bagaimana sejarah Asesmen secara global. Tes semacam ini diarahkan pada tujuan-tujuan ekonomi, bukan pada tujuan pendidikan. Sehingga akses ekonomi akan terus menentukan. Yang paling terkenal adalah Program International Student Assessment (PISA). Tidak pernah tercatat negara miskin dari ujung Afrika atau ujung Asia mendapatkan skor PISA yang tinggi.
Sebab asesmen semacam ini hanya bisa dilaksanakan dengan bimbel atau tambahan waktu belajar yang terlepas dari pembelajaran itu sendiri.
Kedua, adalah kodrat penilaian dengan format kuantitatif. Sebab penilaian kuantitatif, pada kodratnya merubah manusia menjadi angka. Mengubah manusia menjadi sekedar aset, ‘sumber daya manusia.’
Hal ini sebenarnya bertentangan dengan konsep dasar pendidikan kita sendiri yang bermuara pada perkataan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa,’ yang diurai dalam UUD 1945 sebagai bentuk tanggung jawab negara menyelenggarakan pendidikan pada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.
Karena tes semacam ini hanya menyediakan satu jawaban yang benar, maka ia tidak mampu menggali luasnya pikiran seseorang.
Tes semacam ini tidak mampu melacak kepekaan musik Beethoven, kejeniusan Einstein yang seringkali gagal tes, atau mengapa mereka yang mendapatkan nilai skor asesmen rendah tetap bisa sukses dalam kehidupan nyata.
Oleh karena hanya tersedia jawaban tunggal (meskipun Pilihan ganda multijawaban memilih lebih dari satu jawaban, namun jawaban tersebut bersifat pasti dan tidak bisa ditawar), maka formula dalam menjawab soal semacam ini lebih menentukan daripada menguasai gagasan dan wawasan yang menjadi konten dalam soal.
Oleh sebab itu bimbel selalu lebih sukses meluluskan peserta didik dan sekolah yang diciptakan oleh negara itu sendiri yang justru tidak mampu menjamin peserta didik dapat menjawab soal asesmen kuantitatif.
Artinya untuk menghentikan laju bimbel, bukan dengan menyalahkan bimbel atau para guru yang terlibat didalamnya. Namun memikirkan ulang, menguji dan mengevaluasi; apakah soal tes semacam ini berkorelasi dengan pengalaman belajar peserta didik?
Jika jawabannya adalah tidak. Maka solusinya juga sudah jelas. Hentikan tes soal semacam ini dan mulai untuk memperbaiki proses belajar.
Anehnya, untuk mengklaim bahwa, proses belajar perlu diutamakan, justru dengan cara mengadakan tes kuantitatif kembali.
Dimana kemudian solusinya, tentu saja, yang terbaik adalah sistem bimbel yang lebih menjanjikan peserta didik memahami asesmen sumatif dalam bentuk kuantitatif. Kontradiksi semacam ini disebabkan kegagalan negara membentuk instrumen asesmen yang cocok bagi dunia pendidikan.
Masalah utamanya, baik format, bentuk dan paradigma pembuatan soal asesmen nasional meniru keseluruhan format PISA dan hanya mengganti konteksnya saja. Sedangkan sistem yang bekerja dalam soal kuantitatif semacam ini tetaplah suatu formula yang dapat dipelajari. Pengalaman menganalisis formulasi dalam berbagai bentuk soal baik LOTS maupun HOTS membuat bimbel selalu diatas angin meskipun negara selalu mencari cara baru namun tidak merubah kodrat format penilaian kuantitatif.
Dalam paparan saya dalam webinar tersebut, saya menayangkan bagaimana Tiongkok selalu mendapatkan skor tertinggi Literasi, numerasi dan sains yang dilakukan lembaga OEDC dalam PISA.
Jika ingin sukses dalam perolehan nilai, cukup tiru Tiongkok saja. Meskipun Tiongkok selalu tinggi mencapai perolehan rangking dalam PISA, apakah anda tahu akibat dari semua itu?
Pertama, orang tua dan siswa di Tiongkok membayar lebih untuk bimbel. Tentu saja hanya mereka dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang bisa mengakses bimbel.
Kedua, format PISA melahirkan sistem sekolah dengan mental ‘saling memakan’ dan ‘pemenang memiliki segalanya.’ Sehingga penyuapan dan kecurangan menjadi solusi dan kebiasaan dalam dunia pendidikan.
Ketiga, di Tiongkok guru digaji besar untuk memberikan semacam bimbel. Dengan demikian, guru dengan gaji rendah yang bertemu dengan pelajar miskin akan semakin terpuruk untuk mengikuti asesmen semacam ini.
Asesmen Nasional yang akan diselenggarakan di masa pandemik ini memiliki kepercumaan tingkat tinggi. Mengapa?
Jika benar paparan dari Pusmenjar bahwa AN tidak akan membuat perangkingan untuk tiap anak, namun perangkingan tiap sekolah dengan dirinya sendiri, bukan dengan sekolah lain, hal ini tetap mengundang persoalan lebih besar.
Jika perangkingan dalam AN tidak ada, artinya tidak ada perbandingan skor antar sekolah; pertanyaannya, mengapa pelajar di kirim ke Universitas yang selalu bangga dengan posisi perangkingan yang mereka miliki; kemudian mengapa kita mengacu PISA yang jelas-jelas melakukan perangkingan tiap negara?
Artinya guru dituntut untuk membentuk siswa tanpa perangkingan untuk dikirim pada suatu jenjang pendidikan dimana perankingan adalah ukuran suatu kualitas pendidkan. Hal ini seperti melarang membawa alat tempur pada peperangan yang jelas-jelas memerlukan banyak peralatan.
Dengan demikian negara justru menjebloskan pelajar tanpa tanggung jawab dengan cara meniadakan rangking dalam proses belajar mereka namun mengantarkan mereka pada jenjang pendidikan yang jelas-jelas menjadikan perangkingan sebagai modal utama persaingan dalam dunia pendidikan.
Seperti ranking Universitas dan ranking PISA. Namun disaat yang sama mencemooh bimbel dan kompetensi guru, serta keterlibatan guru dalam dunia bimbel sebagai biang masalah.
Bukankah pertanyaannya; Jika suatu penyelenggaraan asesmen dalam skala nasional menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan, mengapa asesmennya tidak dibatalkan saja?
Jika suatu masalah sudah jelas penyebabnya, namun mengapa akibatnya yang dipersalahkan?
Mengapa aktor pendorong kesuksesan Asesmen Nasional seperti guru, sekolah dan Bimbel malah dipersalahkan?
Selama format soal kualitatif tetap dipakai menjadi standar kelulusan, bimbel akan tetap hadir dalam berbagai bentuk meskipun pejabat moralis menyatakan bahwa mereka tidak menyukainya.
Kemampuan bercermin menjadi penting pada level ini.
Saya kira, selain perlu melakukan evaluasi kepada guru dan lembaga bimbel, penyelenggara Asesmen Nasional memerlukan instrumen yang bisa mengevaluasi instrumen mereka sendiri.
Sebenarnya, sebelum melahirkan anak haram pendidikan, mereka punya kesempatan untuk mencegahnya. Oleh sebab itu, sangat wajar jika bimbel menjadi sistem pendidikan itu sendiri, dan apa yang kita sebut sebagai cita-cita pendidikan Nasional hanya tinggal permukaannya saja. []