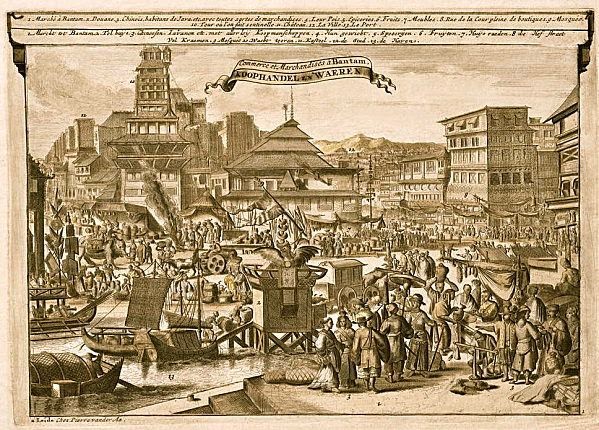Paham radikalisme tidak pernah surut. Ideologi Islam radikal; takfiri, tadhlili, terus berganti wajah. Terus diteriakkan, sekali pun sudah di luar nalar kewajaran. Termasuk dengan melontarkan tuduhan adanya pemurtadan melalui film The Santri, besutan sutradara Livi Zheng yang didukung NU Chanel. Hanya karena perbedaan pendapat seputar hukum ikhtilat, santri masuk gereja dan “percintaan” dunia remaja?
Ustad Maheer Atthuwailibi Jakarta, ustad Yahya al-Bahjah Cirebon, dan ustad Luthfi Bashori Malang, adalah contoh kecil orang-orang yang menuduh ada pemurtadan dalam film The Santri. Dalam kasus Film The Santri, tiba-tiba saja mereka menjadi ahli dan kritikus film. Cukup bermodal bahan trailler dan setumpuk kebencian dalam dada, jadilah mereka kritikus yang lantang. Bahkan, mereka sepakat memboikot penayangan film ini.
Bukti yang banyak mereka soroti adalah cuplikan adegan santriwati menyerahkan nasi tumpeng kepada orang di gereja. Dengan argumen sekenanya, mereka menuduh itulah sarana pemurtadan film The Santri. Tuduhan tidak saja ‘ghuluw’ atau berlebihan melainkan melampaui keputusan para ulama dari berbagai mazhab. Padahal, empat mazhab sepakat bahwa muslim masuk gereja tidak murtad.
Memang benar sebagian ulama mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah mengharamkan muslim masuk gereja. Pendapat tersebut dikeluarkan oleh, di antaranya, Ibnu Hajar al-Haitami (Tuhfatul Muhtaj, 2/424), Syihabuddin ar-Ramli (Nihayatul Muhtaj, 2/63), Qalyubi dan Umairah (Hasyiatu Qalyubi wa Umairah ala Syarhi al-Mahalli ala Minhajit Thalibin, 4/236).
Alasan ulama mengharamkan muslim masuk gereja adalah karena di dalam gereja terdapat setan (Ibnu Najim, Bahrur Raiq, 7/364). Namun, hukum haram tidak lantas membuat pelakunya menjadi murtad. Misal, daging babi haram. Tapi, muslim memakan daging babi tidak menjadi murtad.
Karena hukum haram memiliki ‘illat, maka ulama lain mencoba memberikan batasan, yakni hanya jika di dalam gereja terdapat gambar dan patung Yesus, bunda Maria, dan lainnya. Jika illat hukum ini tidak ada maka boleh muslim masuk gereja (Abdus Salam bin Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, 5/327).
Illat hukum ini berlaku tidak saja di dalam gereja. Tapi berlaku secara umum, termasuk di dalam rumah orang muslim sendiri. Hadits riwayat Ibnu Abbas mengatakan, “jika Nabi saw. melihat ada gambar di dalam rumah maka beliau tidak masuk hingga gambar itu dihapus/diturunkan,” (HR. Bukhari).
Illat inilah yang menjadi pedoman bagi mazhab Hanbali, dengan mengatakan bahwa muslim masuk gereja itu makruh dan bukan haram. Apalagi berlebihan dituduh murtad. Bahkan, apabila orang-orang muslim merasa tidak terganggu oleh adanya gambar dan patung dalam gereja, seperti tidak terpengaruh oleh lukisan penghias dinding di rumah, maka hal itu boleh. Jika masuknya karena keperluan penting, seperti musyawarah untuk mufakat, atau kunjungan yang memang diperlukan dalam rangka mempererat persaudaraan dan toleransi, maka hukumnya biasa saja menjadi baik.
Ulama Hanbali melihat celah nalar tersebut. Sehingga, mereka memberi hukum yang lebih ringan dibanding hukum makruh, yakni hukum mubah atau jaiz. Artinya, muslim boleh masuk gereja sekali pun ada gambar dan patung di dalamnya. Hukum jaiz tersebut dapat dilihat dalam pendapatnya Ibnu Qudamah (al-Mughni, 8/113), Sulaiman al-Marsawi (al-Inshaf fi Ma’rifatir Rajih minal Khilaf, 1/496), dan Ibnu Hazm ad-Dhahiri (al-Mahalli, 1/400).
Membolehkan umat muslim masuk gereja memiliki alasan kuat. Para ulama selain berdalil pada hadits juga berdalil berdasar peristiwa sejarah. Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah memerintahkan umat Nashrani untuk membangun gereja-gereja mereka dengan ukuran yang lebih besar dan lebih luas. Tujuan kebijakan politik Umar ra tersebut adalah agar umat muslim bisa masuk ke dalam gereja dan tidur menginap di sana (Ibnu Qudomah, al-Mughni, 8/113).
Peristiwa sejarah lain serupa terjadi saat penaklukan Negeri Syam. Pada saat itu, Umar ra dan Ali bin Abi Thalib berangkat ke Syam untuk menyaksikan kota yang baru tunduk itu. Untuk menyambut kedatangan sang Khalifah, umat Nashrani memasak masakan paling lezat untuk hidangan khalifah. Ketika hidangan siap santap, Ali bin Abi Thalib tidak melihat Umar. Dia bertanya: “kemana Umar?” Orang-orang menjawab: “beliau di dalam gereja.”
Awalnya Ali menolak ikut masuk ke gereja. Tetapi, Umar berkata: “pergilah bersama yang lain!” Ali pun mengikuti saran Umar, ia masuk ke dalam gereja, dan ikut makan bersama orang-orang Nashrani. Di dalam gereja, Ali bin Abi Thalib melihat-lihat seni ukir dan lukisan umat Nashrani itu (Ibnu Qudomah, al-Mughni, 8/113).
Kebolehan masuk gereja didukung oleh Lajnah Da-imah lil Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta’. Muslim boleh (jaiz) masuk ke dalam gereja dengan catatan untuk tujuan toleransi (at-tasamuh), memperkenalkan wajah Islam yang damai supaya mereka cinta Islam, tidak ikut-ikutan melakukan ibadah gereja, dan tidak khawatir terpengaruh oleh ajaran gereja (Fatawa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta’, Riyadh: Darul Muayyid, 1424 H., 2/115).
Sudah menjadi rahasia umum, para ulama Timur Tengah, terutama Grand Syaikh al-Azhar, terbiasa masuk gereja. Mereka duduk bersama dengan Paus dan bapak gereja lainnya. Jika masuk ke dalam gereja disebut pemurtadan, maka sungguh hal itu lebih terlihat sebagai kebencian atas nama agama dari pada membela agama dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan.
Kritik lain yang kesannya berlebihan (ghuluw) dari berdasar pada ilmu agama adalah tentang ikhtilath. Mereka mengkritik adegan para santriwati dan santriwati di suatu tempat yang sama. Selain pemandangan seperti ini hal lumrah terjadi di banyak pesantren tradisional, banyak ulama juga membolehkan ikhtilat, apalagi di dalam lembaga pendidikan. Dr. Abdul Masih Sam’an, Dosen Universitas ‘Ain Syam sekaligus ulama Kuwait, bahkan mengatakan bahwa ikhtilath antara perempuan dan laki-laki di lembaga pendidikan merupakan keharusan (la budda).
Menurutnya, negara-negara yang melarang ikhtilath jauh lebih potensial memancing kerusakan akhlak. Sebaliknya, pembiasaaan ikhtilath sejak madrasah ibtidaiyah akan mengurangi dampak buruk tersebut. Dengan alasan yang sama, Dr. ‘Adil al-Madani, seorang dosen ilmu psikologi Universitas al-Azhar, Kairo, malah melihat ikhtilath di lembaga pendidikan harus dilakukan sejak usia dini (Alwatan,18/1/2012).
Hadits yang digunakan para ulama adalah riwayat Abdullah bin Amr bin al-Ash, Rasulullah saw naik ke mimbar dan bersabda: “sejak hari ini tidak boleh ada lelaki masuk ke mughibah (perempuan bersuami yang suaminya sedang pergi-pent.) kecuali ia bersama seorang laki-laki lain, atau bersama dua perempuan di sampingnya,” (HR. Muslim, Nasa’i, dan Ibnu Hibban).
Diriwayatkan oleh Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, ia mengatakan: “Rasulullah saw mendatangi Ummu Haram binti Mulhan, lalu Ummu Haram menyuguhkan makanan pada beliau dan menyisir rambut beliau. Kemudian Rasulullah saw tertidur. Setelah bangun, Rasulullah tertawa. Ummu Haram bertanya: ‘apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasul?’ Rasul bersabda: ‘umatku maju ke medan tempur, mereka menunggangi kuda seperti gelombang laut,” (HR. Bukhari-Muslim).
Hadits-hadits di atas tidak saja mendukung bolehnya ikhtilath, bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam batas yang kewajaran, tetapi juga menjadi dalil bagi bolehnya perempuan menyisiri rambut laki-laki bukan muhrimnya. Mungkin karena melihat ada kelonggaran hukum ikhtilat disini, sebagian para kiai masih membiarkan santriwan dan santriwatinya campur dalam satu kelas, sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dicurigai secara berlebihan.
Memang, kritik yang didasari kebencian dan bukan semata ilmu pengetahuan, menyisakan banyak celah. Hal itu terlihat pula saat mereka memaknai alur percintaan (love story) dalam film The Santri dengan mengabaikan prinsip penting yang secara jelas-jelas tertulis pada layar kaca dalam thriller film itu, yakni “friendship”. Kata lain friendship adalah ukhuwah atau persaudaraan.
Adegan penyerahan buku oleh santri putra kepada santri putri sebelum berangkat ke Amerika adalah ikatan ukhuwah. Sehingga ‘love story’ hanyalah bumbu film, dan tidak lebih dari sekadar pemanis. Film tanpa kisah cinta akan terasa kering dan tidak menyentuh. Apalagi benih cinta bukan perkara dosa, bukan aib, apalagi menjadi pembusukan akhlak.
Sebaliknya, cinta adalah watak alamiah manusia, dan bekal spiritualitas. Maulana Rumi dalam sebuah risalah cintanya mengutip sebuah hadits. Pada waktu itu, seorang sahabat duduk di samping Nabi. Tiba-tiba seorang tokoh pembesar dari sukunya keluar dari arah masjid. Sahabat itu berkata pada Nabi, “wahai Rasul, saya kagum pada dia!” Jawab Nabi, “ungkapkanlah!”. Kagum di sini adalah bentuk persahabatan (friendship).
Pergeseran wacana ke ranah seni memang menarik. Tempo hari, Ustad Abdul Somad (UAS) mengkafir para penggemar K-Pop dan film drama Korea. Sekarang, ustad-ustad milenial ini mengkritik film. Modal mereka tetap sama, ideologi takfiri dan tadhlili, pengkafiran dan tuduhan sesat terhadap kelompok lain, sekalipun di luar kapasitas intelektual mereka.
Film adalah satu dimensi intelektualitas yang menggabung banyak aspek, seperti seni akting, pentas, koreografi, bahkan lighting dalam pengambilan gambar, pembuatan teks skenario, dan lainnya. Ranah kesenian adalah dunia lain di luar kapasitas ustad-ustad milenial tersebut. Syeikh Muhammad Qutub mengatakan, al-fann al-islami laisa bid dhorurah. Kesenian dalam Islam bukan perkara substansial (Muhammad Qutub, Minhajul Fann al-Islami, Beirut: Dar as-Syuruq, 1983, h. 6).
Artinya, seni Islami bukan ranah agamawan. Sebaliknya, Muhammad Qutub menekankan bahwa seni Islam mempertahankan dua hal: al-Jamal (aspek estetika) dan al-Haqq (aspek kebenaran). Estetika adalah al-haqiqah fi hadzal kawn, substansi kehidupan. Sedangkan kebenaran adalah dzurrah al-jamal, inti keindahan (Muhammad Qutub, Minhajul Fann al-Islami, 1983: 15 dan 71).
Perlunya Kearifan
Ustad-ustad selebritis hendaklah lebih banyak belajar dan membaca dari pada banyak berfatwa. Masih hangat dalam ingatan beberapa hari lalu ustad Abdul Somad (UAS) mengkafir-kafirkan para penggemar K-Pop dan film drama Korea. Lalu komunitas ustad-ustad milenial macam ini mencari garapan baru dengan mengkritik thriller film The Santri. Polanya tetap sama: berlebihan dan tergesa-gesa dalam berfatwa.
Padahal, trailer film sejak awal menampilkan seorang ustad yang mendidik karakter para santrinya, agar mereka percaya pada kemampuan diri sendiri maupun kepada mimpi yang ingin mereka raih. Ini adalah prinsip kebenaran. Dibumbui dengan adegan olahraga pancaksilat sebelum disusul oleh shalat berjamaah. Lalu apa yang bukan kebenaran?
Kebenaran lain, dengan tegas thriller itu mengatakan, santri adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah Indonesia. Ini adalah narasi soal nasionalisme. Namun, para pengkritik mungkin dihantui rasa takut karena muncul kalimat yang berbau Amerika. “Enam di antara kalian (santri) yang terpilih akan berangkat dan bekerja di Amerika. Buatlah bangga negaramu!”
Jika sutradara film The Santri maupun penulis skenarionya memaksudkan kalimat “siapa yang terpilih akan berangkat dan bekerja di Amerika” sebagai spirit belajar sains dan teknologi, maka film ini sudah benar dalam kategori Muhammad Qutub tentang batasan seni Islam. Namun begitu, cara komunitas NU sejati dengan orang-orang non-NU itu memang berbeda dalam memaknai Amerika.
Mayoritas intelektual-intelektual NU tidak pernah memilah-milah ilmu pengetahuan, antara agama dan sekuler. Antara Amerika, Eropa dan Timur Tengah. Karenanya, intelektual NU sebagian belajar di Timur Tengah dan sebagian di Eropa dan Amerika. Nasionalisme, pluralisme, menjadi konsumsi harian mereka. Tidak perlu heran kemudian bila dalam film The Santri ada cuplikan adegan Santri masuk Gereja membawa Tumpeng, sebab itu menandakan bahwa Tumpeng sebagai kreasi budaya dapat menyatukan Islam dan Gereja.
Persatuan Islam dan Gereja tidak akan pernah dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Cara paling gampang menandai musuh Islam adalah mereka memanfaatkan nama Islam untuk merusak segala hal, termasuk merusak persatuan dan kesatuan, merusak kerukunan. Ayat-ayat, hadis dan sunnah, bahkan logika dan argumentasi mereka berbalut Islam untuk membawa kehancuran dan menimbulkan fitnah.
Itulah kebenaran-kebenaran (al-Haqq) yang terdapat di dalam keindahan estetik (al-jamal) film The Santri. Kebenaran perlu dibicarakan terlebih dahulu karena al-Haqq adalah Dzurratul Jamal. Lalu apa al-Jamal dalam film The Santri? Sepeti potongan penutup thriller tersebut, “friendship” persahabatan antara santri putra dengan santri putri yang terpisahkan oleh takdir; satu pergi ke Amerika untuk belajar dan satu melanjutkan studi di Indonesia. Ini hanya persoalan kedua, menurut kategori Muhammad Qutub.
Film The Santri sudah memenuhi kategori sebagai Seni Islam, yaitu at-ta’bir al-jamil ‘an haqoiqul wujud min zawiyatut tashawwur islami, mengekspresikan keindaham tentang kebenaran-kebenaran wujud dengan cara yang Islami (Qutub, Minhajul Fann, 1983: 171). Olahraga, pendidikan karakter, nasionalisme, pluralisme, dan ukhuwah (friendship) adalah hakikat-hakikat kebenaran yang merupakan inti dari estetika Islam.
Anwar al-Jundi dalam Kitab Kaifa Yahtafizhul Muslimun biz Dzatil Islamiyah mengatakan, kesenian dalam Islam itu adalah upaya transformasi nilai (qiyam), gagasan (afkar), dan empati (masyair) kepada orang lain, dengan cara-cara estetis, membekas dalam jiwa audiens (al-Jundi, Kaifa Yahtafizhu, Beirut: Tsaqafiyah, 1985). Bagaimana cara hati audiens tersentuh? Tentu saja relatif, sesuai spirit jaman. Jika roman dan drama adalah cara yang populer di suatu jaman maka drama pun bisa dipakai sebagai wasilah. Dan hal itu tidak menyalahi aturan Islam.
Penulis yakin, tidaklah elok kita mengkritik sebuah karya seni berupa film hanya bermodalkan “cangkeman” menurut istilah orang Jawa. Yaitu, justifikasi-justifikasi tidak bermodal dan receh. Jika memang kelompok yang suka menghujat kesenian ini punya versi sendiri, tampilkanlah dalam wujud karya nyata. Buatlah film tandingan. Di sanalah kita akan bangun perdebatan tentang esensi dan substansi karya seni Islam.
Terlepas dari kekurangannya, Film The Santri sedang memperjuangkan spirit nasionalisme, pluralisme, inklusifitas, persaudaraan, dan kerukunan antar iman. Selebihnya, hanyalah tafsir yang berlebihan dan ketakutan tak beralasan. Kesimpulan ini didapatkan, karena misalnya, ketika film Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Pesantren Rock’N Roll dan, 212 The Power of Love, yanga adegannya lebih fulgar, mereka justru antusias mengapresiasi, tetapi giliran THE SANTRI, yang sebenarnya masih dalam batas kewajaran, mereka memberi cap liberal dan tidak syar’i!? Sesunguhnya kalian ini ada apa? Apakah ‘benci’ pada Kiai NU? Atau mungkin ada sesuatu yang kami tidak tahu?