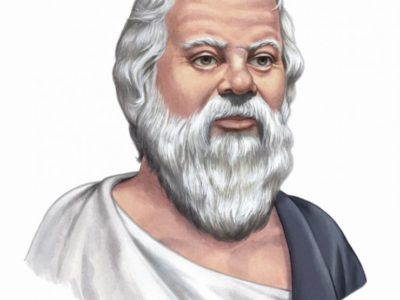Dalam hakikatnya, pernikahan adalah ibadah, dan pada realitanya juga berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan, baik sosial, budaya, psikologi, bahkan hukum. Sebagai suatu perjanjian atau ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidhan), ikatan pernikahan tersebut melibatkan berbagai aturan ketetapan syara’ yang sakral. Oleh karena itu, adanya kafa’ah menjadi salah satu bentuk kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup yang sangat urgent, terutama dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. Unsur kafa’ah mencakup keseimbangan, keserasian, dan kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sehingga apabila dalam suatu pernikahan tidak ada unsur kafa’ah, maka dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam menciptakan keharmonisaan rumah tangga.
Imam Al Bakr Ad Dimyathiy dalam Kitab I’anatu At Thalibin mendefinisikan, kafa’ah adalah persamaan suami terhadap istri dalam beberapa aspek yang telah ditentukan. Dalam beberapa literatur Arab, khususnya karya ulama Syafi’iyyah juga menyebutkan beragam pengertian kafa’ah yang mengindikasikan hal yang sama, yaitu kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri atau persamaan derajat suami di hadapan istri. Di antara keduanya -suami dan istri- haruslah seimbang, agar tidak saling memberatkan atau menimbulkan ketimpangan peran yang dilatarbelakangi perbedaan kualitas seperti dalam pendidikan, kedudukan sosial, keturunan (nasab), sampai kualitas agamanya.
Para ulama syafi’iyah mengkualifikasikan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam kafa’ah. Di antaranya, pendapat Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu’ Syarh Al Muhaddzab yang mengkategorikannya menjadi lima aspek;
- Keturunan (nasab), menjadi pertimbangan dalam pernikahan, tidak lepas dari tradisi orang Arab di zaman dahulu, di mana orang bangsa Ajam tidak setara dengan orang bangsa Arab, orang Arab suku Quraiy tidak setara dengan suku selain Quraisy, Kesetaraan nasab ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab yang sama halnya dengan menjaga kehormatan keluarga dan kualitas generasi.
- Agama (ad din), dalam hal ini seorang laki-laki yang fasik pemabuk, pezina, atau orang yang tidak sholat tidaklah sekufu dengan perempuan merdeka yang terjaga agamanya (afifah), Allah SWT melalui firman-Nya telah menjelaskan bahwa tidak ada kesetaraan antara orang mukmin dengan orang fasik dari segi manapun, yakni dalam QS. As Sajdah ayat 18, yang terjemahnya : “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama.”
- Status kemerdekaan (hurriyah), seorang hamba sahaya tidaklah setara dengan perempuan merdeka, begitupun juga seorang laki-laki merdeka tidak setara dengan seorang hamba sahaya perempuan (amat) karena perbedaan status di antara keduanya. Hal ini dikarenakan seorang hamba sahaya akan kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya yang merdeka dan keluarganya yang berkecukupan.
- Pekerjaan/profesi (shun’ah), seorang laki-laki yang berprofesi rendahan tidaklah setara dengan perempuan yang berprofesi lebih tinggi (dinisbatkan pada ayahnya), seperti tukang sapu jalan, tukang bekam, penjaga kantor, penggembala, dan penjaga kakus tidaklah setara dengan anak perempuan dari penjahit. Sedangkan seorang laki-laki anak penjahit tidak sekufu dengan anak pedagang, dan mereka semua tidak sekufu dengan anak perempuan seorang alim, tidak pula anak perempuan seorang hakim. Dan aspek ini ditinjau berdasarkan adat kebiasaan, pekerjaan rendahan itu dianggap suatu kekurangan.
- Selamat dari cacat pernikahan (salamah min ‘uyub an nikah), seperti cacat pada laki-laki yakni memiliki gangguan jiwa, terkena penyakit lepra/kusta, trputus dzakarnya, dan impoten, sedangkan cacat pada perempuan yakni gangguan jiwa, penyakit lepra/kusta, alat kelamin tersumbat daging (rataq), alat kelamin tersumbat tulang (qarnu), dan lainnya.
Dalam kitab Tuhfatu Al Muhtaj fi Syarhi Al Minhaj, Imam Ibnu Hajar Al Haitamiy menjelaskan bahwa seorang perempuan boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu’ (setara) harus dengan kerelaan perempuan tersebut dan walinya, sehingga pernikahan tetap sah dan kafa’ah bisa digugurkan. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW menikahkan Fatimah binti Qais yang berbangsa Quraisy dengan Usamah seorang hamba sahaya, begitu juga Abi Hudzaifah jug menikahkan hamba sahayanya yang bernama Salim dengan keponakan perempuannya, putri dari Al Walid ibnu Utbah. Di samping itu, Rasulullah SAW menikahkan putri-putri beliau tanpa mensyaratkan adanya kafa’ah (keesetaraan), namun hendaklah memiliki alasan kebutuhan yang mendesak, misalnya menjaga eksistensi keturunan. Sebaliknya, apabila tidak ada kerelaan dari pihak perempuan (calon istri) dan walinya atau tidak ada kerelaan dari salah satunya, maka kafa’ah harus menjadi syarat agar pernikahannya sah, dalam hal ini wali mujbir memegang otoritasnya untuk menikahkan si perempuan dengan laki-laki yang sepadan, pilihan wali.
Pembahasan tentang kafa’ah sejauh ini belum diketahui dalilnya secara eksplisit di dalam Al Qur’an, yang notabene justru lebih sering membahas tentang persamaan / kesetaraan manusia, begitupun juga para ulama membahas tentang kafa’ah terbatas pada hadits-hadits nabi yang menjelaskannya sebagai adat kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu. Sehingga kafa’ah bukan menjadi suatu keharusan melainkan pertimbangan yang dianjurkan dalam memilih calon pasangan hidup. Dan para ulama juga berpendapat bahwa kafa’ah boleh ditinggalkan apabila kedua belah pihak saling rela satu sama lain atau pada masa sekarang dianggap dengan saling mencintai dan menghormati.
Dalam realita zaman sekarang, suatu pernikahan dapat terlaksana bahkan dengan tanpa disertai adanya kafa’ah di dalamnya. Dinamika kehidupan yang semakin kompleks memungkinkan hal ini terjadi pada siapapun, kini seseorang dapat menikah dengan siapapun pilihannya yang dicintai tanpa membeda-bedakan latar belakang kehidupan pasangan, dan kafa’ah tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan pernikahan. Karena pada sisi lain, juga penting mempertimbangkan hal-hal semacam kesiapan mental, finansial, kehidupan sosial, dan lainnya. Pada taraf ini, kafa’ah hanya dilakukan bagi kalangan agamawan, bangsawan, dan sebagian orang yang menyadari pentingnya kafa’ah demi menjaga eksistensi generasi yang berkualitas. Kafa’ah yang identik sebagai salah satu adat kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu, pada masa sekarang terkesan sulit diaplikasikan sepenuhnya, karena terdapat sebagian dari beberapa aspeknya sudah dianggap tidak relevan mengingat zaman yang terus berkembang dan karena terdapat alasan lain yang dianggap lebih penting.
Oleh karenanya, implementasi kafa’ah di masa sekarang, hendaknya perlu dipahami kembali sebagai suatu hal yang dipertimbangkan dalam mencapai tujuan pernikahan agar tidak sepenuhnya diabaikan. Terdapat beberapa aspeknya yang nampak tidak relevan, seperti status kemerdekaan seseorang, yang mana di masa kini semua orang merdeka atas dirinya sendiri dan persamaan kedudukan umat manusia sudah terjamin. Kemudian aspek pekerjaan yang biasanya berkaitan dengan status sosial, aspek kesehatan fisik dan psikis, aspek keagamaan, aspek nasab atau keturunan, semua itu sudah tidak begitu menjadi perhatian ketika kedua belah pihak, antara calon suami dan calon istri saling rela (taraadlin) atau saling mencintai dan menerima pasangannya dengan sepenuh hati dan cenderung menerima konsekuensinya. Nampak sejalan dengan maksud suatu kaidah fiqh “ridla bi as syai’i ridla bima yatawallada minhu” yang mendasari seseorang dalam memilih pasangan hidup, apapun konsekuensinya akan ditempuh jika saling rela.
Selain itu, berbicara tentang integritas keagamaan seseorang, misalkan perihal apakah ia termasuk orang fasik atau tidak, di masa sekarang tentu sulit diketahui kecuali dengan melakukan penyelidikan yang merepotkan. Namun yang terpenting dari itu semua ialah pertimbangan utama dalam kafa’ah untuk memiliki satu keyakinan agama yang sama dengan pasangan, karena pernikahan orang islam dengan orang yang berbeda agama dan keyakinan tidak sama sekali dibenarkan oleh Allah SWT.
Implementasi aspek-aspek kualifkasi kafa’ah pada era sekarang dapat dipahami menjadi dua sudut pandang; Pertama, kafa’ah dianggap relevan, yakni ketika menghasilkan maslahah lebih banyak, misalnya seorang Ning (putri Kiai) akan lebih baik dinikahkan dengan seorang Gus (putra Kiai) atau santri yang memiliki keilmuan tinggi agar bisa bersanding dengan Ning tersebut. Karena apabila seorang Ning dinikahkan dengan laki-laki biasa (awan) dikhawatirkan akan mengalami kesulitan, apalagi dalam hal bertanggung jawab mengemban regenerasi pengasuh pesantren. Kedua, kafa’ah dianggap tidak relevan, apabila kafa’ah menghasilkan banyak kemadlaratan, misalnya ketika kafa’ah dijadikan alasan untuk pernikahan dengan membeda-bedakan kedudukan orang lain atau bahkan sampai merendahkan orang lain, alih-alih menjunjung tinggi kesetaraan antar sesama umat manusia. Maka yang demikian ini tidaklah dibenarkan dalam menjaga hubungan persaudaraan di antara manusia.
Apabila kafa’ah bisa digugurkan sebab adanya keridlaan (kerelaan) dari pihak calon istri dan walinya, juga tidak sepenuhnya bisa menjamin tercapainuya tujuan pernikahan yang diharapkan, karena sewaktu-waktu bisa berubah sejauh mana kedua pihak bisa saling menjaga kepercayaan dan bekerja sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk itu, selain dengan pentingnya membuat perjanjian pra-nikah, agar dapat menarik kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dari lika-liku pernikahan, berdasar kaidah ad dlararu yuzal, kafa’ah tetaplah menjadi pertimbangan pernikahan karena dirasa lebih besar menghasilkan maslahahnya daripada madlaratnya. Begitupun juga berdasar kaidah maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu, jika tidak bisa seluruhnya, setidaknya sebagian aspek kualifikasi kafa’ah tidak ditinggalkan dan tetap diberlakukan sesuai kebutuhan yang dirasa penting asalkan tidak melewati batas yang telah menjadi ketetapan syari’at islam dalam mencapai tujuan syari’at hifdhu an nasl. Wallahu a’lamu bisshawaab.