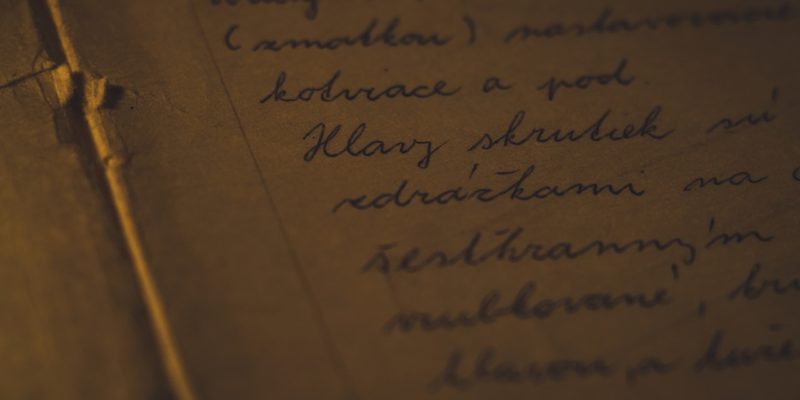Ini adalah catatan tentang keresahan saya untuk kesekian kali tentang betapa buruknya kualitas berbahasa kita (wa bil khusus: para akademisi) sekarang, terutama dalam konteks akademis.
Saya hendak menegaskan: yang harus diperbaiki dalam tradisi kesarjanaan di Indonesia adalah aspek kebahasaan, terutama bahasa ilmiah. Saya melihat mutu bahasa Indonesia yang dipakai oleh sarjana kita di jurnal-jurnal ilmiah, masih amat buruk. Yang menyedihkan saya, tampaknya, nyaris tak ada yang menyadari bahwa ada isu yang serius di sini. Kesan saya, seolah-olah ndak ada soal dalam bidang kebahasaan ini (as if the businness is going usual).
Untuk hal ini, kita perlu belajar pada praktek berbahasa dalam kalangan sarjana yang menggunakan bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa Barat yang lain (terutama Jerman dan Perancis). Secara rerata, bahasa Inggris yang dipakai dalam konteks akademis, mutunya sudah tinggi. Ini bukan semata-mata karena ada editor bahasa di jurnal-jurnal ilmiah di sana, tetapi karena masing-masing sarjana yang menulis untuk jurnal-jurnal itu, sudah menjadi editor bagi dirinya masing-masing. Mereka, secara orang per orang, sudah terlatih menulis dengan bahasa yang amat baik.
Apa yang saya sebut dengan “berbahasa yang baik” ini menyangkut, misalnya dan terutama, cara membuat kalimat yang benar dan rapi secara gramatik; termasuk cara meletakkan tanda baca yang pas. Salah satu model penggunaan tanda baca dan sekaligus gaya bahasa akademis yang “indah”, menurut saya, adalah Clifford Geertz, antropolog Amerika yang menulis buku yang amat saya gemari, terutama secara kebahasaan, berjudul The Interpretation of Culture. Dia paling lihai memakai apa yang, dalam tradisi pesantren, disebut “جملة معترضة”, atau anak dan cucu kalimat.
Saya nggak tahu, dari mana memulai perbaikan dalam aspek ini. Tapi, yang jelas, kalau aspek bahasa ini ndak segera dibenahi, dan kalau masyarakat akademis kita ndak disadarkan bahwa this is BIG issue, kita tidak akan membuat progres yang berarti dalam bidang keilmuan di negeri ini.
Saya, hingga sekarang, masih belum bisa menikmati, dan tidak pernah bisa sabar membaca karya-karya akademis yang ditulis dalam bahasa Indonesia, karena kualitas bahasa di sana masih buruk sekali; susah dinikmati. Hanya beberapa sarjana Indonesia yang bisa saya nikmati tulisan-tulisan mereka, salah satunya adalah kawan saya, Taufik Adnan Amal. Sejak menulis skripsi di IAIN Yogya tentang Fazlur Rahman (sarjana besar asal Pakistan yang merupakan gurunya Cak Nur dan Buya Syafii Maarif) pada tahun 80-an dulu, Taufik sudah menunjukkan cara memakai bahasa Indonesia akademis yang rapi. Kepada mahasiswa saya, saya selalu menganjurkan untuk membaca karya-karya Taufik Adnan Amal sebagai model bernahasa Indonesia yang baik, rapi, indah dalam konteks akademis.
Sarjana lain yang saya suka karena berbahasa Indonesia yang baik dan indah (sekali lagi dalam konteks akademis) adalah filosof Indonesia, Fransisco Budi Hardiman yang sekarang mengajar di UPH. Saya juga harus menyebut nama satu ini Abdul Gaffar Karim. Sejak menulis skripsinya tentang Gus Dur di UGM pada tahun 90-an dulu, Mas Gaffar sudah menarik perhatian saya, karena menulis dengan bahasa Indonesia yang rapi dan baik.
Tentu masih banyak contoh sarjana lain yang berbahasa dengan baik. Tetapi secara umum, kualitas bahasa Indonesia di lingkungan akademis kita saat ini sungguh masih buruk-ruk-ruk. Mutu suatu gagasan, bagi saya, tak sekedar dinilai berdasar gagasan itu “qua” gagasan, tetapi juga oleh bentuk dan ‘style’ bahasa yang dipakai penggagas bersangkutan.
Para ulama besar dalam sejarah Islam, memakai bahasa Arab akademis yang indah. Dua contoh yang dapat saya sebut adalah Imam Syafii dan Imam Ghazali. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafii berjudul Al-Risalah (tentang ushul fiqh), sejatinya bukan sekedar karya akademis yang penting, tetapi juga sebuah monumen sastra. Barangsiapa pernah membaca kitab ini, dan memahami keindahan bahasa Arab, akan mengerti kebenaran statemen saya ini.
Begitu pula, kitab Ihya’ karya al-Ghazali: bagi saya, bukan sekedar karya besar yang penting secara akademis, tetapi juga secara literer/sastra.
Sarjana yang “sungguhan” selalu bergulat dengan soal bahasa. Jika ada seseorang yang disebut sarjana, tetapi tidak pernah menganggap penting aspek bahasa dari karya akademis, saya meragukan kesarjanaan orang bersangkutan.
Sekian.(HNZ)