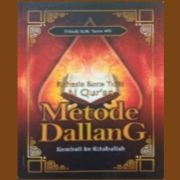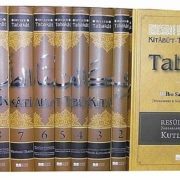Anda semua yang membaca tulisan ini tentu bersepakat, bahwa kita semua terlahir dari seorang Ibu. Ibu adalah orang yang memiliki derajat tinggi dalam tatanan kehidupan manusia. Tentu ayah pun tidak dapat dikesampingkan peranan dan penghormatan baginya. Namun ibu memiliki tempat spesial. Bahkan argumentasi ini ditopang dengan alasan teologis maupun logis. Teologis lantaran Nabi Saw pernah ditanya seorang sahabat, “wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. (HR. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad, sanadnya hasan).
Sementara alasan logis merujuk bahwa Ibu-lah yang selama lebih dari sembilan bulan mengandung kita di dalam rahimnya. Segala asupan gizi dan aneka logistik lainnya kita peroleh darinya. Bahkan setelah terlahir pun, kita masih memerlukan ASI darinya dan aneka layanan dan kasih sayang beliau. Maka sudah barang tentu, wajar belaka jika kita secara relasi manusiawi, kita sangat berhutang budi kepada beliau, pun kepada ayah tentunya.
Sejarah Peringatan Hari Ibu
Peringatan Hari Ibu di negeri ini telah diresmikan sejak era pemerintahan Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden RI No.316 Tahun 1953. Namun, sejarah tanggal 22 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal Hari Ibu sebenarnya bermula jauh sebelumnya. Yakni mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I yang dihelat tanggal 22-25 Desember 1928, atau hanya beberapa pekan setelah Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Sebagaimana terekam dalam buku Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1991) yang ditulis Suratmin dan Sri Sutjiatiningsih, kongres tersebut dilangsungkan di Yogyakarta, tepatnya di Ndalem Joyodipuran. Sekarang, gedung itu digunakan sebagai Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu diikuti oleh tidak kurang dari 600 perempuan dari puluhan perhimpunan perempuan yang terlibat. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, juga usia.
Sejarah Hari Ibu dan Kesetaraan Perempuan Panitia Kongres Perempuan Indonesia I dipimpin oleh R.A. Soekonto yang didampingi oleh dua wakil, yaitu Nyi Hadjar Dewantara dan Soejatin. Dalam sambutannya, dinukil dari buku karya Blackburn, R.A. Soekonto mengatakan: “Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.” “Artinya,” lanjut R.A. Soekonto, “Perempuan tidak [lantas] menjadi laki-laki, perempuan tetap perempuan, tetapi derajatnya harus sama dengan laki-laki, jangan sampai direndahkan seperti zaman dahulu.” Selain diisi dengan pidato atau orasi tentang kesetaraan atau emansipasi perempuan oleh para tokoh perempuan yang terlibat, kongres ini juga menghasilkan keputusan untuk membentuk gabungan organisasi perempuan dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).
Slamet Muljana dalam buku Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan (2008), memaparkan dua tahun setelah kongres pertama itu, kaum perempuan di Indonesia itu menyatakan bahwa gerakan perempuan adalah bagian dari pergerakan nasional. Dengan kata lain, perempuan wajib ikut serta memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab untuk membangun negeri ini. Bukan saja perempuan hanya dikirim dalam urusan domestik an sich namun lebih dari itu, ia memiliki kans yang sama untuk berkiprah dan membangun kemaslahatan bagi sekelilingnya, seluas-luasnya.
Peran dan Tantangan Perempuan
Jika kita membaca sejarah di atas, kita setidaknya dapat merumuskan aspirasi para perempuan pada zaman tersebut. Semangat yang ingin digelorakan oleh perempuan dan ibu pada zaman itu ialah dua hal. Pertama, persamaan hak. Kedua adalah rekognisi atau pengakuan. Artinya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lantas menjadikan adanya penafian atau subordinasi antar satu sama lain. Semua elemen memiliki hak, tanggung jawab serta kesempatan yang sama untuk “berbuat” bagi kemaslahatan. Tentu maslahat tidak dalam kaca mata sempit dan paksaan. Harus ada kesempatan yang terbuka lebar bagi keduanya untuk memilih mana medan juang dan jihadnya, sejauh tidak mengabaikan kewajiban atau tupoksi hakikinya masing-masing.
Oleh karena itu modal utama untuk mencapai cita-cita luhur itu – sekurang-kurangnya- ada tiga hal. Pertama; pengetahuan. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan merengkuh pendidikan setinggi mungkin. Tidak boleh ada stereotip bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, karena kelak ia hanya akan kembali ke “jalan ninjanya” yakni, dapur, sumur dan kasur. Stigma primitif ini harus dilenyapkan. Pendidikan yang baik dan unggul akan menghasilkan mutu manusia yang unggul pula. Perlu diingat bahwa perempuan adalah calon ibu. Ibu akan menjadi madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anaknya. Semakin baik kwalitas pengetahuan seorang ibu maka akan semakin baik pula putra-putri yang dihasilkan dan dididik oleh tangan mulia tersebut.
Kedua adalah akhlak atau moral. Perempuan (tentu beserta laki-laki) sebagai para calon ibu yang akan mendidik putra-putrinya harus memiliki moral yang baik. Karena mereka akan menjadi teladan dan kompas moral serta inspirasi bagi anak-anaknya. Maka dengan keteladanan akhlak yang baik, cita-cita memiliki generasi penerus yang baik akan menemukan probabilitas atau kemungkinan yang tinggi. Bahkan dikatakan dalam sebuah ungkapan; perempuan ialah penopang sendi-sendi sosial. Jika ia menjunjung nilai-nilai moralitas maka kehidupan sosial akan baik, namun jika sebaliknya, kondisi sosial pun akan tidak baik pula.
Ketiga, kesempatan dalam mengaktualisasikan diri. Hari ibu harus dimaknai bahwa perempuan ialah manusia yang utuh dengan segala “otonomi” dan nalurinya. Perempuan tidak hanya manusia yang diseting untuk sirkuit dalam dan sempit, namun ia juga harus diberi kesempatan dalam sirkuit luar dan luas. Maksudnya ialah ibu sebagai perempuan tidak boleh hanya diberi panggung untuk mengurusi dan ngopeni urusan rumah tangganya saja tanpa diberi hak serta pilihan untuk mengakomodir keinginannya untuk “keluar” dan berbuat sesuatu. Ibu (tentu ialah seorang perempuan) dan ayah (tentu ialah laki-laki) adalah sama-sama khalifah fil ardh. Mereka sama-sama diberi taklif oleh Rabb tuk menjadi pengelola bumi. Bumi dengan segala kompleksitasnya dituntut untuk dikelola secara kolektif-kolegial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki harus bersama-sama mengelolanya dengan baik dan berkeadilan. Kata kuncinya ialah adil serta proporsional. Dan keadilan akan terwujud dengan komunikasi dan kepercayaan. Maka apakah kita sudah saling berkomunikasi dan percaya?
Akhirul kalam, Selamat Hari Ibu. Semoga engkau , Ibu.. senantiasa dalam lingdungan Allah, kasihNya dan sayangNya….. Amin….