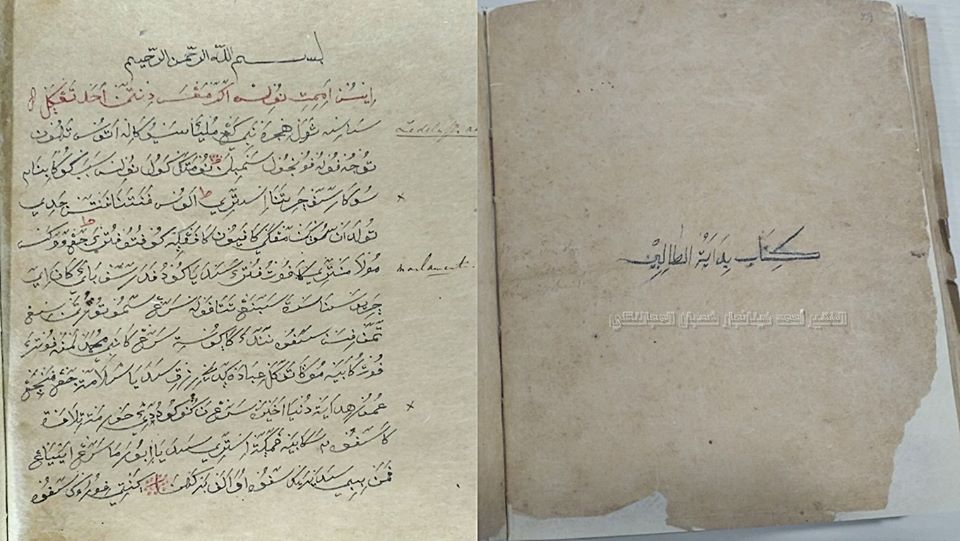Sore itu saya masih santai di depan halaman rumah bermain bersama anak saya Fayyad Ahmad Mutamakkin, tiba-tiba handphone saya berbunyi dan terlihat notifikasi pesan pribadi melalui whatsapp (WA) dari Gus Afthon, “Mbak Haty penulis dua barista nopo wonten ten grup DSC pak dosen?
saya jawab dereng gus, nopo jenengan wonten kontaknya?
Mboten, namung biasa DM lewat Instagram, beliau sepupu istri saya pak dosen,
lalu saya balas “cubi jenengan tawari masuk di DSC gus, ceritakan ada Ning Khilma Anis (Hati Suhita) juga, kita perlu promosikan novelnya yang berbasis pesantren, saya malah dereng maos novelnya gus. sambil saya sertai emosi senyum, siap pak dosen jawaban dari gus afthon.
Demikian adalah asbabul wurud saya kenal dengan Najhaty Sharma, penulis novel bestseller “Dua Barista” beberapa menit berlalu saya mendapatkan pesan pribadi melalui WA dari Ning Aida Mudjib Jombang yang mengirim cerita mengenai Ning Haty penulis novel itu, pucuk dicinta ulam tiba, ternyata beliau sudah akrab dan memberikan nomor ning Haty.
Segera saya ambil HP saya yang tergeletak di atas meja kerja dan mengirimkan pesan kepada Ning Haty “Assalamu’alaikum Ning Haty, dalem Hamid saking Dunia Santri Community (DSC), rencange Gus Afthon dan Ning Aida.
Wa’alaikum Salam Masyaallah Inggih, Maturnuwun sampun menyapa kawulo, demikian adalah balasan dari Ning Haty yang sangat ramah dan low profile. Singkat cerita saya meminta beliau untuk bedah novel “Dua Barista” melalui online di komunitas Dunia Santri Community, dan beliau mengiyakan.
Tepat dua hari setelah perkenalan saya dengan Ning Haty tiba-tiba ada kiriman paket, saya buka pelan-pelan dan ternyata isinya “wow” novel “Dua Barista” dengan detail saya mencari tahu siapa pengirimnya dan ternyata tertulis Najhaty Sharma. Subhanallah sang mualif “Dua Barista”.
Tidak membutuhkan waktu lama sebenarnya untuk mengkhatamkan novel yang mempunyai ketebalan 492 halaman itu karena tulisannya yang enak, mengalir dan mengaduk aduk emosi, di tengah-tengah jadual saya #WorkFromHome akhirnya saya menyelesaikan novel tersebut.
Ketika membaca judulnya sekilas “Dua Barista” kita akan membayangkan tentang kopi, kafe dan segala yang berhubungan dengannya, namun isinya sesuatu yang berbeda.
Novel ini menurut saya adalah novel yang sangat berani, berisi tentang auto kritik untuk tradisi-tradisi pesantren, mulai dari bagaimana kehidupan para gus dan ning yang hedon dan glamour, budaya patriarki, penerus kerajaan pesantren dan kebiasaan umroh oleh keluarga pesantren.
Ning Aida dalam tulisan sebelumnya di pesantren.id dan perempuanmembaca sudah panjang lebar meresensi mengenai novel ini, ada yang menggelitik saya mengenai novel ini,
bukan tentang poligami yang dilakukan oleh Gus Avash dengan alasan Ning Mazarina (Ning Maza) sudah tidak mungkin punya keturunan karena penyakit, kemudian memilih Mbak Meysaroh (Mbak Mey) yang awalnya adalah seorang khodimah sebagai istri kedua dengan harapan mendapat keturunan.
Sebagai penerus estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Tegalklopo, Bukan persaingan antara Ning Mazarina dan Mbak Meysaroh yang berlomba-lomba menjadi barista demi meraih hati Gus Alvash.
Menurut saya novel ini juga bukan membahas tentang pro atau kontra poligami, poligami hanya sebagai stimulus saja (walau saya akui, kisahnya juga mengaduk-aduk perasaan, dan membuat kita baper).
Inti dari novel ini adalah mengajak kita untuk merenung bersama untuk selalu belajar adil baik sejak dalam pikiran, adil dalam menilai sesuatu, serta adil dalam perbuatan,
mensyukuri apa yang ada, serta memberikan pesan bahwa seorang pengasuh pesantren harus memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat sekitar.
Selanjutnya ada space menarik yang diceritakan dalam novel ini tentang bagaimana sikap santuy Ning Maza ketika mendapatkan Fitnah, beliau teringat sebuah Maqolah popular:
Al asghoru yatahaadatsu alal ashkhosh. Al akbaru yatakhadatsu alal afkar, wal mutawasitu yatakhadatsu alal akhdast.
ciri-ciri orang kerdil adalah cenderung membicarakan orang lain, ciri-ciri orang besar cenderung membicarakan gagasan atau pemikiran. Sedangkan ciri-ciri orang yang sedang diantara keduanya adalah cenderung membicarakan keadaan atau hal yang baru tejadi” (2B Hal. 449).
Najhaty Sharma memberi gambaran epic mengenai style ning Maza dengan latar belakang tradisi Jawa Timur seorang Ning yang alim, smarth, cantik, cerdas dan fashionable.
Ning Maza yakin kaum pesantren tetap dapat mengepakkan sayap selama kita memegang teguh apa yang menjadi landasan. karena dalam kemajemukan membutuhkan ruang-ruang tanpa batas bagi santri itu sendiri, maka melebur dengan karya adalah suatu keharusan (2B Hal. 451).
Penulis juga memotret kehidupan Mbak Mey sebagai santri dari Dieng Wonosobo Jawa Tengah yang alim, sederhana, pandai dalam hal pekerjaan domestik rumah tangga serta membaur dengan masyarakat.
Hal ini mengamini tulisan dari Raedu Basya tentang perbandingan santri Jawa Tengah dan santri Jawa Timur. (lihat https://alif.id/read/raedu-basha/membandingkan-santri-di-jawa-tengah-dan-jawa-timur-b217309p/).
Santri dan pesantren Jawa Tengah memiliki tradisi lebih egaliter daripada santri Jawa Timur.
Jawa Tengah mempunyai tradisi pesantren yang berbeda dengan jawa timur, perbedaan latar belakang masyarakatnya, mengakibatkan perbedaan dalam cara riyadhoh serta strategi dakwahnya, (ada salah satu kiai sepuh dawuh “kiai Jawa Tengah itu lebih suka puasa dan hidup sederhana, sedangkan kiai Jawa Timur lebih suka qiyamullail dan berpenampilan menarik).
Kiai Jawa Timur mengidolakan sosok Sunan Ampel yang kharismatik beserta strategi dakwahnya, demikian pula dengan Kiai Jawa Tengah yang meneladani karakter Sunan Kalijogo yang sederhana besertai strategi dakwahnya pula. ini merupakan perbedaan apik yang saling melengkapi.
Salah satu pesan penting yang ingin disampaikan oleh Najhaty Sharma adalah kesadaran Gus Alvash tentang kebersyukuran, dan semakin rajin dalam mengajar.
Pesantren bukanlah bisnis yang dianggap prestice sehingga harus posesif menjaganya dengan keturunan, kenapa takut mengkader orang lain (santri) karena warisan ilmu tidak selalu bisa dilanjutkan dengan garis keturunan semata (nasab) tetapi bisa juga diwariskan melalui garis keilmuan (sanad).
Bukankah santri juga seorang anak ideologis? Sehingga alasan poligami mengatasnamakan agama dan dengan alasan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pesantren bukankah bentuk dari kesombongan? (2B Hal. 458).
Kuy kita baca “Dua Barista” buah novel genre pesantren mahakarya Najhaty Sharma, ikuti iramanya, nikmati kisah-kisahnya dan rasakan sensasinya!