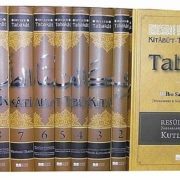Sejak manusia menemukan jarum jahit. Mulailah mereka merangkai dan menyulam bahan menjadi pakaian. Waktu terus bergulir dan masa pun terus berganti. Kali ini mereka memakai kain dan merangkainya, hingga melahirkan penemuan yang kita kenal sebagai baju, celana dan semacamnya. Manusia pertama yang menciptakan jarum jahit. Entahlah ia pernah berpikir penemuannya akan membawa pengaruh besar terhadap peradaban umat manusia.
Tersebutlah seorang berkebangsaan amerika bernama Elias Howe yang mematenkan temuan sebuah mesin jahit. Mesin ini membawa manusia kepada era dimana pakaian dikatakan sebagai gaya hidup. Kita mafhum sekarang sebagai fashion. Para desainer pakaian tak henti-hentinya menciptakan gaya baru. Mereka bersaing menciptakan pakaian yang tak pernah ada sebelumnya. Akhirnya kita pun maklum ada pakaian-pakaian tertentu yang disebut sebagai trend fashion.
Setiap profesi memiliki pakaian yang berbeda, pakaian buruh tak sama dengan pekerja hiburan. Seragam tentara berbeda dengan seragam polisi. Sekalipun sama-sama aparat Negara. Begitupula dengan kaum intelektual kita, didikan pesantren dengan didikan kampus memiliki pakaiannya masing-masing. Mereka yang murni mendapat pendidikan pesantren cenderung selalu memakai sarung. Ciri khas katanya. Sebaliknya, bagi lulusan kampus, celana yang dikenakannya.
Lalu mereka saling mengklaim, separuh dari mereka mengatakan bahwa sarung lah pakaian khas orang Indonesia. Sedangkan memakai celana itu merupakan didikan barat. Mereka menyatakan kalau celana adalah salah satu bentuk westernisasi. Separuhnya lagi tentu saja menolak dan menyatakan kebalikan dari ungkapan yang pertama.
Tidaklah dua pendapat ini bisa dibenarkan ataupun disalahkan. Di Negara kita ini, santri sudah tidak bisa dilepaskan dari sarung karena keduanya sudah menjadi identik. Begitu pula dengan mahasiswa dan kampus. Pernahkah kita melihat mahasiswa yang hendak kuliah mengenakan sarung. Tentunya celana lah yang dipakainya. Mengaca dari keduanya, sangatlah bijak kalau kita katakan kesemuanya merupakan ciri khas nusantara di kalangan intelektual.
Sekarang problemnya pada sarung. Di beberapa tempat di Indonesia, suatu daerah terkadang memiliki puluhan pondok pesantren. Mulai dari pesantren dengan ribuan santri sampai pesantren dengan puluhan santri saja. Dengan banyaknya pesantren di daerah tersebut, banyak pulalah santri yang tumpah ruah. Tidak hanya di dalam pesantren tetapi juga diluar. Yang diluar itu, terkadang santri yang memiliki keperluan keluar pesantren atau alumni yang menjaga eksistensinya dengan tetap menggunakan sarung.
Budaya sarungan, selain sudah melekat dan menjadi kebiasaan warga setempat. Juga didukung oleh tokoh-tokoh daerah itu. Pada akhirnya masyarakat menjadi salah kaprah dan biasa saja memakai sarung ke sembarang tempat. Mereka menggunakannya ke pantai, kolam renang, dan pusat-pusat perbelanjaan. Lebih parahnya lagi, kalau-kalau mereka mengenakannya untuk pergi ke tempat-tempat maksiat.
Barangkali hari ini biasa saja. Tapi tidak menutup kemungkinan pada hari-hari berikutnya akan menjadi suatu keidentikan. Di masa yang akan datang tentulah kalau ini terus terjadi, sarung tidak akan lagi identik dengan tempat peribadatan. Tidak lagi identik dengan musala, tidak lagi identik dengan masjid, juga tidak lagi identik dengan pengajian. Tetapi sarung akan identik dengan pantai, akan identik dengan konser, identik dengan tempat-tempat hiburan lainnya. Atau bahkan akan identik dengan tempat maksiat.
Lalu hadir sebuah varian baru, sebuah model baru. Model yang satu ini mencoba memadukan antara celana dan sarung. Kalau kita lihat dari depan, tampak seseorang mengenakan sarung. Tapi kalau dilihat dari belakang. Pahamlah kita bahwa itu sesungguhnya adalah celana. Model baru itu dinamai celarung.
Kalau kita perhatikan celarung mengajak kita untuk bersikap moderat. Berada ditengah-tengah. Tetapi kenyataannya, celarung tidaklah banyak diminati lantaran tak lazim sekali dimata. Orang yang terbiasa memakai sarung akan mengatakan kalau celarung itu tak elok. Sedangkan bagi pemakai celana, celarung hanya akan melahirkan kesan aneh pada dirinya. Pada masa sekarang, celarung tidak dapat menjadi penengah antara keduanya.
Singkatnya, didikan pesantren maupun kampus. Perlulah kalian paham mengenai adaptasi. Jangan samakan adaptasi dengan penyalahan ideologi. Juga jangan berpikir bahwa memakai pakaian tertentu hukumnya mutlak pada diri. Setiap kondisi memiliki situasi, dan setiap situasi harus dibarengi dengan adaptasi. Tidak perlu salah satu diantara keduanya mengotot dan menahbiskan diri. Selama pakaian itu menutup aurat sesuai dengan yang diajarkan agama kita. Rasanya kurang pantas kalau kita harus menafikannya.
Mudahnya, tidak mengenakan sarung ketika mau pergi ke tempat wisata pun ke tempat-tempat hiburan. Sebab itu akan merusak citra dari sarung. Jargon “Sesuaikan pakaian dengan tempatnya”. Kiranya perlu direnungkan dan diamalkan. Mengingat pakaian adalah hal pertama dan yang paling tampak di mata orang melihatnya.
Terlepas dari itu semua, pakaian yang paling netral rasa-rasanya tetap di punyai celana. Kita bisa saja pergi ke pesantren memakai celana atau pergi ke tempat peribadatan mengenakannya. Oleh karenanya, tidak bisa kita menyangkal celana sebagai pakaian yang lebih universal ketimbang sarung. [HW]