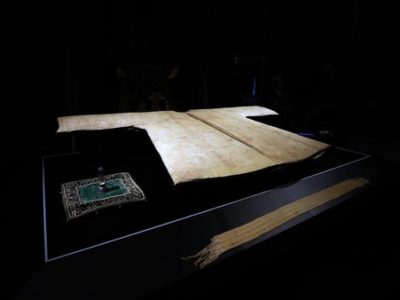Saya kok hampir tidak tertarik dengan kontroversi mengenai konten ceramah ustaz-ustaz di medsos. Pertama, karena memang tidak tertarik. Kedua, secara teknis komentar jelek pun di jagat internet merupakan poin bagi yang bersangkutan. Kita hidup di era “post truth”, bahwa yang diperhitungkan bukan sentimen positif atau negatif, tapi traffic atau lalu lintas data atau keriuhannya. Ketiga, respon negatif atau bahkan cacian yang salah sasaran bisa jadi malah menjadi sentimen positif buat yang bersangkutan. Masyarakat malah bertambah simpati.
Saya paham, banyak teman santri atau Nahdliyin gelisah dengan keberadaan para ustaz medsos. Sebagian ustaz/ustazah memang tidak mempunyai kualifikasi keilmuan yang layak untuk mengorbitkan diri menjadi mubalig. Sebagian lagi cukup mumpuni, mereka alumni Timur Tengah yang cukup paham bahasa Arab atau banyak membaca riwayat dalam kitab-kitab ulama namun mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda dengan kita. Saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang dua kategori ini, tapi poinnya yang mungkin membuat gelisah adalah mereka punya follower/jamaah yang cukup besar. Artinya pesan mereka sampai kepada umat; entah dilaksanakan atau sekedar didengarkan.
Bagaimana cara menyikapinya? Begini, sebagian ustaz medsos itu sudah lama menggunakan media elektronik dalam berdakwah. Ketika itu masih radio dan TV. Konten/karakter dakwah mereka yang tidak populis atau beda dengan kemauan masyarakat, mengharuskan mereka memilih berdakwah “dari atas”. Nah ketika teknologi komunikasi beralih ke internet, mereka lebih siap bermigrasi ke jaringan baru. Peralatan dan tim yang ada sudah sangat siap. Tinggal bergeser sedikit. Ini sama seperti media-media cetak mainstream yang lebih siap mengelola media online dari pada pendatang baru, karena mereka punya modal, peralatan dan SDM. Tinggal di upgrade sedikit ke media baru.
Jadi persoalannya sangat teknis, dan ini urusan duniawi: Bagaimana mengenali dan membuat perencanaan pasar/jamaah yang dibidik. Jangan bayangkan jamaah medsosiyah adalah orang-orang yang siap mendengarkan pengajian dengan baju koko atau mukena. Bisa jadi mereka mendengar pengajian sambil naik kereta, sambil iseng, atau sambil nonton drama Korea. Berikutnya adalah bagaimana peralatan dan SDMnya, sampai pada teknis yang lebih detail lagi mengelola emosi netizen melalui berbagai konten, kata-kata, bunyi-bunyian, penekanan-penekanan, bentakan-bentakan, olah visual, cara memotong dan mengedit dan seterusnya.
Lalu, juga bagaimana manajemen bisnisnya. Saya sangat suka dengan cara ustaz-ustaz medsos menggalang dana: Lewat donasi, lewat iklan produk-produk internal. Beberapa ustaz mengembangkan banyak unit usaha dan dia berceramah sekaligus sebagai bintang iklannya. Ini saya kira sah-sah saja. Nah para santri masih malu-malu dalam hal ini.
Berikutnya, tidak syak lagi, sebagian tim manajemen ustaz ini sudah berpengalaman sebagai konsultan atau buzzer politik. Ingat sepuluh tahun terakhir ini sebagian besar bahan politik adalah isu agama, dan para operatornya sebagian besar adalah orang yang itu-itu juga. Sebagian tim juga sudah berpengalaman bekerja dalam manajemen artis. Orang kampus menyebut ustaz medsos ini sebagai micro selebriti. Mikro ini menunjuk media baru yang digunakan berbasis internet.
Yang kedua, begini, para ustaz kondang medsos yang dijejer banyak sekali itu sebenarnya tidak satu kelompok. Faksinya banyak sekali dan memang beda manajemen, beda organisasi, beda paham keagamaan, beda patron politik dan seterusnya. Kesalahan kita kadang-kadang mengumpulkan mereka menjadi satu faksi kemudian semua dibawa ke ring untuk dihadapi sendirian, semua dianggap kompetitor, ya pasti kalah duluan. Dalam konteks fastabiqul khorot, berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam berdakwah, para ustaz santri atau timnya bisa bermitra dengan mereka. Contohnya sudah ada beberapa. Ada sindiran yang mungkin benar, para santri atau Nahdliyin lebih mudah bekerjasama dengan nonmuslim dari pada dengan kelompok Islam lain.
Maka sambil menata manajemen dakwah baru untuk masyarakat muslim baru (kata Alvara mereka adalah kaum milenial, muslim kota dan kelas menengah), yang bisa dilakukan adalah mendorong dan mengencangkan kembali kegiatan dakwah atau pengajian di lingkungan kita sendiri, entah dengan cara konvensional atau coba-coba cara baru lewat medsos. Ini penting, minimal agar jamaah besar (silent majority yang tidak terlalu berisik di medsos) tidak dicekoki dengan sajian-sajian ceramah atau pengajian instan.
Tidak perlu menurunkan standar, karena berapapun pasti ada peminatnya. Pengajian-pengajian kitab kuning online yang sangat serius disiarkan dari bilik-bilik pesantren pun punya pangsa pasarnya sendiri. Kira-kira kalau bicara pahala, keutamaan dakwah itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah jamaah tapi keikhlasan dan keistikamahan pendakwahnya atau timnya.
Dengan bahasa lain, merawat pasar lama itu sangat-sangat penting sambil terus melakukan proses ekspansi pasar. Maaf kalau saya menggunakan istilah pasar.
Dus, saya berbahagia sekali sekarang banyak santri atau alumni pesantren yang mulai tertarik dengan dunia dakwah. Selama ini, sebagian santri merantau ke kota, coba-coba aktif di dunia politik, atau mengincar pekerjaan-pekerjaan kerah putih, atau menggeluti dunia wiraswasta murni, menjadi orang umum yang melupakan kesalihan yang selama ini digeluti. Para pegiat sekolah-sekolah Islam juga anehnya bukan lulusan pesantren atau perguruan tinggi Islam. Kata Pak Hasyim Muzadi, sebagian besar santri yang merantau ke kota sudah “bosan salih”, sehingga panggung kesalihan ini diisi oleh orang lain.
Nah musim corona ini banyak santri yang coba-coba jadi mubalig. Sebagian pantas, sebagian harus diakui, tidak. Tapi di dunia medsos, bukankan yang tidak pantas tapi diputar berulang-ulang, lama-lama akan menjadi pantas? UAS atau Gus Baha yang penampilannnya biasa-biasa saja, berbeda dengan ustaz televisi pada umumnya, toh banyak juga yang suka karena mereka punya kelebihan dan berkarakter. Tentu tetap ada seleksi siapa yang layak tampil dan siapa yang men-support di luar panggung. Pahalanya sama. [HW]