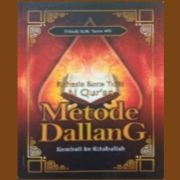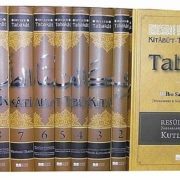Berbicara tentang sejarah santri berarti tidak terlepas dari perbincangan sejarah pendidikan Islam. Kontribusi dan dinamika pendidikan Islam menjadi mercusuar bagi pembangunan dan pengembangan terhadap pembentukan generasi muslim demi tegaknya nilai-nilai Islam yang berkonteks global. Pendidikan Islam yang bermula sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah di Makkah, tepatnya pada tahun 610 M, ketika wahyu pertama-Nya turun di Gua Hira.
Syahdan, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai ayat apa yang diturunkan pertama kali, ada suatu sisi yang menjelaskan bahwa Pendidikan Islam mulai dilaksanakan Rasulullah setelah mendapat perintah dari Allah agar beliau menyeru kepada Allah. Yaitu ayat yang termaktub dalam Al-Qur’an surat Al-Mudatsir ayat 1-7, pada ayat ini bahwa “bangun (menyeru)” sama dengan mengajak dan mengajak berarti mendidik.
Kemudian pendidikan ini dimulai di Mekkah, dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi di bawah bayang-bayang ancaman pembunuhan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya, salah satunya adalah rumah milik Al-Arqam bin Abil yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat pendidikan untuk para sahabat-sahabatnya.
Namun, setelah orang banyak memeluk agama Islam khususnya masyarakat Madinah yang merespon dan berkenan baik menerima ajaran Rasulullah akhirnya menjadi satu kesatuan sosial dan kekuatan politik tersendiri. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah di Madiah mendapat kedudukan sebagai kepala Negara.
Hal tersebut yang akhirnya berimpact besar untuk pendidikan Islam itu sendiri. Yakni Rasulullah yang dijadikan kepala negara oleh masyarakat Madinah dapat memberikan berbagai kebijakannya, terkhusus dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan masjid yang selanjutnya difungsikan sebagai sektor pusat kegiatan pendidikan. Nabi juga memfasilitasi tempat khusus seperti emperan masjid untuk digunakan para sahabat yang faqir yang kemudian menjadi tempat berteduh sekaligus tempat pendidikan berlangsung.
Orang-orang tersebut yang akhirnya dikenal dengan sebutan Ahlus Shuffah. Dalam Tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili misalnya, yang mendefinisikan Ahlus Shuffah sebagai “kaum faqir muhajirin dengan jumlah kisaran 400 lelaki, mereka tinggal di tsaqifah masjid (papan lebar yang dibuat rumah) dan pula mereka belajar Al-Qur’an di malam hari dan berjihad di siang hari”.
Tradisi-tradisi seperti ini yang kemudian berlanjut kepada sistem pendidikan santri yang notabenenya sebagai representasi muslim nusantara. Clifford Geertz adalah orang yang melakukan penelitian terkait kebudayaan Jawa, ia mengkategorisasi masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan; priyayi, santri, dan abangan. Dalam penelitiannya, golongan santri adalah tipe masyarakat yang dinilai taat dan bersungguh-sungguh dalam mendalami dan menjalankan ajaran agama serta mampu menguasai ilmu agama dengan baik.
Seperti halnya Ashabus Shuffah, Prototipe tentang penyelenggaraan pendidikan santri disampaikan oleh kyai dengan memberi bahan/materi secara berangsur-angsur dan juga selain mengacu pada ilmu dirayat tak luput menekankan ilmu riwayat.
Tradisi Ilmu Dirayat di kalangan santri direpresentasikan dalam ruang-ruang musyawarah diskusi, sedangkan tradisi Ilmu Riwayat dipraktekkan melalui metode talaqqi, yaitu berhadapan langsung dengan seorang guru. Santri yang hendak menginginkan ijazah sanad suatu fan ilmu, harus terlebih dahulu mampu untuk membaca, memahami, dan menguasai fan ilmu tersebut, tentu dengan pertimbangan guru layak atau tidaknya santri tersebut mendapatkan sanad.
Prestise bagi para santri senior adalah ketika mereka telah berhasil mendapatkan sanad kitab-kitab induk, seperti dalam fan Ilmu Tafsir dengan kitab yang dicari seperti Tafsir Baidhowi dan Tafsir Munir, fan Ilmu Hadits dengan kitab seperti Kutubussittah, Muwatho Imam Malik, fan Ilmu Tashawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin, dan seterusnya.
Sanad adalah suatu sistem yang mewujudkan akan keaslian suatu riwayat. Dengan sanad, maka suatu hadits bisa diklasifikasikan. Sanad bisa bernilai shohih manakala pemegangnya adalah seorang yang adil dan sempurna ke-dzabit-annya (akurat dari sisi pemahaman, baik pemahaman ingatan ataupun catatan), begitupun dengan Al-Qur’an yang bisa terjaga keotentikannya melalui metode ilmu riwayat ini.
Namun, seiring berkembangnya zaman, metode ini banyak dianggap kurang efektif, ribet, bahkan dianggap tidak penting. Banyak orang beranggapan untuk memahami agama cukuplah difahami sendiri tanpa harus dikaji di depan guru. Tak ayal lagi, orang merasa percaya diri untuk bebas berbicara tentang agama, akibatnya perspektif mengenai humand mind dipinggirkan dan sudah tidak lagi dipertimbangkan.
Selain itu, ada juga tradisi santri yang sama dengan tradisi ashabus shuffah, yaitu; mereka para santri yang sudah mumpuni dan dapat diandalkan dalam keilmuannya, maka seringkali ditugaskan oleh kyainya untuk melakukan perjalanan ilmiah ke pelosok Nusantara, guna mengajarkan kepada masyarakat dan meneruskan estafet kepemimpinan ulama dalam tradisi santri.
Maka bukan menjadi barang tabu, jika berdirinya pesantren-pesantren di Nusantara didirikan oleh orang-orang yang memiliki bekal yang kuat dalam ilmu agama dan mempunyai basic gemblengan ala pesantren hingga terbentuknya jiwa yang tulus dan tegar dalam menghidupkan warisan Rasulullah.
Namun, seiring dengan pergolakan zaman, tak ayal lagi, siapapun orangnya dan apapun latar belakangnya bisa saja membangun lembaga yang mereka klaim sebagai pesantren, sekalipun tanpa bekal agama yang dimiliki. Pemilik pesantren sudah tidak perlu lagi repot mendalami agama, karena melalui dana yang mereka miliki, bisa dengan mudah merekrut dan membayar dewan guru, ustadz, dan pengajar.
Sangat disayangkan memang, dari fenomena-fenomena semacam inilah yang akhirnya memunculkan kapitalisasi pesantren yang justru menjadi faktor merosotnya dunia pesantren dan mengikis keotentikan tradisi santri itu sendiri. []