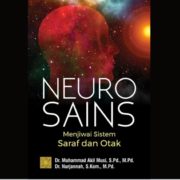Momen ujian yang diberikan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak kinasihnya, acap kali dikenang pada setiap perayaan Idul Adha tiba. Tidak ayal, sebab dari peristiwa itulah kemudian syariat ibadah kurban ditetapkan kepada kita hari ini. Memang demikian adanya, namun peristiwa sakral itu nyatanya tidak harus melulu dipandang dari segi pensyariatan ibadah tersebut. Itu memang tidak salah, hanya saja terdapat beberapa potret autentik dari kekasih Tuhan Ibrahim a.s. tersebut, yang perlu diulik dalam peristiwa yang masyhur itu. Tulisan ini akan mengurai satu di antara potret tersebut, yaitu potret komunikasi Ibrahim itu sendiri kepada anaknya.
Peristiwa luhur itu direportase Al-Qur’an dalam Q.S. Ash-Shaffat [37]: 102 berikut ini.
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ
Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”
Dari sajian ayat di atas, dapat lihat bagaimana cara Ibrahim memanggil anaknya. Itu tercitra dari fragmen ayat: yâ bunayya. Bentuk yang digunakan untuk menyebut sang anak pada penggalan ayat itu berupa isim mushaggar. Musthafâ Al-Ghulayainî, dalam Jâmiʻ Ad-Durûs Al-ʻArabiyyah menjelaskan bahwa bentuk tersebut memiliki beberapa faedah. Salah satu faedah tersebut adalah untuk menunjukkan cinta maupun kasih sayang. Dari penggunaan bentuk tersebut, jelas tercermin betapa Ibrahim amat menyayangi pun mengasihi anaknya itu.
Pada kelanjutan redaksi ayat itu, diinformasikan mengenai pengutaraan Ibrahim kepada anak yang dikasihinya. Pengutaraan tersebut perihal pengelihatan beliau yang menyembelih anaknya itu dalam mimpinya: innî arâ fî al-manâm annî adzbahuka. Ayat itu menggunakan kata arâ yang merupakan fi’il mudhâriʻ. Sekurang-kurangnya didapati dua penjelasan mengenai penggunaan bentuk tersebut.
Pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaylî dalam At-Tafsîr Al-Munîr: fî Al-Aqîdah wa Asy-Syarîʻah wa Al-Manhaj. Bahwa pengelihatan dalam mimpi tersebut terjadi berulang. Kedua, seperti halnya penjelasan M. Quraish Shihab, dalam Tafsîr Al-Mishbâh bahwa seolah masih terlihat oleh Ibrahim apa yang dilihat beliau dalam mimpinya itu tatkala beliau mengutarakannya kepada anaknya. Penggalan ayat tersebut juga sekaligus memperlihatkan bagaimana Ibrahim terbuka kepada anaknya. Beliau menyampaikan akan apa yang dialaminya.
Ayat itu berlanjut, dan mengeksplisitkan tujuan Ibrahim dalam pengutaraan pengelihatan dalam mimpinya kepada anaknya itu. Itu terindikasi dari penggalan redaksi: fanzhur mâdzâ tarâ. Ibrahim menanyakan pendapat sang anak, mengenai pengelihatan beliau dalam mimpinya. Terdapat beberapa penafsiran mengenai tujuan Ibrahim di sini. Pertama, dalam Tafsîr Al-Jalâlayn, Jalâluddîn Al-Mahallî dan Jalâludîn As-Suyûthî menjelaskan bahwa itu dilakukan Ibrahim agar anaknya itu mengikuti, menurut untuk disembelih.
Kedua, menurut Ibn Katsîr dalam Tafsîr Al-Qur’ân Al-ʻAzhîm, dilakukannya hal itu oleh Ibrahim di antaranya untuk menguji kesabaran maupun keteguhan sang anak, serta mengetahui sejauh mana tekadnya untuk taat kepada Allah swt. dan menaati ayahnya. Ketiga, M. Quraish Shihab berpendapat dalam Tafsîr Al-Mishbâh, bahwa itu dilakukan Ibrahim di satu sisi menghendaki untuk melaksanakan titah sebagaimana mimpi yang beliau alami, namun di sisi lain beliau memahami bahwa titah itu tidak harus dipaksakan kepada sang anak. Bila nyatanya sang anak tidak menuruti, itu merupakan urusannya dengan Allah.
Di sini terlihat bagaimana Ibrahim tidak lantas lalu mengambil keputusannya sendiri, bahkan dari pendapat Quraish Shihab terlihat sisi seperti apa komunikasi yang Ibrahim lakukan dalam rangka membangun hubungan dengan anak yang dikasihinya itu.
Komunikasi Intersubjektif Ibrahim yang Menuansakan Keterbukaan Hubungan
Sekarang mari tilik komunikasi Ibrahim pada ayat tersebut. Tulisan ini mengatakan bahwa komunikasi yang diterapkan Ibrahim merupakan komunikasi intersubjektif. Istilah itu meminjam istilah Jürgen Habermas, seorang pemikir Jerman dari kalangan Mazhab Frankfurt generasi kedua. Pada bahasan Reza A. A. Wattimena dalam Memaknai Digitalitas: Sebuah Filsafat Dunia Digital, dijelaskan bagaimana komunikasi intersubjektif ini mempunyai kondisi di mana adanya keterbukaan, keegaliteran, serta bebas dari dominasi, yang dengan itu dapat tercapailah kesepakatan antar sesama yang masuk akal untuk semua, kesepakatan yang juga adalah kesepakatan disepakati pihak-pihak yang secara implikatif berkenaan dengan kesepakatan tersebut.
Artinya, pada komunikasi intersubjektif ini individu-individu yang terlibat dipandang sama-sama sebagai subjek. Tidak ada satu pihak pun yang diobjektivikasi dalam komunikasi semacam ini. Sebab pihak-pihak sama kedudukannya sebagai subjek, kesepakatan yang lahir adalah kesepakatan dari pemahaman intersubjektif pihak-pihak yang terlibat itu sendiri.
Dari penjelasan sebelumnya, setidaknya didapati beberapa isyarat elementer komunikasi Ibrahim. Pertama, bahwa Ibrahim memulai percakapan dengan anaknya dengan ungkapan kasih. Kedua, Ibrahim mengutarakan kepada sang anak mengenai apa yang dilihat beliau dalam mimpi. Pendapat Quraish Shihab mengenai penggunaan fi’il mudhâriʻ pada potongan redaksi yang membincang hal ini, di mana seolah masih terlihat oleh Ibrahim apa yang beliau lihat dalam mimpinya tatkala kala beliau mengutarakan itu kepada anaknya, mengindikasikan bahwa Ibrahim menyampaikan ihwal itu dengan sebagaimana adanya. Artinya, apa yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anaknya merupakan apa yang sebenar-benarnya beliau lihat dalam mimpinya. Ini mengisyaratkan keterbukaan secara total Ibrahim dalam pengutaraan itu.
Ketiga, Ibrahim tidak hanya terbuka dengan pengutaraan itu kepada anaknya, namun beliau juga membangun keterbukaan dalam komunikasinya, beliau meminta sang anak untuk berpendapat mengenai pengutaraan mimpi itu. Di sini terlihat bahwa Ibrahim memposisikan sang anak sebagai subjek. Tidak ada dominasi Ibrahim atas anak yang dicintainya itu. Kepada anaknya itu, Ibrahim menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan pun persamaan. Dengan pola demikian, seperti halnya pada ayat tersebut, Ibrahim mendapatkan respons yang adiluhung dari sang anak. Dari ayat tersebut dan dari ayat sekanjutnya: Q.S. Ash-Shaffat [37]: 103, terlihat pula suatu kesepakatan yang intersubjektif, kesepakatan yang lahir keduanya. Di mana keduanya melaksanakan perintah Allah.
Bisa diperhatikan bagaimana sistematika komunikasi itu terjadi. Di mana dalam komunikasi tersebut, bukan hanya satu subjek yakni Ibrahim, yang dengan otoritasnya kemudian memaksakan anaknya sebagai subjek yang lain, untuk turut pada kehendak pribadinya. Namun Ibrahim dengan pemahaman beliau yang purna, justru menjadikan diri beliau dan anaknya dalam posisi yang sama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, hingga pada akhirnya lahir suatu kesepakatan dari keduanya. Tidak lupa juga dalam mencapai kesepakatan itu, Ibrahim terbuka dengan apa yang beliau alami, serta menstimulasi keterbukaan itu pula dari sang anak, dengan menanyakan pendapat sang anak mengenai mimpi yang diutarakannya.
Cara komunikasi Ibrahim ini, bisa dijadikan teladan bagi orang tua dalam menjalin hubungan bersama anak. Dengan tidak mendominasi mereka, meposisikan diri anak sebagai subjek yang berhak turut dalam suatu keputusan. Terbuka terhadap mereka, dan menstimulasi pendapat dan menerima keterbukaan mereka. Dengan cara ini, keputusan-keputusan yang lahir adalah keputusan berdasarkan kesepakatan intersubjektif orang tua dan anak. Dengan komunikasi ini pun, mengalir keterbukaan dalam hubungan yang terjalin tersebut.