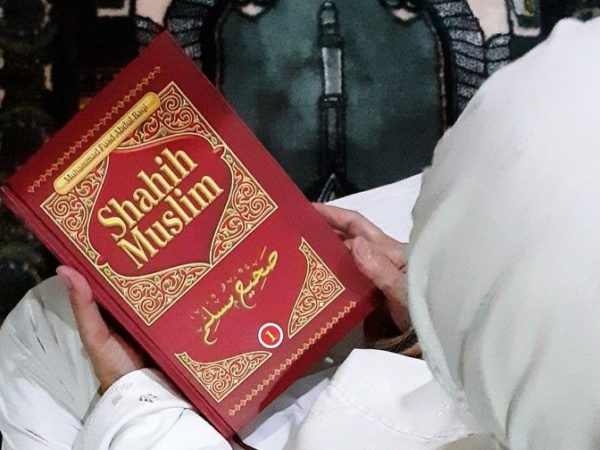Dalam salah satu “Tetralogi Pulau Buru”, Bumi Manusia, sastrawan Pramoedya Ananta Toer memusatkan perhatiannya pada kesewenang-wenangan industri gula terhadap masyarakat Jawa. Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo, yang menjadi latar penceritaan Pram, adalah tempat pertarungan kelas, diskriminasi, kesewenang-wenangan, penindasan buruh, dan relasi jender yang timpang. Nyai Ontosoroh, salah satu magnet novel ini, adalah anak seorang juru tulis di pabrik gula Toelangan, Sidoarjo, yang hidup di akhir abad 19. Oleh orangtuanya, dia dijual sebagai gundik bagi bule Belanda pemilik pabrik gula. Perjuangan Nyai Ontosoroh dalam melakukan perlawanan dengan cara khas inilah yang mengesankan banyak pembaca.
Melalui penokohan Nyai Ontosoroh dan latarbelakang kehidupan para buruh pabrik gula dan kehidupan sosial di akhir abad 19 hingga tiba era politik etis, Pram menggelar “pertunjukan kata-kata” melalui novelnya. Menjadi pertanyaan penting manakala melihat alasan mengapa Pram mengambil Pabrik Gula sebagai titik pijak penggambaran zaman. Penulis menduga, Pram sengaja melakukannya, karena dengan jumlah ratusan di sekujur pulau Jawa, pabrik gula menjadi salah satu penanda eksporasi besar-besaran tanah Jawa untuk kebutuhan industri gula kaum kolonial, sekaligus menggambarkan eksploitasi mengerikan atas para petani tebu dan buruh pabrik.
Dalam konteks sejarah pendidikan Islam di Indonesia, rasanya mustahil mengabaikan sejarah pendirian pesantren di berbagai daerah. Dalam hal ini, menarik apabila kita telusuri satu persatu beberapa pesantren besar yang berdiri di akhir abad XIX maupun awal abad XX. Faktanya, ada banyak pesantren yang secara geografis lokasinya berdekatan dengan pabrik gula. Hubungan keduanya juga unik, kadang antagonistik, harmonis, kadang pula simbiotik. Namun pasang surut hubungan antara lembaga pendidikan dengan lembaga industri, baik secara struktural maupun kultural-politis, membuktikan apabila pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan sekaligus lembaga budaya yang memiliki elastisitas sosial dan daya tahan kultural yang luar biasa. Hal ini terbukti, beberapa pabrik gula sudah tidak lagi berproduksi, karena berbagai alasan dan tantangan, namun pesantren yang berada di sampingnya tetap bertahan, bahkan berkembang pesat.
Pesantren yang berdampingan dengan pabrik gula yang paling mencolok tentu saja Ponpes Tebuireng yang berseberangan dengan Pabrik Gula Tjoekir. Ketika pabrik gula ini didirikan pada tahun 1853 lalu berkembang lebih pesat pada 1884 ketika dikelola oleh NV Kooy dan Coster Van Voorhout, wilayah di sekitarnya lambat laun berkembang menjadi komunitas perambah yang antara lain menjadi sentra kehidupan buruh yang kelam. Pabrik Gula Tjoekir menjadi mesin industri paling terkemuka dan termodern di zamannya.[1] Keberadaannya menjadi ironi. Di satu sisi memakmurkan pemodal kolonial, namun di sisi lainnya menjadikan rakyat sebagai obyek eksploitasi besra-besaran. Dari sisi nama saja, “Tebu Ireng”, menunjukkan antara lain pengaruh industrialisasi melalui perkebunan tebu. Nama Tebu Ireng kemudian digabung menjadi Tebuireng, tanpa spasi. Dalam terminologi ilmu nahwu, penggabungan dua nama menjadi satu seperti itu disebut sebagai Murakkab Majzi.
Hari ini, 122 tahun silam, bertepatan dengan 3 Agustus 1899/ 26 Rabiul Awal 1317 H, KH. M. Hasyim Asy’ari mendirikan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu dengan ukuran 6 x 8 meter. Bangunan sederhana ini disekat menjadi dua. Bagian belakang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan bagian depan digunakan sebagai langgar alias musalla. Saat itu santrinya hanya 8 orang. Tiga bulan kemudian santrinya menjadi 28 orang. Kehadiran Kiai Hasyim di perkampungan perambah ini tentu saja mendapatkan pertentangan. Fitnah datang bertubi-tubi. Bahkan para santrti memilih tidur bergerombol di tengah langgar, takut tusukan beda tajam yang seringkali diarahkan ke dinding gedhek. Di luar, Kiai Hasyim juga mendapatkan intimidasi agar menghentikan dakwahnya. Bahkan para santri juga mendapatkan ancaman agar meninggalkan Kiai Hasyim. Melihat gangguan yang semakin kuat, Kiai Hasyim akhirnya meminta bantuan dari para sahabatnya yang berasal dari Banten, antara lain Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Panguragan, Kiai Sansuri Wanantara, dan Kiai Abbas Abdul Jamil Buntet, Cirebon. Mereka diundang secara khusus untuk melatih para santri pencak silat, sehingga kemampuan beladiri ini membuat para santri semakin percaya diri untuk melindungi dirinya maupun gurunya.
Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, langgar sederhana ini berkembang menjadi pondok pesantren dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kharisma dan keilmuan Kiai Hasyim semakin diakui. Kampung yang dihuni komunitas perambah buruh tebu ini berubah lebih agamis berkat sentuhan dakwah tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Kiai Hasyim. Bahkan, ketika salah satu anak dari pimpinan PG Tjoekir yang berkebangsaan Belanda menderita sakit parah dan dalam kondisi kritis, dia akhirnya sembuh berkat air doa (suwuk) dari Kiai Hasyim.[2]
Hasyim Asy’ari, Jaringan Santrinya, dan Pemukiman Perambah
Yang menarik adalah, jaringan para santri Kiai Hasyim Asyari di kemudian hari juga mendirikan pesantren yang lokasinya tidak jauh dari pabrik gula. Seolah terdapat pola unik apabila sasaran dakwah yang paling urgen adalah kawasan loji, pemukiman buruh pabrik, para petani tebu, dan komunitas perambah. Hal ini bisa dilacak dari setidaknya beberapa pesantren, antara lain, saat KH. Abdul Karim (Mbah Manab) mendirikan Ponpes Lirboyo pada 1910 yang keberadaannya tidak jauh dari PG Pesantren Baru. Lirboyo melakukan perlawanan kultural dan spiritual terhadap budaya perambah PG Pesantren Baru yang didirikan oleh NV Javasche Cultuur Mij dua tahun setelah Lirboyo berdiri. Meskipun polanya terbalik, Lirboyo dulu (1910) baru kemudian PG Pesantren Baru berdiri (1912), namun secara embrio, terdapat pabrik gula kuno sebelum NV Javasche Cultuur Mij membangun pabrik yang lebih besar. Nama PG Pesantren Baru sendiri dinisbatkan pada lokasi wilayah, yaitu daerah (Kecamatan) “Pesantren”. Dari sisi nama, jelas ada keterkaitan antara kaum “santri” yang bermukim di situ, yang kemudian berkembang menjadi nama wilayah. Perlawanan kultural di bidang edukasi keagamaan yang dilakukan Lirboyo ini kemudian dibantu oleh Ponpes al-Falah, Ploso, yang didirikan pada tahun 1925 oleh alumni Tebuireng lainnya, KH. Djazuli Utsman. Di sekitar PG Mritjan, Kec. Mojoroto, Kediri, yang dibangun oleh Nationale Industrie en Landbouw Mij NV pada 1903, ada beberapa pesantren yang menyangga keilmuan agama. Di antara yang bertahan adalah PP. Al-Hasyimi.
Baik Lirboyo maupun Ploso membentuk front perlawanan secara cerdas dengan mendampingi dan mendidik para santri yang merupakan anak-anak dari kaum buruh pabrik gula maupun para petani tebu, dan kaum marginal lainnya. Sepola dengan Tebuireng, Lirboyo dan Ploso, salah satu santri Kiai Hasyim lainnya, KH. Bisri Syansuri, juga mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Maarif, pada 1917, di Denanyar. Uniknya, lokasi pesantren ini juga tidak jauh dari Pabrik Gula Djombang Baru, yang didirikan pada tahun 1895 oleh Anemaat & Co (yang kemudian diambil alih oleh NV Perusahaan Perkebunan Djombang Baru pada tahun 1957). Keberadaan Denanyar ini juga ditopang oleh PP. Bahrul Ulum Tambakberas, yang meskipun lebih tua dibandingkan dengan usia PG Djombang Baru, namun tetap memiliki kontribusi berarti dalam dakwah di masyarakat yang terdampak industrialisasi.
Sedangkan di Tulungagung ada Pabrik Gula Modjopanggung yang secara geografis dekat dengan Pondok Menara Al Fattah Mangunsari Kedungwaru. Pesantren ini didirikan oleh KHR. Abdul Fattah pada tahun 1935. Sedangkan PG Modjopanggung didirikan pada 1852, ketika era tanam paksa berlangsung. Dari sisi sanad keilmuan, KHR. Abdul Fattah belajar hadits kepada KH. Hasyim Asyari.
Jaringan santri KH. Hasyim Asy’ari lainnya, KH. Zaini Mun’im mendirikan Pesantren Nurul Jadid tidak jauh dari lokasi PG Paiton. Pabrik gula ini sudah hancur. Namun apabila dilihat berdasarkan peta, keberadaan PP. Nurul Jadid menjadi penopang dakwah agama bagi masyarakat saat hingga kini. Bahkan keberadaan beberapa pabrik gula di Pobolinggo juga membuat beberapa investor Belanda tertarik menanamkan modalnya untuk membuat rel kereta api yang membujur dari Probolinggo kota hingga ke Paiton. Keberadaan rel kereta api di Probolinggo ini yang juga tercatat sebagai salah satu jalur tertua di Jawa. Jalur dari Probolinggo ini bersambung dengan jalur kereta api di Pasuruan, yang juga menjadi urat nadi industri gula yang berporos di PG Kedawoeng, salah satu pabrik gula dengan kualitas produk ekspor. Selanjutnya Pasuruan yang juga menjadi terkenal karena menjadi stasiun percobaan gula sedangkan Probolinggo menjadi sentra distribusi dan pengapalan produk-produk untuk gula, tembakau dan beras.[3]
Dalam satu rangkaian dengan PP. Nurul Jadid di Paiton Probolinggo, ada pesantren yang lebih tua, PP. Zainul Hasan, Genggong. Lokasinya juga tidak jauh dari PG Padjarakan. Pondok Pesantren yang saat ini diasuh oleh KH. Mutawakkil Alallah ini merupakan pesantren kuno yang didirikan oleh Syekh Zainul Abidin pada tahun 1839. Pendirian pesantren ini juga berada dalam jarak yang tidak jauh dari Pabrik Gula Padjarakan yang berdiri sejak 1832. Penulis menduga, kedatangan Syekh Zainul Abidin yang berasal dari Maroko, Afrika Utara, dan sebelumnya mondok di Sidoresmo, Surabaya, antara lain menyasar perkampungan yang menjadi penyangga industri gula di kawasan ini. Setelah pemerintah Belanda memberikan keleluasaan bagi pihak swasta untuk terlibat masuk dalam industri yang menguntungkan ini, maka perusahaan Anamaet & Co masuk menjadi pengelola swasta pasca liberalisasi industri, 1870. Sampai saat ini, ketika produksi PG Padjarakan mulai menurun setelah beroperasi lebih dari 150 tahun, maka PP. Zainul Hasan semakin berkembang dengan berbagai unitnya dan ditopang keberadaan 20.000 santri.
Di wilayah timur Probolinggo, tepatnya di Kabupaten Situbondo, KH. As’ad Syamsul Arifin, salah seorang santri KH. Hasyim Asy’ari yang lain, juga mengembangkan pesantren yang dirintis oleh ayahnya, KH. Syamsul Arifin. Sungguh bukan merupakan kebetulan apabila keberadaan PP. Salafiyah Syafi’iyah ini juga berdekatan dengan Pabrik Gula Asembagus, Situbondo, yang didirikan pada tahun 1891. PG Asembagus ini adalah salah satu mesin industri gula di wilayah timur selain PG Olean, PG Pandji, dan PG Wringin Anom.
Di Jember, salah satu santri KH. Hasyim Asy’ari yang berasal dari Rembang, KH. Djauhari Zawawi, merintis pendirian PP. Assunniyah pada tahun 1942. Lokasi pesantren ini sangat dekat dengan Pabrik Gula Gunungsari, Kecamatan Kencong. Pasca industrialisasi besar-besaran di pedalaman timur, ada sedikitnya empat pabrik gula yang didirikan oleh Belanda di daerah Jember, antara lain PG Semboro, PG Bedadung, PG Jatiroto (sekarang masuk wilayah Lumajang), dan PG Gunungsari di Kencong. Kiai Djauhari merintis pengajian di lokasi yang berdempetan dengan perumahan pegawai Pabrik Gula Gunungsari. Setelah dinasionalisasi pada 1957, pabrik gula ini masih beroperasi untuk beberapa saat sebelum kemudian tutup. Sedangkan PP. Assunniyah semakin berkembang hingga saat ini.
Di Banyuwangi, ada seorang ulama NU yang juga santri Kiai Kholil Bangkalan. Namanya Kiai Soleh, Lateng, Banyuwangi. Lahir pada 1862, Kiai Soleh nyantri kepada Kiai Kholil Bangkalan sebelum melanjutkan pendidikannya di Haramain. Setelah kembali ke tanah air, dia bergabung dengan Sarekat Islam. Ketika KH. Hasyim Asy’ari mendirikan NU, Kiai Soleh memilih bergabung dengan organisasi baru ini bahkan menyatakan kesediaannya sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-IX tahun 1934.[4] Sahabat Kiai Hasyim Asy’ari ini juga merintis dakwah di kawasan hitam yang merupakan basis buruh dan kaum petani tebu tak jauh dari Pabrik Gula Sukowidi yang berdiri pada 1895. Selain Kiai Soleh, ada pula pondok pesantren yang dirintis oleh KH. Abdullah Faqih di Cemoro, Balak, Rogojampi, pada tahun 1911. Sedangkan Kiai Hasyim mendirikan pesantren yang tak jauh dari Cemoro. Kedua kiai ini memilih berdakwah di kawasan yang tak jauh dari Pabrik Gula Rogodjampi, yang berdiri sejak 1893.
Di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat, pertumbuhan industri gula tidak segencar di Jawa Timur. Sebab, selain cuaca dan kontur tanah, hal ini juga dipengaruhi oleh daya serap dan daya tahan perusahaan dalam melakukan pola ekspor ke luar negeri. Meskipun tidak sebanyak di Jawa Timur, namun tetap saja keberadaan pondok pesantren menyisakan pola yang hampir sama dengan wilayah timur, yaitu lokasinya tidak jauh dari pabrik gula. Hal ini, misalnya, ditunjukkan oleh KH. Munawwir yang merintis pendidikan agama Islam di Krapyak, yang lokasinya juga tidak jauh dari Pabrik Gula Madukismo milik Keraton Yogyakarta.
Di Jawa Tengah, khususnya di Kendal, ada PP. Asrama Pelajar Islam Kauman (APIK) Kaliwungu Kendal, yang berdiri pada tahun 1919, berdekatan dengan PG Kaliwungu yang saat ini hanya menyisakan puing-puing. PG Kaliwungu didirikan oleh NV Cultuuronderneming Kaliwungi Plantaran.[5] Akibat pendudukan Jepang, banyak pabrik gula di Kendal yang tutup, antara lain PG Gemuh, PG Puguh, dan PG Kaliwungu. Sedangkan yang masih beroperasi hingga 1997 hanyalah PG Cepiring. Menurut cerita tutur, di sekitar pondok dulu banyak tanaman tebu yang dipelihara untuk kebutuhan suplai ke PG Kaliwungu maupun PG Cepiring. Di titik-titik ini terdapat perkampungan yang juga masuk dalam binaan pesantren APIK. Di Jawa Barat, Ponpes Buntet lokasinya tidak jauh dari PG Sendanglaut.
Mengapa Harus Mendampingi Buruh Pabrik Gula?
Bagi pemerintah Hindia Belanda, jelas, industri gula menjadi sumber pemasukan yang vital sehingga pabrik gula diberi perlindungan dan bantuan politik secara maksimal. Sejak diberlakukannnya sistem tanam paksa, sumbangan perkebunan tebu terhadap penghasilan pemerintah pusat memang tinggi.[6] Di zaman keemasan industri gula, 1900-1930, terdapat 179 pabrik gula yang menguasai 196.592 hektar lahan tebu dengan rata-rata 14,8 ton/ hektar. Dengan ekspor 3 juta ton gula, Hindia Belanda menjadi produsen gula terbesar kedua setelah Kuba. Hanya saja, ketika kemerosotan ekonomi terjadi pada 1930, dalam waktu empat tahun jumlah pabrik gula di Hindia Belanda yang berjuumlah 179 pabrik menyusut hingga 54 saja yang aktif berproduksi.[7]
Gurita industri gula ini bisa bertahan lebih dari satu abad karena ditunjang struktur dan sistem yang menempatkan para pejabat Belanda di level puncak dan kaum pribumi di strutur bawah, berikut berbagai peraturan yang memperkokoh cengkeraman kolonialisasi gaya baru tersebut. Struktur pabrik gula yang berkuasa hampir satu abad ini terdiri dari administrator yang berada di posisi puncak.[8] Mereka memiliki akses langsung ke pemerintah pusat di Batavia. Bahkan pejabat pabrik gula ini menikmati kekuasaan politik yang tidak bisa diintervensi oleh penguasa lokal (pejabat daerah). Di bawahnya terdapat tiga kepala bagian yaitu, pertama, kepala kebun yang bertanggungjawab atas lahan tebu dan kebun secara umum. Kedua, kepala pabrik, yang bertugas menjalankan pabrik, serta ketiga, book houder alias pemegang buku yang bertanggungjawab atas urusan pembukuan keuangan dan administrasi pabrik. Tiga level puncak ini dijabat boleh orang Belanda. Di bawahnya lagi ada beberapa kepala seksi yang berfungsi sebagai staf, yang juga terdiri dari bule Belanda.
Setelah itu, staf dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama disebut sebagai pegawai satu (pegawai Kelas I), seluruhnya berjumlah 500-100 orang. Baik administrator dan wakilnya beserta para staf ini tinggal di kompleks pemukiman yang tertutup, dijaga ketat, terpisah, eksklusif dan terasing dari lingkungan sekitarnya. Sebagian besar juga merupakan Belanda totok, hanya sebagian kecil orang Jawa. Pemukiman ini disebut loji. Loji dikelilingi oleh pemukiman para pegawai dua (Pegawai Kelas II), meskipun sebagian juga tidak kebagian perumahan. Yang paling merana adalah kelompok ketiga, yaitu buruh yang berkeahlian maupun tidak memiliki keahlian yang layak. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu orang. Mereka bahkan terbagi lagi menjadi dua kelompok: kelompok yang bekerja secara permanen sepanjang tahun (pegawai tetap dan pegawai harian), dan golongan yang bekerja hanya pada saat musim giling tiba. Golongan terakhir ini dinamakan “buruh kampanye”. Mereka hanya melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian seperti memanen tebu, mengangkut tebu hingga ke pabrik, dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan proses pembuatan gula selama musim giling.
Ketika musim giling tiba, jumlah kelompok buruh kampanye ini meningkat. Mereka datang dari berbagai daerah. Meskipun mereka bekerja lebih keras dan berat—memotong dan mengangkut tebu ke lori—namun upahnya relatif sedikit. Kedatangan mereka juga diiringi kelompok lain, yaitu para pedagang makanan, penjual rokok, penyedia jasa, penghibur, hingga para bandar judi. Kelompok kedua (pegawai Kelas II) yang tidak memiliki mobilitas social vertical, pada akhirnya lebih dekat dengan pegawai kelas III dan para buruh kampanye ini. Dengan demikian, terjadi kontradiksi dan diskriminasi di sini. Di satu pihak, penghuni loji mendapatkan layanan berkelas dan eksklusif, di pihak lain ada puluhan ribu buruh rendahan yang hidup dalam kondisi menyedihkan.
Struktur yang menindas, perlakuan yang diskriminatif, ketidakpastian ekonomi uang (cash economy) dan kerentanan buruh terhadap fluktuasi harga komoditi dunia berperan pada terbentuknya gaya hidup yang khas dan keras di kalangan buruh yang tidak memiliki keahlian memadai. Gaya hidup ini umumnya bersifat sekuler, terfokus pada kebutuhan hari ini ketimbang hari esok. Rejeki yang didapat langsung dihabiskan di meja judi, untuk hiburan, prostitusi, maupun kebutuhan hedonistik lainnya.
Pada akhirnya, para buruh ini membentuk komunitas perambah yang dibangun berdasarkan kohesi sosial yang longgar. Dengan kata lain, mereka hidup terpisah dari lingkungan sekitarnya. Parade komunitas ini biasanya berlangsung seiring dengan berlangsungnya musim giling pabrik gula. Mereka berpesta dengan menggelar “ritual sekuler” seperti pertunjukan ludruk, perjudian, menenggak minuman keras, hingga tari erotis, dan prostitusi.[9]
Meskipun juragan pabrik tebu kaya raya, namun tidak dengan para petani dan buruh pabrik. Dengan kondisi lahan pertanian yang menyempit dan didominasi tebu di areal persawahan mereka, maka kondisi kesejahteraan jauh dari kata layak. Demikian juga dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang minim. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyakit sosial seperti pencurian, perampokan, candu, dan prostitusi. Gaji buruh yang tidak seberapa, maupun penghasilan panen yang jauh dari kata cukup banyak dihabiskan di meja judi.
Hal ini selaras dengan penelitian Clifford Geertz yang menilai apabila dampak yang paling menonjol dari perkebunan tebu di Jawa sejak Tanam Paksa hingga pertengahan abad XX adalah terjadinya proses involusi pertanian (agricultiural involution) dan kemiskinan bersama (shared poverty). Terjadinya involusi karena tanaman tebu dan padi tumbuh dalam rotasi pada sawah yang sama. Jika basis ekonomi desa tradisional masih utuh, maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, di satu sisi terjadi perkembangan cepat dalam perkebunan tebu yang menguntungkan secara ekonomi bagi pemerintah colonial dan pemodal asing, di lain pihak terjadi kemerosotan ekonomi agraria penduduk bumiputra. Hal ini didukung dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat serta tidak diimbangi dengan penambahan luas lahan sawah. Dalam kondisi seperti ini masyarakat Jawa di pedesaan mengalami perkembangan ekonomi yang statis atau involusi.[10]
Selain degradasi moral, buruknya edukasi, robohnya norma dan pranata sosial serta minimnya nilai spiritual, ditambah dengan involusi ekonomi yang terjadi di berbagai berbagai daerah, membuat para ulama memilih merapat dan memberikan pencerahan di kantong-kantong pemukim yang berisi para buruh kelas tiga maupun buruh kampanye ini. Mereka merintis langgar yang dijadikan sebagai pusat pengajaran, kemudian diikuti dengan pendirian kamar-kamar yang disediakan bagi para santri. Mereka mendidik penduduk dengan ilmu agama, memberikan pencerahan, dan menjadi oase di antara kegersangan spiritual.
Berdirinya pabrik gula secara positif menyediakan lapangan kerja bagi kaum pribumi, namun ekses negatifnya lebih banyak. Selain eksploitasi besar-besaran atas tanah dan tenaga kerja di Jawa, masalah lain juga tak kalah penting. Kantong pemukiman kaum buruh rendahan yang menderita, masyarakat lebih banyak menggunakan upahnya untuk aktivitas konsumtif-hedonis, serta gaya hidup yang tidak teratur.
Dalam sistem kapitalisme, buruh memang menjadi pihak yang dieksploitasi. Mereka diperas tenaganya untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai nilai lebih (surplus value). Akan tetapi nilai lebih ini tidak kembali kepada buruh, melainkan kembali pada pihak pengusaha (kaum kapitalis). Dalam hal ini, buruh hanya menerima upah tertentu dari majikannya, dan upah tersebut sama sekali tidak merepresentasikan pembagian keuntungan dari nilai lebih yang dipeoleh oleh pihak perusahaan.[11]
Meskipun pernah menjadi komoditas andalan dan menjadi salah satu raksasa industri kolonial, namun pasca krisis tahun 1930, nuansa kehancuran pabrik gula mulai kelihatan. Keruntuhan ini semakin terlihat pada saat Jepang datang, 1942. Lahan perkebunan tebu banyak dialihfungsikan menanam pohon jarak yang dianggap lebih berguna untuk diolah menjadi bahan bakar mesin pesawat terbang, dan pabrik gula banyak dialihfungsikan sebagai gudang mesiu dan logistik. Ketika Jepang hengkang, lalu Sekutu datang, maka beberapa pabrik gula yang tersisa sengaja dibumihanguskan oleh gerilyawan republik. Tujuannya agar tidak diambil alih kembali oleh Belanda yang membonceng Sekutu. Hal ini misalnya menimpa Pabrik Gula Gending Probolinggo. Para gerilyawan juga membakar tanaman tebu yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam perjalanan zaman, banyak pabrik gula yang berguguran dengan berbagai problematikanya masing-masing, antara lain:
Pertama, pendudukan tentara Jepang. Kedua, aksi pembakaran yang dilakukan oleh gerilyawan republik. Ketiga, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah pada 1957 yang ternyata tidak diikuti oleh penyediaan sumberdaya manusia yang baik. Keempat, manajemen dan tata kelola yang buruk. Kelima, penyakit tebu, harga sewa tanah yang mahal, patokan harga gula yang tidak sebanding dengan modal, alih fungsi lahan, dan sebagainya.
Meskipun banyak pabrik gula gulung tikar dan hanya menyisakan beberapa saja, namun keberadaan pesantren yang mengiringinya tetap bertahan dengan berbagai dinamikanya. Tebuireng, Denanyar, Lirboyo, Ploso, Genggong, Paiton, Sukorejo-Asembagus dan lain sebagainya malah semakin berkembang dengan jumlah santrinya yang jika ditotal mencapai ratusan ribu. Hal ini membuktikan apabila konsistensi, sikap menghadapi perubahan zaman, dan metodologi bertransformasi secara jelas turut membuat pesantren bertahan hingga kini. Wallahu A’lam Bisshawab. []
[1] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 171.
[2] Mubarok Yasin, dkk., Profil Pesantren Tebuireng (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 5-6.
[3] Achmad Taufik, “Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (1830-2010)”, Penelitian di Universitas Negeri Malang, 2010.
[4] Zainul Milal Bizawie, Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945) (Jakarta: Pustaka Compass, 2016), 76.
[5] Lina Farida, “Pabrik Gula Cepiring Kendal Pasca Nasionalisasi, 1957-2008”, dalam Journal of Indonesian History, Vo. 3, tahun 2014 hlm. 34-41.
[6] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), 107-117.
[7] Hiroyosi Kano, Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20 (Yogyakarta: Akatiga & UGM Press, 1996), 49.
[8] Sebutan administrator ini kemudian disebut sebagai direktur setelah nasionalisasi pabrik gula pada 1957.
[9] Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966) (Jakarta: Pensil 234, 2011), 118.
[10] Clifford Geertz, Agricultural Involution, The Process of Ecological Change in Indonesia (Berkeley: University of California Press, 1963), hlm. 38 dan 74-75, sebagaimana dikutip oleh Wasino, Kapitalisme Bumi Putra, 4. Berbeda dengan penilaian Geertz soal involusi di atas, Hiroyosi Kano dkk., menilai apabila masyarakat desa di sekitar pabrik gula tidak mengalami involusi, melainkan diferensiasi. Kepemilikan tanah pedesaan tidak merata, tetapi terjadi kesenjangan antara petani pemilik tanah luas dengan pemilik tanah sempit dan mereka yang tak bertanah. Penduduk desa tidak semata-mata menggantungkan mata pencahariannya pada pertanian saja, tetapi dari berbagai sektor di luar pertanian, seperti kerajinan, tambak, dan perdagangan. Selengkapnya, Hiroyosi Kano, Frans Husken, dan Djoko Surjo (ed.), Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20 (Yogyakarta: Akatiga & UGM Press, 1996), 233-257.
[11] Abdul Jalil, Teologi Buruh (Yogyakarta: LKiS, 2008), 69.
Artikel ini juga dimuat pada portal: https://jatim.nu.or.id/read/122-tahun-tebuireng-dan-persandingan-pesantren-dengan-pabrik-gula